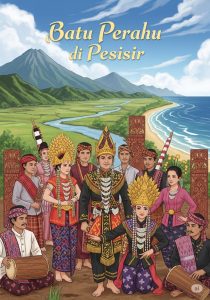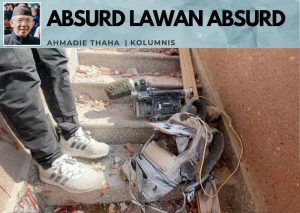Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya
HATIPENA.COM – Bali penuh dengan makna dan lambang. Tak semua yang mampu berarti boleh. Tak semua yang paham berarti pantas.
Pada tanah yang dijaga oleh mantra dan makna, banyak kisah tentang orang yang mampu namun belum boleh.
Mereka telah menyelami kitab suci, hafal ayat dan puja, dueg memantra, piawai metanganan, namun tangannya belum pantas melantunkan doa-doa untuk muput yadnya.
Dalam Hindu Bali, tak semua pemahaman berujung kewenangan. Hanya mereka yang telah didwijati baru boleh muput yadnya. Sementara pinandita, sang pemangku, ada di bawah pandita.
Pemangku hanya diwinten, disucikan dalam pawintenan oleh pandita, diberi tugas mulia menjaga pura, nganteb upacara, menyambungkan doa umat kepada Hyang Widhi.
Batasnya tegas—hanya sampai di situ.
Pemangku tak boleh melangkah lebih jauh, tak boleh muput. Sebab melangkahi batas adalah mencemari kesucian, mencederai upacara, dan menjerat diri sendiri dalam kekeliruan niskala.
Laksana pengemudi handal tanpa SIM—meski fasih mengendalikan motor atau mobil, jika belum sah menurut aturan, ia tak boleh melaju di jalan raya. Apalagi melaju tanpa tahu batas kemampuan.
Simbol-simbol, bhusana, dan gelar pun tak hanya urusan lahir, tapi juga cermin tatanan semesta. Memakai tongkat dan meperucut tak serta-merta menjadikan seseorang sulinggih. Pemangku dibatasi untuk ini. Menyamakan diri dengan memada-mada, bukan sekadar pelanggaran norma, tetapi keretakan dalam keharmonisan dharma.
Saya pernah punya pengalaman di kapal Fery dalam perjalanan ke Bali. Saat itu bertemu seseorang yang mengenakan tongkat, berbusana putih, rambut maperucut layaknya sulinggih.
Saya bingung. Saya tahu orangnya (pemangku), tapi tak pernah mendengar dia didiksa.
Disapa salah, tidak disapa lebih salah lagi. Saya sangat hormat pada pandita apakah Ida Pedanda, Ida Dukuh, Ida Mpu, siapa pun mereka saya harus membungkuk tanda hormat jika bertemu di mana saja, tapi ini siapa? Saya membungkuk pada orang yang tak pantas? Bingung bagaimana menyapa? Dengan sebutan apa disapa? Akhirnya saya memilih menghindar, namun tetap dibuat tidak nyaman.
Hening dan ragu terus menyergap, sebab dunia di hadapan saya menyajikan wajah yang tak seutuhnya jujur.
Lebih mengagetkan lagi, saya mendengar cerita seorang ibu-ibu mengenakan sanggul layaknya sulinggih, menyapa umat dengan senyum pandita, berbhusana selayaknya sulinggih, bahkan mengaku telah didiksa.
Tapi siapa gurunya? Di mana upacaranya? Tak ada yang tahu. Konon dasaran. Dasaran, ya dasaran. Bagi yang percaya silahkan, tapi untuk menjadi sulinggih ada tatanan, ada tata cara, ada diksa pariksa, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Tak bisa mengaku-aku demikian, lalu dipercaya dan disulinggihkan.
Dunia jadi riuh oleh sosok yang seharusnya menentramkan. Sebuah kebingungan lahir dari kemauan yang melangkahi takdir.
Inilah dunia paradoks: ketika seseorang mampu tapi belum boleh. Ketika suara bisa menggetarkan langit, namun belum mendapat restu bumi. Dan, dalam dunia yang masih menjunjung tatanan dharma, kita hanya bisa berharap: semoga yang mampu menunggu saatnya, dan yang belum boleh tak memaksakan kuasa. (*)
Denpasar, 8 Mei 2025