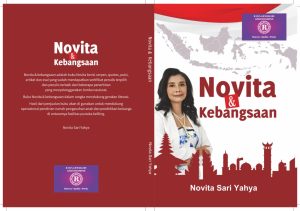Oleh : Ririe Aiko
HATIPENA.COM – Suatu malam, saya menerima sebuah foto. Sekilas, tampak seperti foto biasa—seseorang sedang duduk santai, tersenyum samar ke arah kamera. Tapi malam itu saya terdiam cukup lama. Jantung saya berdegup lebih cepat, tangan saya sedikit gemetar. Wajah di dalam foto itu… mirip sekali dengan almarhum ayah saya.
Begitu miripnya hingga sesaat saya berharap—mungkin itu benar beliau. Mungkin selama ini ia tidak meninggal. Mungkin ia hanya pergi, diam-diam menghilang karena tak tahan menghadapi kerasnya hidup. Ada harapan absurd yang tumbuh, harapan yang sebenarnya saya tahu tak mungkin. Tapi rindu bisa membutakan logika, dan duka yang belum sembuh bisa memunculkan ilusi.
Ayah saya adalah seorang guru. Bukan guru besar dengan gelar panjang dan pendapatan tinggi. Tapi guru di sebuah sekolah kecil, yang lebih sering dibayar dengan sayuran dan ucapan terima kasih ketimbang lembaran rupiah. Ia mengajar dengan sepenuh hati. Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan. Hanya ketulusan yang kadang menyakitkan: karena dalam dunia yang berjalan dengan uang, kebaikan hati saja tak cukup untuk menafkahi satu keluarga.
Nasib baik memang tidak selalu berpihak pada orang baik. Ayah tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit itu datang seperti badai di musim kemarau, menghantam tubuh yang sudah terlalu lelah berjuang sendirian. Dan kami… kami tak punya apa-apa. Bertahun-tahun mengabdi untuk anak-anak negeri, bahkan tak membuat Ayah punya cukup biaya, untuk berobat ke rumah sakit yang layak.
Saya masih duduk di bangku sekolah saat itu. Usia saya terlalu muda untuk kehilangan sosok penopang keluarga, tapi apa daya? Takdir tak pernah datang tanpa rasa iba. Saya harus merelakan kepergian Ayah, tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya masih ingat betul malam-malam panjang yang dipenuhi doa, tangis tertahan, dan harapan kosong tentang masa depan.
Ketika akhirnya ayah pergi, saya tidak hanya kehilangan sosok seorang ayah, tapi juga kehilangan panutan, kehilangan rumah. Dan dunia, rasanya menjadi tempat yang terlalu sunyi dan terlalu sulit untuk saya jalani sendiri.
Tapi dunia tak pernah berhenti, bahkan saat kita ingin diam. Saya tahu, saya tak bisa berlama-lama larut dalam kehancuran. Saya ingat betul—orang kecil tak punya cukup waktu untuk tenggelam dalam duka, karena selalu ada perut yang harus diisi dan hidup yang harus dijalani. Maka, saya pun terus melangkah. Saya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, meski setiap langkah terasa berat, dengan kaki yang tertatih dan hati yang masih hancur lebur.
Saya tumbuh dalam luka dan ketidakadilan. Saya tahu rasanya jadi rakyat kecil yang terjepit sistem. Saya tahu rasanya melihat orang baik dipinggirkan, dilupakan, dan akhirnya harus pergi dalam diam tanpa sempat merasakan penghargaan yang pantas.
Dan malam itu, ketika saya melihat foto itu, semua luka lama menganga kembali. Rasa kehilangan itu seperti gelombang yang datang tiba-tiba, menghantam pantai yang tampak tenang.
Tapi dari kehilangan itu juga, saya menemukan sesuatu. Saya menemukan suara. Suara kecil yang ingin saya pakai untuk menulis, untuk bercerita, untuk menyentuh mereka yang pernah merasa sendiri dalam duka dan putus asa. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, satu tulisan bisa menjadi secercah cahaya. Dan jika cahaya itu bisa menuntun seseorang—satu saja—keluar dari gelapnya nasib, maka saya tahu saya tidak menulis dengan sia-sia.
Saya menulis untuk ayah saya. Untuk semua guru yang terlupakan. Untuk semua anak yang berjuang sendiri di tengah sistem yang tidak adil. Dan untuk dunia yang, saya harap, suatu hari bisa lebih berpihak pada orang-orang pintar yang benar-benar berjuang untuk kebaikan. (*)