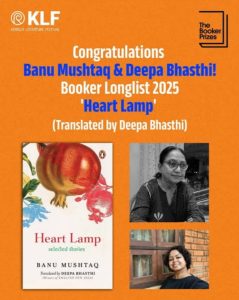Rosadi Jamani
HATIPENA.COM – Pada pagi tanggal 21 Mei 2025, langit Pontianak terasa sedikit lebih terang. Bukan karena cuaca cerah, melainkan karena ada satu momentum besar yang akan menggetarkan ruang pendidikan nasional, pengukuhan Prof. Dr. Agung Hartoyo, M.Pd sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai Matematika. Jangan salah, ini bukan sekadar seremoni akademik biasa yang penuh bunga dan toga lalu dilupakan esok harinya. Ini adalah deklarasi suci, petuah dari altar tertinggi ilmu pengetahuan, yang jika disimak dengan telinga hati bisa membuat batu menangis, dan bahkan kalkulator mengucurkan air mata haru.
Dengan suara yang tenang namun berisi bara, Prof. Agung membuka pidatonya seperti membuka gerbang candi ilmu, “Seandainya pembelajaran pada semua mata pelajaran berlangsung secara holistik-integratif…” Kalimat ini terdengar biasa bagi yang belum mengantuk di seminar-seminar dosen. Tapi jangan salah. Kalimat ini adalah tamparan elegan, sindiran surgawi untuk sistem pendidikan kita yang selama ini terlalu sibuk mengejar akreditasi, sampai lupa bahwa anak-anak bukan mesin fotokopi kurikulum.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 3 sudah dengan sangat jelas menyebut bahwa pendidikan seharusnya menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tapi yang terjadi di lapangan? Alih-alih melahirkan insan utuh, kita justru sibuk memburu angka-angka dan standar nilai minimum, seolah-olah manusia itu bisa diukur dengan rubrik yang sama seperti mengukur panjang tali rafia. Tak heran jika Clint, seorang karakter fiktif dalam game Mobile Legends, sampai harus turun tangan menyuarakan keprihatinannya, “Sopan santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya.” Betul, Bung. Ketika karakter game lebih paham akhlak dari sebagian pemangku kebijakan, itu pertanda ada yang sangat serius sedang tidak beres.
Maka tak heran ketika seorang tokoh publik sekaliber Kang Dedi Mulyadi, yang tampaknya makin hari makin terlihat seperti superhero lokal, memutuskan untuk mengirim 39 siswa nakal dan sulit diatur ke barak militer. Publik pun gempar. Yang pro bilang ini solusi. Yang kontra bilang ini pelanggaran HAM. Yang netral? Masih sibuk menonton sinetron religi yang penuh dialog penuh hikmah tapi tak berdampak pada moral sehari-hari. Namun dalam kaca mata Prof. Agung, tindakan semacam ini bukan hukuman, melainkan pendidikan dalam bentuk yang paling purba dan otentik. Karena karakter tidak bisa diajarkan dengan slideshow PowerPoint dan worksheet LKS. Karakter dibentuk dalam tempaan tekanan, disiplin, interaksi langsung, dan bahkan kelelahan. Ia bukan teori di atas kertas, tapi etika yang tumbuh dari pengalaman nyata.
Apa hubungannya dengan matematika? Nah, inilah bagian yang membuat kita perlu duduk lebih tegak. Matematika, yang selama ini hanya dianggap sebagai ladang rumus dan angka, ternyata adalah medan latihan karakter yang tersembunyi di balik logika-logika formalnya. Menurut Johnson dan Johnson (2009), proses pembelajaran matematika sangat ideal untuk melatih kolaborasi, empati, dan nilai sosial. Bayangkan saja, seorang siswa mengerjakan soal limit yang panjangnya seperti naskah UU, ia butuh ketelitian luar biasa, kesabaran lebih tinggi dari harapan mantan, dan ketabahan dalam menghadapi nilai ulangan yang tak sesuai doa. Lalu, dalam kerja kelompok, ia belajar toleransi, karena selalu ada satu teman yang tak paham-paham walau sudah dijelaskan berkali-kali. Ini bukan sekadar belajar angka, ini belajar menjadi manusia.
Prof. Agung merujuk Soedjadi, yang menyebut bahwa pembelajaran matematika itu adalah proses membentuk nilai-nilai karakter: ketelitian, konsistensi, sikap sistematis, dan berpikir runtut. Jika kita bisa menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, maka kita tak perlu lagi membuat ribuan spanduk ‘Tingkatkan Karakter Bangsa’. Karena karakter akan tumbuh diam-diam, seperti akar yang menghujam tanah, tidak terlihat, tapi menopang bangunan kokoh di atasnya.
Tidak berhenti di situ, pendekatan integratif juga menyentuh teknologi dan game. Menurut penelitian Supratman, Sutajaya & Suja (2023), pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep-konsepnya dengan kehidupan nyata dan teknologi terkini akan jauh lebih bermakna. Game edukatif, aplikasi, dan teknologi digital bukan musuh, tetapi justru bisa menjadi guru alternatif yang efektif. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, di mana konsentrasi anak-anak lebih kuat untuk scroll TikTok daripada memahami pecahan biasa, guru harus lebih kreatif daripada algoritma media sosial.
Namun di balik semua strategi itu, inti dari pidato ini bukan sekadar metode atau pendekatan. Intinya adalah: pendidikan karakter bukan bonus, bukan tambahan, dan bukan sisipan yang boleh dihapus saat jam pelajaran kepotong. Ia adalah roh dari pendidikan itu sendiri. Sebuah bangsa bisa tetap tegak walau miskin teknologi, tapi tidak akan pernah bisa berdiri jika karakter manusianya runtuh. Kita bisa hidup tanpa kalkulus, tapi tidak bisa hidup dalam masyarakat tanpa integritas.
Prof. Agung Hartoyo telah membuka lembaran baru. Ia tidak hanya mengajar rumus, tapi menyulam jiwa. Ia tidak hanya menulis artikel jurnal, tapi menulis ulang arah pendidikan bangsa. Dalam dunia pendidikan yang sering terasa seperti labirin tanpa peta, pidatonya hari ini adalah kompas moral yang mengingatkan kita, bahwa mendidik bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi menyalakan hati.
Jika nanti ada anak bertanya, “Pak, mengapa saya harus belajar matematika?” Maka jawablah seperti seorang guru sejati: “Karena dari sanalah kamu belajar bukan hanya menghitung, tapi juga memahami dunia, dan menjadi manusia.”
Begitulah. Di ujung pidato itu, kita tidak hanya melihat seorang guru besar sedang dikukuhkan. Kita sedang menyaksikan harapan sedang dibangkitkan, lewat angka-angka yang bicara tentang nilai, dan rumus-rumus yang ternyata menyimpan cinta. (*)