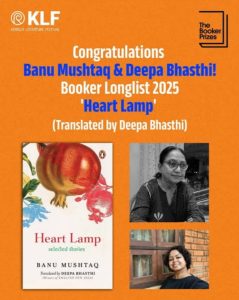Catatan Paradoks; Wayan Suyadnya
HATIPENA.COM – Penari itu muda. Matanya kosong. Geraknya gemulai, tapi ada luka di sela-sela lengkung tangannya.
Di bawah panggung, tawa meledak, sorakan menggema, dan selembar uang melayang seperti janji—cepat, ringkih, menjatuhkan harga diri lebih cepat dari denting kendang.
Itulah Joged hari ini. Tarian rakyat yang dulu lahir dari keriangan muda-mudi, kini seperti tumbuh duri di tangkainya.
Joged Bumbung, yang dulu sederhana dan jenaka, kini tergelincir menjadi joged jaruh—tarian yang menyelipkan syahwat dalam elognya yang angkuk-angkuk.
Siapa yang membutuhkannya?
Pertanyaan itu bergema seperti lonceng sunyi di kepala para budayawan, seniman, dan siapa pun yang masih punya cinta pada warisan.
Tapi jawabannya pahit: tarian itu tetap dipanggil, tetap diundang, tetap ditonton. Itu pula yang menyebabkan joged jaruh sulit ditiadakan. Ada yang butuh. Siapa? Jangan-jangan di antara kita ada yang menyukainya.
Penari hanya menjalankan pesanan. Ia bukan pencipta joged jaruh—ia hanya perpanjangan tangan dari pasar, dari penabuh yang genit memainkan nada agar penarinya angkuk-angkuk yang diikuti pengibing yang naik ke panggung sambil menuntut goyangan yang lebih liar.
Jika tidak ada yang memesan, siapa yang akan menari seperti itu?
Jika tidak ada yang menabuh musik sensual itu, bagaimana mungkin tubuh itu akan angkuk-angkuk seperti kehilangan arah?
Jika tidak ada pengibing yang menyuruh, merayu, memaksa, siapa yang akan rela menukar harga dirinya hanya untuk mendapat aplaus?
Mereka semua—pemesan, penabuh, pengibing—adalah panggung sesungguhnya dari joged jaruh. Penari hanyalah korban yang ditampilkan. Wajah yang menerima tamparan dunia, semua seakan ditanggung olehnya, semua seakan ia mendapatkannya, sementara yang lain bersembunyi di balik layar.
Lalu datang solusi yang setengah hati. “Buat saja komitmen,” kata otoritas. “Buat janji agar penari tak menari cabul,” seru pengamat.
Tapi siapa yang bisa menjamin? Kalau penari A menolak, bagaimana dengan penari B yang butuh makan? Kalau si B menolak, ada penari C yang tak sempat membaca janji itu.
Mereka banyak. Mereka bukan satu, dua. Mereka semua hidup dari panggung yang terus menggoda. Bahkan dia, si penari yang mendapat hujatan itu, yanh dicap jaruh, menghidupi panggung itu sendiri. Jika tak menari, penabuhnya pun tak megamel. Tak megamel, tak mendapat upah.
Menekan penari untuk berubah tanpa menyentuh akar masalah, seperti menambal perahu bocor dengan kertas doa.
Tak akan berhasil. Karena selama masih ada pasar yang butuh joged jaruh, selama masih ada irama yang memancing syahwat, selama masih ada pengibing yang menuntut pertunjukan erotik—tarian itu akan tetap hidup, meski kita memejamkan mata.
Maka, solusinya bukan pelarangan. Bukan persekusi diam-diam. Bukan menekan yang lemah.
Solusinya adalah literasi. Literasi untuk penabuh, agar tahu bahwa nada bisa menyelamatkan atau menjerumuskan.
Literasi untuk masyarakat, agar paham bahwa joged bukan panggung untuk menertawakan martabat.
Literasi untuk penari, agar tahu bahwa tubuh mereka bukan milik siapa-siapa, dan mereka punya hak untuk menari dengan harga diri.
Dengan literasi, joged akan kembali menjadi milik semua. Milik remaja Bali yang menari karena cinta, karena ngayah, karena riang, bukan karena buang, apalagi cemas tak bisa makan.
Milik ibu-ibu yang menonton sambil tertawa bangga, bukan canggung karena anak-anak mereka bertanya kenapa penarinya goyang aneh, angkuk-angkuk? Tari Bali tak ada angkuk-angkuk, ngelog itu ke samping, dengan rasa, dengan khidmat, dengan indah, bukan liar angkuk-angkuk depan-belakang.
Joged itu milik semua, yang menjunjung seni, bukan menukar harga diri dengan hiburan murah. Joged harus kembali. Bukan dengan goyangan, tapi dengan kebanggaan.
Dan, semua harus ikut bertanggung jawab. Karena joged jaruh tak akan pernah lahir kalau kita tak pernah memintanya. Jaruh tak pernah ada jika kita tak butuh. (*)
Denpasar, 21 Mei 2025