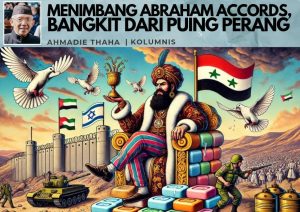Oleh Mila Muzakkar
(Sekretaris Forum Kreator Era A)
(Catatan dari Acara Dermakata Award 2025 dan makan siang bersama Esther Haluk).
HATIPENA.COM – “Jika suaramu hanya menghantam tembok tuli,
menggesek hati yang membatu karena ketamakan,
tikam dan hujamkan belati, dan robek nuraninya dengan penamu.”
Sepotong puisi Esther Haluk dalam buku “Nyanyian Sunyi” itu dibacakan Denny JA pada pemberian Dermakata Award 2025 kategori fiksi—sebuah penghargaan tahunan oleh Forum Kreator Era AI (KEAI)—yang diberikan kepada Esther Haluk, Senin, 19 Mei 2025.
Pantas saja kata-kata kuat itu lahir sebab, Denny JA menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua adalah terendah dari wilayah lain di Indonesia. Sekitar 18,09% orang Papua masuk dalam kategori miskin. Hal ini menjadi paradoks di tengah besarnya kekayaan alam di Papua.
Kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan itulah yang mendorong seseorang bersuara dan melawan dengan pena dan sastra. Esther Haluk salah satunya. Melihat ketidakadilan di tanah kelahirannya, perempuan ini tak tinggal diam. Dalam buku kumpulan puisinya, ia ingin menghujam belati dan merobek nurani para tuan yang tak lagi memakai hati.
Sejak kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Esther t’lah menumpahkan kegelisahan-kegelisahannya dengan pena dan kertas.
Tulisan-tulisan itu berceceran di mana-mana, di Salatiga hingga di Wamena, tempat kelahirannya. Tak berani ia beberkan tulisan-tulisan itu meski darahnya hampir berhenti mengalir, dan air matanya kering, menyaksikan penderitaan di bumi Cenderawasih.
Penderitaan menjadi orang Papua ia tuliskan dalam salah satu puisinya di bawah ini:
“Menjadi Papua tra gampang, kawan!
Banyak bangsa yang datang menghisap kekayaanmu,
Namun mereka diam melihat ketidakadilan di atas tanahmu.
Mereka sibuk menggrogoti dan mengeruk tiap jengkal tanahmu
Namun sama sekali tak gubris sedu-sedanmu.
Jika kau ingin tahu seperti apa rasanya di mana tamu berlagak menjadi tuan rumah,
Nyawa hanya dihargai dengan selembar rupiah
Negeri di mana hukum rimba menjadi the golden rules,
Sudah tepat kau injakkan kakimu di sini.”
(kutipan puisi Esther Haluk, “Menjadi Papua”)
Perempuan dan Luka
Malam itu, Esther tak lagi bisa menahan keingintahuannya terhadap peristiwa yang berulang di keluarganya. Sejak kecil, ketika keluarganya berkumpul, Esther dan anak kecil lainnya akan diminta masuk kamar. Lalu mereka, para orang tua saling bercerita, dan selalu berakhir dengan tangisan.
Ketika duduk di bangku SMA, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Esther akhirnya mendengar juga kisah kelam tentang saudara jauhnya yang secara bergilir diperkosa oleh TNI, di hadapan suaminya sendiri.
Pengalaman traumatis dan operasi militer yang tak pernah berhenti memaksa keluarga Esther mengungsi hingga ke perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia.
Telinga Esther hampir pecah. Hatinya bergemuruh. Sejak itulah, ia berteriak lewat pena, lewat puisi. Sebab perempuan adalah korban yang paling banyak menyimpan luka yang hingga kini tak pernah disembuhkan oleh negara.
Di mana-mana perempuan memang mengalami peminggiran, diskriminasi, dan ketidakadilan. Tapi menjadi perempuan di Papua lebih sadis. Bebannya berlapis-lapis. Selain praktik budaya patriarki yang masih kental, perempuan direpresi secara struktural dari atas hingga bawah, tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, juga tak berpartisipasi di sektor publik. Adapun sedikit perempuan yang aktif dalam aktivitas ekonomi hanya cukup untuk makan dan minum belaka.
Kumpulan luka perempuan itu selama ini hanya mengendap di dalam. Tak ada yang berani mengungkapnya. Sebab rasa takut itu lebih besar. Para penguasa itu lebih beringas.
Hingga Aprila Wayar, perempuan kelahiran Jayapura, memulainya. Dialah novelis perempuan pertama yang berani menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan yang masif dilakukan aparat di Papua, melalui novelnya, Mawar Hitam Tanpa Akar (terbit 2009). Aprila pula yang pertama kali membaca puisi-puisi Esther, dan mendorongnya untuk menerbitkannya menjadi buku.
Memberontak Lewat Puisi
Meski banyak luka di pundaknya, Esther memilih bangkit dan melawan, lewat tulisan dan gerakan perempuan. Melalui West Papua Feminist Forum yang ia dirikan, di sanalah konsolidasi dan gerakan kolektif perempuan diperkuat.
Di Gereja, Esther juga hadir memberi pelayanan. Pada perempuan-perempuan di lingkungan Gereja, Esther hadir mendengar dan menguatkan suara-suara mereka.
Dalam acara pemberian Dermakata Award 2025 yang berlangsung di kantor LSI Denny JA, Esther menyampaikan keharuan dan rasa terima kasihnya atas penghargaan itu. “Ini menjadi ‘beban’ dalam arti positif untuk saya terus menyuarakan keadilan lewat tulisan,” ucapnya.
Aku yang turut hadir dalam acara itu, juga ikut berbagi tentang kekuatan tulisan yang mampu menggugah pembaca melalui puisi esai. Dalam buku puisi esai “Karena Perempuan, Aku Di-Cancel”, aku mengangkat luka-luka perempuan yang menyayat hati. Mereka adalah perempuan korban terorisme, perempuan bercadar yang diperkosa di rumah Tuhan, perempuan yang bunuh diri karena terjerat pinjaman online, hingga pekerja seks komersial (PSK) yang membawa anaknya saat melayani tamu di kamar hotel.
Bagi kami para perempuan yang menulis, pada tulisan-tulisan itu, kami teriakkan pemberontakan. Goresan pena itu adalah pengingat bahwa sebesar apa pun upaya mereka membungkam, nurani dan gerakan kami jauh lebih besar. Sebab kami adalah hati, telinga, kaki, dan tangan mereka yang merindukan keadilan sosial. (*)
Depok, 21 Mei 2025