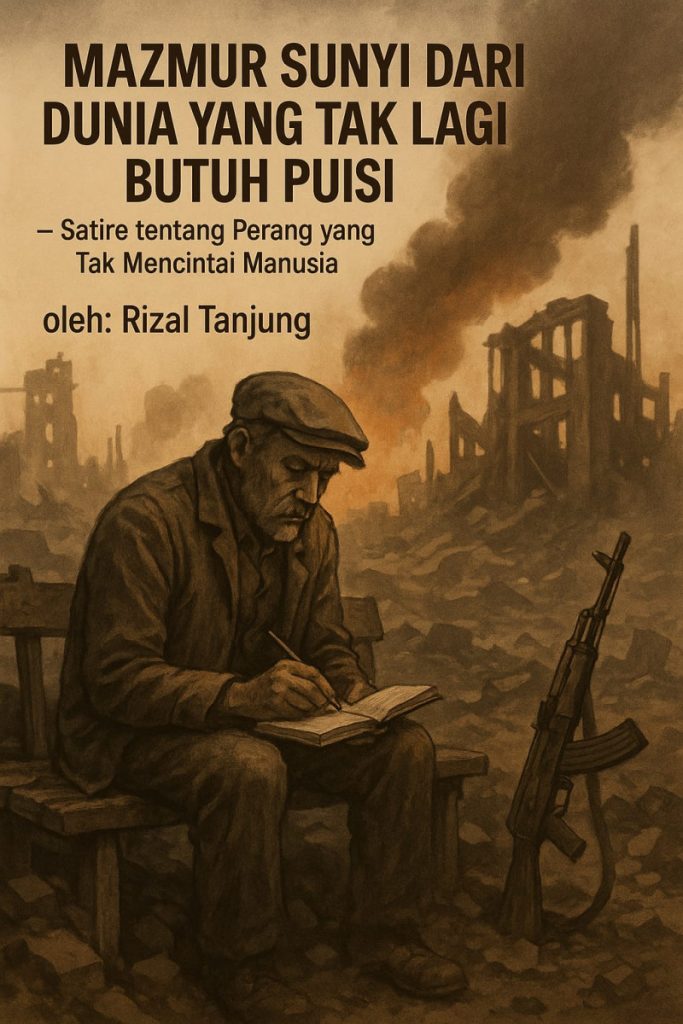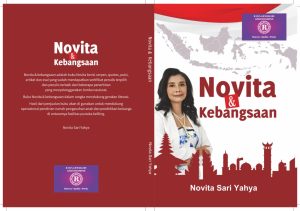— Satire tentang Perang yang Tak Mencintai Manusia
oleh: Rizal Tanjung
Wahai engkau,
penyulam kata di tengah artileri,
yang masih percaya bahwa sajak dapat membungkam senapan,
mari duduk di bangku puing peradaban,
di mana mimpi telah hangus,
dan doa tinggal jejak karbon
di langit yang dibakar kontrak-kontrak militer.
Puisi?
Ah, saudaraku,
itu hanya debu harum
di meja-meja jenderal yang bersulang
dengan darah petani dan tangis anak-anak.
Sementara mereka menertawakan statistik korban,
kau masih sibuk menimbang irama luka
di antara rima-rima yang dilupakan sejarah.
Perang bukan tentang benar atau salah.
Ia tentang lisensi—
siapa yang memiliki saham di pabrik neraka,
siapa yang boleh siarkan derita menjadi tontonan utama,
siapa yang paling piawai mengubah nyawa
menjadi angka yang nyaman dibacakan
di forum ekonomi global.
Dan kita?
Kita hanya para penjaga nyala kecil,
diberi pena, bukan rudal.
Diberi hujan kata, bukan markas senjata.
Puisi kita tak pernah berhasil menghentikan genosida,
tak sanggup menutup luka di punggung dunia.
Tuhan pun,
jika boleh jujur,
telah lama dijadikan juru bicara resmi
bagi mereka yang membakar masjid dan gereja
atas nama langit yang diklaim sepihak.
Kita hanya bisa menulis
tentang seorang ibu yang kehilangan anak
sebelum sempat menjadi pemberontak,
tentang sepetak tanah yang dirampas,
bukan demi surga,
tapi demi konsesi tambang
yang lebih menggiurkan dari cinta itu sendiri.
Puisi, saudaraku,
adalah bunga duka yang diam-diam mekar
di liang lahat nurani global.
Ia tak bisa menggigit,
tak bisa menembus kevulgaran zaman,
tapi ia tumbuh—
sebagai isyarat bahwa masih ada yang percaya
manusia bukan robot dengan sistem operasi kebencian.
Mereka akan terus berperang.
Sebab kekuasaan adalah makhluk lapar
yang tak pernah kenyang oleh air mata.
Kehormatan mereka adalah tiruan murahan
yang dijahit dari kulit orang-orang lemah.
Mereka takut dicintai,
dan lebih memilih ditakuti—
sebab cinta menuntut kerentanan,
dan itu adalah musuh terbesar dari mesin kekuasaan.
Kita?
Kita hanya bisa menyalakan lilin kecil,
dan lilin itu pun kerap padam
ditiup propaganda yang berseragam kebenaran.
Namun teruslah menulis,
sebab mungkin,
di ujung zaman nanti—
ketika peluru kehabisan suara,
dan tangisan jadi satu-satunya bahasa universal,
dunia akan datang padamu
bukan untuk meminta senjata,
tapi sepotong puisi yang bisa dijadikan bantal
di malam paling gelap,
ketika tak ada lagi bendera yang layak dikibarkan,
dan tanah air hanyalah kenangan dalam selimut luka. (*)
Sumatera Barat, 2025