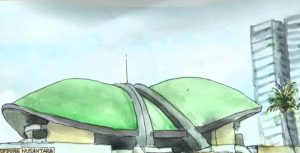Albertus M. Patty
HATIPENA.COM – Ada ironi besar dalam diri Immanuel Ebenezer. Sebenarnya dalam namanya ada makna yang sangat dalam. Immanuel artinya Allah beserta kita. Ebenezer, batu pertolongan. Saat kedua kata digabung berarti Allah beserta kita, Dialah batu pertolongan! Pelakon drama politik ini dipanggil: Noel.
Ironis bahwa sosok yang dulu dielu-elukan sebagai relawan merakyat, pembela buruh, dan pengusung moral anti-korupsi, kini jatuh dalam pelukan KPK. Noel ditelanjangi oleh fakta: kekuasaan bukan dipakai untuk melayani, melainkan untuk memperkaya diri.
Machiavellian
Machiavelli pernah menulis bahwa seorang penguasa harus mampu menyulap wajahnya: tampak penuh kasih, tetapi keras di dalam; tampak bermoral, tetapi siap mengkhianati moralitas saat kekuasaan terancam. Noel mempraktikkan itu dengan telanjang. Dari Jokowi Mania, beralih ke Ganjar Mania, lalu mendirikan Prabowo Mania. Jelas, Noel bukanlah pejuang garis lurus. Dia seperti pengendara Gojek yang berjalan zig-zag mencari ‘jalan tikus’ untuk menemukan jalur tercepat menuju lingkaran kuasa.
Dalam perspektif Machiavelli, Noel bukanlah pengkhianat. Ia justru murid yang patuh: memahami bahwa loyalitas sejati bukan pada rakyat, melainkan pada peluang dan pada kekuasaan itu sendiri. Ia tahu, rakyat mudah dipikat dengan retorika moral, tetapi kuasa hanya bisa diraih lewat kedekatan dengan mereka yang sedang berkuasa. Noel seorang realis tulen, tetapi yang dalam bahasa nurani disebut oportunis.
Pedagang Politik
Noel bukan hanya pemain individual. Ia adalah bagian dari orkestra besar para politisi opportunis yang memanfaatkan narasi ‘relawan’ sebagai alat hegemoni. Saya teringat pada Gramsci yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya berdiri di atas paksaan, tetapi juga pada kemampuan membangun persetujuan rakyat melalui bahasa dan simbol.
Relawan adalah simbol itu: suara rakyat jelata, suara keadilan, suara perubahan. Noel memainkannya dengan mahir. Dia membentuk JoMan, Ganjar Mania, hingga Prabowo Mania. Setiap kali nama “mania” itu digelorakan, rakyat merasa sedang berbicara. Elite penguasa pun dikelabui karena merasa telah berhasil menggenggam suara ‘akar rumput’. Padahal, suara itu hanyalah gema dari ruang kosong. Relawan bukan lagi gerakan moral, melainkan kendaraan dagang politik. Noel tahu itu, dan ia menjualnya dengan cerdas.
Narasi yang seolah pro-rakyat itu akhirnya runtuh di hadapan barang bukti mobil-mobil mewah dan motor Ducati. Disinilah wajah asli hegemoni terkuak: yang disebut “suara rakyat” ternyata hanyalah topeng bagi transaksi elite.
Demokrasi yang Luka
Fenomena Noel bukan sekadar kisah seorang individu yang terjerat korupsi. Ia adalah cermin buram demokrasi kita. Presiden gagal memilih pembantu yang bermoral. Partai gagal melahirkan kader berintegritas, relawan berubah jadi broker kekuasaan, dan pejabat publik menjadikan jabatan sebagai pasar gelap rente. Parah sudah luka demokrasi kita!
Saya bayangkan, Machiavelli akan tersenyum dan berkata: begitulah hukum besi politik, tujuan selalu menghalalkan cara! Saat yang sama, Gramsci mungkin menghela napas: hegemoni berhasil membius rakyat, hingga mereka bertepuk tangan ketika kekuasaan sedang mencuri.
Bagi kita, yang tersisa adalah luka yang makin busuk dan bernanah, serta sebuah tanya: sampai kapan kita membiarkan suara rakyat dijadikan topeng, dan kekuasaan dijadikan alat memperkaya diri? (*)
Bandung, 22 Agustus 2025