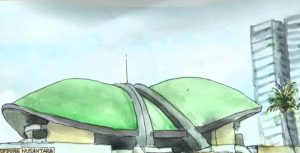Catatan Paradoks; Wayan Suyadnya
HATIPENA.COM – Hari ini, kesibukan warga Bali mulai memuncak. Galungan sudah di depan mata. Hari ini disebut penyajaan galungan.
Jalanan ramai, pasar sesak, aroma bumbu dapur bercampur keringat para ibu yang berburu kebutuhan upacara.
Sejak kemarin di setiap sudut desa, terdengar suara kapak dan gergaji memotong bambu, tangan-tangan cekatan merangkai janur menjadi penjor yang anggun menjulang.
Namun di balik gegap gempita itu, dunia paradoks tersingkap pelan-pelan.
Ini bukan keluhan. Merainan adalah kewajiban sakral, bukan beban yang boleh digugat. Tetapi, bukankah setiap kewajiban juga perlu direnungkan?
Di sinilah tulisan ini menjadi “nyuh daksina” yang airnya bisa dijadikan tirta penawar, bukan untuk menghilangkan rasa, tapi untuk menjernihkan pikiran kita.
Penjor, simbol kemenangan, berdiri gagah di depan gerbang rumah mengungkapkan rasa syukur atas karunia Ida Hyang Widhi Wasa.
Tapi bolehkan kita mendiskusikannya? Satu batang penjor bisa berharga Rp325 ribu, bahkan teman bilang yang agak bagus mencapai Rp500 ribu. Saya kira cukup dengan seratus ribuan. Harga kelapa daksina yang dulu Rp5 ribu –7 ribu, kini melonjak Rp20 ribu. Bumbu dapur, buah-buahan, janur, semua ikut naik.
Intinya, merainan kali ini berada di tengah meroketnya harga-harga: kenyataan empiris yang terjadi hari ini.
Ini baik menjadi perenungan bagi panglingsir, tokoh umat, dan kita semua terutama oleh pengambil kebijakan; bagaimana mungkin umat Hindu menjalankan kewajiban spiritualnya jika terus dibebani ongkos yang tak sepadan dengan kemampuan?
Upacara bagi gama Bali bukan hanya Galungan. Ada Kuningan, Nyepi, Odalan, Ngaben, Ngenteg Linggih, dan upacara lainnya.
Ada yang diselenggarakan secara pribadi, ada juga secara komunal: oleh dadia, banjar, dan desa adat.
Di sinilah paradoks menjadi lebih dalam. Dalam ruang komunal, tak ada si kaya dan si miskin. Semua sama rata dalam iuran dan kewajiban. Sama rasa, tapi tidak sama derita. Ternyata, sama itu tidak selalu adil.
Lalu muncul istilah “sumbangan sukarela”, tapi disebut sebagai “wajib”. Sukarela yang dipaksakan, menjadi paksarela. Tanpa sanksi, tapi menekan secara sosial.
Di sinilah rasa kekeluargaan berbalut paradoks.
Tak hanya uang, waktu pun menjadi mahal. Dalam masyarakat industri, waktu adalah penghasilan. Seorang sopir atau pemandu wisata bisa kehilangan sejuta sehari jika absen demi upacara.
Jika hidup sebagai masyarakat agraris, waktu bisa dikelola lebih lentur. Tapi kini, waktu adalah mata uang, bukan lagi sekadar jarum jam yang berotasi.
Siapa yang bertugas mengingatkan? Bukan untuk menghapus upacara, bukan pula menghilangkan kewajiban, tapi menghidupkan kembali esensi upacara itu sendiri.
Guru spiritual, para Pandita, sudah waktunya bersuara. Konsep Sisya-Surya—murid dan guru—harus dihidupkan, agar upacara tak kehilangan arah, agar kembali pada esensinya dan umat tak kehilangan tenaga sia-sia.
Dadia, banjar, krama pura termasuk desa adat jangan hanya mengurus parahyangan, tetapi juga memperhatikan pawongan dan palemahannya.
Apa gunanya pura megah jika rakyatnya terjerat kemiskinan? Pawongan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dan ironi besar terjadi saat kemiskinan justru dicap karena upacara itu sendiri.
Jika tanah-tanah dijual, jika palemahan berubah fungsi, lama-lama bukan hanya palemahannya yang hilang, tetapi desa adatnya yang beralih fungsi; ini tak boleh terjadi.
Banjar, dadia dan desa adat harus menjaga ketiganya: parahyangan, pawongan, dan palemahan.
Sementara cerdik pandai dan akademisi harus merakyat dan turun dari menara gading. Jangan mengajarkan “agama baru” yang membingungkan umat dengan dalih modernitas. Hindu bukan untuk dikonversi menjadi “Hindu” tapi Hindu harus dipahami. Apa yang dijalankan masyarakat Bali bukan versi rendah dari Hindu, melainkan ruh lokal yang penuh kearifan.
Paradoks adalah bagian dari dunia. Tapi kita bisa mengelola paradoks itu dengan nalar, cinta, dan spiritualitas yang jernih.
Mari kita megalungan bukan hanya sebagai kemenangan dharma atas adharma, tapi juga kemenangan kesadaran, kemenangan cara berpikir.
Rahajeng Galungan; semoga semua berbahagia. (*)
Penyajaan, 21 April 2025