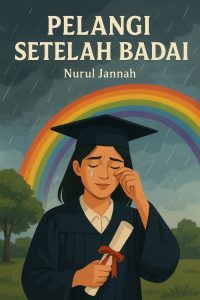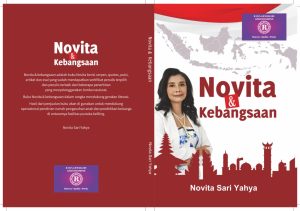Catatan Paradoks; Wayan Suyadnya
HATIPENA.COM – Dulu, pergi ke dokter adalah ritual yang jelas: disuntik. Tidak ada suntikan, berarti belum ke dokter.
Suntik itu tanda sah sebuah pengobatan. Kalau tidak disuntik, maka pulang dengan perasaan: belum benar-benar berobat.
Dokter tidak banyak bicara. Lihat, periksa, suntik. Lalu diberi obat—langsung dari tangan dokter.
Obat minum, salep, atau bubuk pahit dalam kertas minyak.
Dan yang dibayar pasien adalah itu semua: obat suntik, obat minum, obat oles. Transaksi yang konkret. Uang ditukar obat.
Itu dulu, tapi kini? Semua berubah. Ke dokter tak lagi identik dengan disuntik. Bahkan menyentuh obat pun tidak. Dokter hanya memeriksa, lalu menulis resep.
Resep dibawa ke apotek, obat dibayar di sana. Jadi, apa yang dibayar pasien saat ke dokter? Jasa. Hanya jasa. Jasa menatap wajah pasien dan menuliskan resep yang hanya bisa dibaca apoteker.
Dan di sanalah letak ganjalan besar itu: banyak pasien merasa belum benar-benar berobat. Karena tak disuntik, tak menerima obat dari tangan dokter.
Mereka hanya pulang dengan selembar kertas dengan resep yang harus dibawanya ke apotek.
Berat membayar jasa yang tak berwujud, apalagi jika penyakit tak kunjung sembuh. Seringkali muncul keluhan klise namun tajam: “Sudah ke dokter, sudah minum obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh?”
Ketika sains tak memuaskan, mistik pun membuka pintu. Pasien beralih ke dukun.
Cukup diberi air putih, dibacakan mantra. Diminum—lalu pasien merasa sembuh.
Dan herannya, membayar dukun terasa lebih ringan, dibanding membayar jasa dokter, barangkali karena ada ‘bukti fisik’: air dan doa.
Paradoks pun mencolok di situ. Dokter—yang ilmunya didapat dari bertahun-tahun pendidikan ditambah pengalaman—dikalahkan oleh dukun yang kadang tak tamat sekolah dasar.
Belakangan, tak hanya dukun yang mengancam profesi yang mulia itu. Datanglah AI. Kecerdasan buatan, tak punya gelar, tapi punya jawaban cerdas.
Pasien cukup mengetik: “Saya pusing.” AI menjawab: “Kemungkinan migrain ringan. Coba cari obat ini.” AI menjelaskan dosis, efek samping, bahkan kandungan senyawa.
Lengkap. Logis. Gratis. Tis.
Apotek, karena sistemnya sudah berubah, memberikan obat itu juga—tanpa perlu resep dokter.
Lalu, untuk apa dokter? Untuk apa jasa yang tak lagi tampak?
Saat dunia beralih ke kecerdasan sintetis, dokter bukan hanya bersaing dengan dukun, tapi juga dengan algoritma.
Namun ada yang lebih paradoks. Di tengah ancaman AI dan dukun, di tengah profesi dokter tergerus, fakultas kedokteran tetap jadi rebutan.
Biayanya yang selangit tak menyurutkan minat menjadi dokter. Universitas berlomba membuka jurusan kedokteran, yang tumbuh seperti jamur di musim hujan.
Kenapa? Karena menjadi dokter masih menjanjikan gengsi. Menjadi dokter, menaikkan status sosial. Tak hanya secara personal, keluarganya pun jadi terhormat.
Dokter adalah penyembuh. Profesi yang dianggap mulia, bahkan melebihi guru atau dosen. Guru membuat kita pintar, tapi dokter menyelamatkan hidup.
Di mata masyarakat, yang menyembuhkan lebih agung dari yang mengajarkan.
Akankah kemuliaan itu bertahan? Guru dan dokter—dua profesi luhur—kini sama-sama digerus zaman. Digerus oleh teknologi yang tanpa wajah, tanpa gelar, tanpa bayar, tapi serba tahu.
Masihkah ada yang rela membayar ratusan juta rupiah untuk mengejar gelar menjadi dokter, saat diagnosis pintar bisa diberikan oleh AI, dan kesembuhan dirasa dari air doa dukun?
Zaman terus berjalan. Teknologi tak pernah menunggu. Dan kita, lagi-lagi, terlambat bertanya: apa yang tersisa dari profesi, saat kepercayaan tak lagi dibayar mahal? (*)
Denpasar, 12 Mei 2025