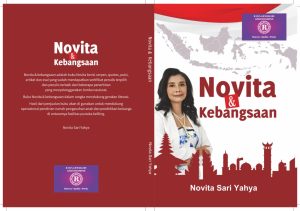Oleh: Wahyu Iryana *)
HATIPENA.COM – Penulis sebagai bagian dari rakyat perlu menyampaikan kritik membangun terkait Gaji DPR 100 Juta perbulan, yang tentu tidak sesuai dengan kinerja, ini tidak pas dengan kondisi rakyat Indonesia yang masih serba kekurangan ekonomi.
Kalau Mahbub Djunaedi masih hidup, mungkin ia akan menulis: “Di negeri ini ada dua manusia: yang hidup dari keringat, dan yang hidup dari rapat.” Orang kedua itu sering datang terlambat, rapatnya lebih banyak hening daripada gagasan, namun gaji selalu tepat waktu bahkan dobel kalau “maraton” dianggap merampungkan selfie, bukan legislasi. Sementara itu, rakyat masih berjuang membayar harga pokok, menikmati subsidi seadanya, dan berharap digaji setidaknya cukup untuk sehari.
Mari kita mulai dengan angka. Gaji pokok anggota DPR RI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 memang hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan kini naik 3 juta perhari. Tapi itu juga hanyalah ujung dari piramida penghasilan mereka. Tambahkan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan komunikasi, uang sidang, biaya perjalanan, hingga tunjangan pensiun, total pendapatan yang bisa dibawa pulang anggota DPR berkisar 100 juta per bulan.
Bahkan jika dihitung rata-rata, mereka bisa mendapat sekitar Rp3 juta per hari. Angka ini fantastis bagi banyak rakyat Indonesia yang untuk mendapatkan Rp100 ribu sehari saja harus bergelut di jalanan.
Si Budi, misalnya, seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Dalam sehari, ia bisa mendapat Rp160 ribu, itupun belum dipotong bensin, parkir, dan servis motor. Bersihnya? Mungkin Rp80 ribu–100 ribu. Jika bulan berjalan baik, ia mengantongi Rp3–4 juta sebulan. Atau petani buruh di Indramayu misalkan yang hanya mengais upah kalau hanya ada kerjaan itupun hanya diupah 100 ribu sehari kerja empat hari kemudian nganggur lagi hari berikutnya.
Bahkan gaji ASN yang sering dikambinghitamkan masyarakat pada umumnya tidak sebesar gaji para anggota dewan terhormat yang ada di senayan, nelayan yang melaut harus membayar solar yang kadang tak berimbang dengan hasil tangkapan. Sementara anggota DPR yang duduk di kursi gedung ber-AC bisa dapat angka 3 juta dalam satu hari atau bahkan tanpa kerja jika kebetulan masa reses.
Kesenjangan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal etika dan simbolisme politik. Di satu sisi, rakyat diimbau untuk hidup hemat dan “turut berjuang bersama pemerintah”, namun di sisi lain, para elit menikmati tunjangan luar negeri, fasilitas hotel bintang lima untuk reses, hingga dana representasi yang kadang tak jelas urgensinya. Ketika harga beras melambung, rakyat diminta “bersabar”. Ketika tunjangan pejabat naik, disebut sebagai “penyesuaian anggaran”.
Di sini, “fairplay” tampaknya hanya berlaku di pidato, bukan dalam praktik. Subsidi BBM dikurangi atas nama efisiensi fiskal, tetapi dana kunjungan luar negeri justru membengkak. Harga bahan pokok melonjak, tetapi tunjangan komunikasi anggota DPR mencapai lebih dari Rp15 juta. Ironi ini lebih absurd dari sinetron: satu pihak sibuk mengais receh di pasar, satu pihak sibuk mencairkan dana aspirasi yang lebih sering jadi safari politik.
Secara historis, ketimpangan elite dan rakyat bukan hal baru di negeri ini. Pada masa kolonial, golongan priyayi dan pegawai pemerintahan Hindia-Belanda menikmati gaji dan fasilitas tinggi sementara kaum bumiputra hidup miskin dan tertindas. Harapan akan tatanan baru muncul pasca kemerdekaan bahwa republik berarti kesetaraan. Namun yang terjadi? Budaya feodalisme ternyata tidak runtuh, hanya berganti seragam dan institusi.
Mari sedikit melihat refleksi historis, sidang-sidang BPUPKI dan PPKI dulu berlangsung sederhana. Para perumus konstitusi datang dengan semangat pengorbanan, bukan daftar tagihan reimbursement. Bung Karno hidup dalam kesederhanaan, dan Bung Hatta bahkan menolak tunjangan demi integritas, bahkan banyak mentrinya yang mengontrak rumah sampai akhir hayatnya. Bandingkan dengan hari ini, ketika anggota DPR bisa menerima fasilitas kredit mobil Rp70 juta per periode, apartemen mewah, hingga pensiun seumur hidup meski hanya menjabat lima tahun.
Dalam sejarah pemikiran politik Indonesia, tokoh seperti Anhar Gonggong pernah mengingatkan bahwa bangsa yang tidak belajar dari sejarah akan mengulang penderitaannya. Dan Ahmad Mansyur Suryanegara menegaskan bahwa Indonesia tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keikhlasan rakyat untuk berjuang, lapar, bahkan mati demi tanah air. Namun kini, demokrasi kita justru menjauh dari rakyat.
Parlemen telah menjadi semacam “monarki konstitusional”: rakyat memilih, elite menikmati. Demokrasi berubah menjadi pasar transaksional, di mana suara rakyat hanya dibutuhkan lima tahun sekali, lalu dilupakan selama sisa masa jabatan. Legislasi disusun tergesa, minim partisipasi publik, dan kadang tak berpihak pada keadilan sosial. Rapat molor, reses tidak terdokumentasi dengan baik, dan laporan kinerja sulit diakses publik.
Ini bukan lagi sekadar soal gaji besar, tapi soal struktur kekuasaan yang permisif terhadap kemewahan tanpa akuntabilitas. Ketika anggota DPR lebih sibuk membahas fasilitas ketimbang nasib petani dan buruh, maka demokrasi kita sedang mengalami krisis legitimasi. Ketika rakyat dibiarkan menonton dari pinggir lapangan yang becek, sementara wakilnya bermain di lapangan rumput Swiss, maka pertandingan ini tidak adil sejak peluit ditiup.
Jika ini pertandingan sepak bola, maka rakyat adalah tim yang diberi bola kempes, disuruh bermain tanpa sepatu, dan tidak diberi hak bicara pada wasit. Sementara anggota DPR main di lapangan hijau, dengan pelatih luar negeri, fasilitas lengkap, dan skor sudah ditentukan dari awal.
Maka wajar jika rakyat mulai sinis. Mereka bukan anti terhadap gaji besar. Mereka hanya ingin keadilan. Gaji besar boleh saja, asalkan berbanding lurus dengan kerja besar. Tapi kenyataannya, banyak anggota DPR lebih aktif di media sosial ketimbang di ruang sidang. Banyak yang lebih lihai membuat konten TikTok daripada meneliti undang-undang. Rakyat tak marah pada kemewahan, mereka marah pada ketidakadilan yang sistemik.
Apa solusinya?
Pertama, reformasi menyeluruh sistem penggajian dan tunjangan anggota legislatif. Tunjangan harus berbasis kinerja nyata, bukan sekadar jabatan. Tidak ada rapat? Tidak ada uang sidang. Tidak hadir reses? Potong dana aspirasi.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas anggaran legislatif harus diperkuat. Semua pengeluaran dari tiket pesawat hingga biaya hotel harus dilaporkan secara daring dan terbuka, bisa diakses rakyat secara real-time.
Ketiga, pendidikan politik massal untuk rakyat. Rakyat harus diberi akses untuk menilai rekam jejak wakilnya, memahami proses legislasi, dan punya saluran pengawasan. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi soal terus mengawasi dan menagih janji.
Keempat, batasi gaya hidup elitis pejabat publik. Jika perlu, wakil rakyat wajib hidup satu minggu di kampung miskin, makan dengan upah minimum, dan merasakan antrean beras subsidi. Agar mereka kembali merasakan denyut nadi rakyat yang sesungguhnya.
Demokrasi Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi reality show: mahal, dramatis, penuh sorotan kamera tapi kosong makna. Demokrasi bukan tentang fasilitas mewah untuk pejabat, tapi tentang bagaimana negara hadir dalam dapur rakyat, sekolah rakyat, dan puskesmas rakyat.
Jika wakil rakyat terus hidup dalam dunia paralel yang nyaman dan steril dari derita rakyat, maka akan tiba masa di mana suara rakyat tidak hanya disampaikan lewat pemilu, tapi lewat amarah kolektif. Dan sejarah sebagaimana diajarkan oleh Anhar Gonggong tidak pernah memberi ampun pada penguasa yang lupa daratan.
Indonesia adalah rumah bersama, bukan ruang VIP bagi segelintir elit. Sudah saatnya kita tuntut agar demokrasi tidak hanya jadi sandiwara lima tahunan, tapi sistem yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat yang sesungguhnya. Wakil rakyat harus kembali menjadi pelayan rakyat bukan penikmat uang negara.
Jika tidak, maka demokrasi jet pribadi akan terus melaju, meninggalkan rakyat yang berjalan kaki dengan sandal jepit di jalan berlubang, sambil bertanya: Apakah ini republik yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata?tentu bukan! Karena memimpin adalah menderita kata Agus Salim sang Diplomat Ulung yang pernah dimiliki Bangsa Indonesia.
Ingat para bapa ibu anggota DPR yang terhormat audit rakyat semesta lebih konkret daripada audit badan resmi pemerintah sekalipun. Itu di dunia, belum lagi audit keadilan di akherat kelak. (*)
Wallahu’alam.
*) Penulis adalah sejarawan yang percaya bahwa pena rakyat bisa lebih tajam daripada hasil rapat DPR