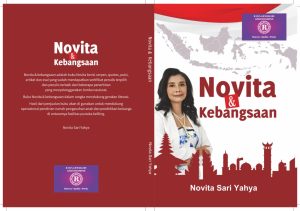Oleh ReO Fiksiwan
“Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dapat mengatur tempat kerjanya secara lebih fleksibel dan berorientasi pada kelompok, dengan lebih banyak tanggung jawab yang didelegasikan ke tingkat organisasi yang lebih rendah.“ — Francis Fukuyama (72), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995).
HATIPENA.COM – Sebuah negeri yang nyaris uzur, punya pengalaman panjang dan penuh kucuran keringat dan darah warga, tak dengan sendirinya negeri ini tinggi demokrasi dan meritokrasi dalam tata kelola negaranya.
Untuk mengujinya, kita hanya butuh dua figur yang bikin perut warga mual-mual dan kepalanya mendadak migran.
Wamen Naker, Imanuel Ebenezer Gerungan, ditangkap tangan oleh KPK—lembaga yang kini lebih sering tampil sebagai cameo dalam drama politik ketimbang aktor utama pemberantas korupsi.
OTT itu bukan lagi kejutan, melainkan semacam rutinitas nasional, seperti hujan di bulan Desember atau janji kampanye yang tak pernah ditepati.
Satu lagi, pun baru dalam sejarah negeri ini, mantan presiden yang konon katanya berasal dari rakyat jelata, kembali menjadi sorotan publik.
Bukan karena prestasi gemilang atau warisan kebijakannya yang visioner, melainkan karena tuduhan ijazah palsu yang tak kunjung reda.
Ironisnya, sang tokoh yang tampak kalem dan konteoversi, rupanya gemar menikmati sorotan itu dengan gaya megalomania yang tak kalah dari diktator-diktator tua dan raja-raja tua dulu kala.
Paska turun dari tahta, ia masih tampil di panggung politik seperti bintang utama yang tak rela pensiun, meski naskahnya sudah usang dan penonton mulai bosan.
Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity menekankan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi dari masyarakat yang sehat.
Tapi di sini, kepercayaan publik telah direduksi menjadi komoditas politik—diperjualbelikan, dipalsukan, dan dipakai sebagai alat kosmetik untuk menutupi borok para pejabat publik dalam banalitas kekuasaan.
Para pejabat publik kita bukan lagi penjaga etika, melainkan badut-badut yang sibuk berdandan untuk mempertahankan citra, bukan integritas.
Mereka pun tak segan membayar konsultan publik plus buzzer demi kosmetik banal posisi mereka.
Michel Foucault barangkali akan rontok lagi kulit plontos kepalanya dan kacamata naik minus 10 melihat bagaimana kekuasaan di negeri ini tak lagi beroperasi lewat disiplin atau pengawasan, melainkan lewat bebalisme absurd.
Kekuasaan menjadi semacam pertunjukan, di mana logika dan moralitas ditanggalkan demi mempertahankan narasi dengan norma palsu.
Mereka yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi simbol dari banalitas karakter: berkuasa tanpa kapasitas, berpengaruh tanpa kredibilitas.
Mengacu pada Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963), dikutip: “Kejahatan berasal dari kegagalan berpikir. Ia menentang pikiran… Itulah banalitas kejahatan.“
Arendt menekankan bahwa kejahatan besar bisa dilakukan oleh orang biasa yang tidak berpikir secara mendalam tentang tindakan mereka.
Dalam konteks kekuasaan, ini berarti bahwa sistem birokrasi atau otoritas bisa melahirkan kejahatan jika individu di dalamnya berhenti berpikir secara moral dan hanya patuh pada aturan atau perintah.
Krisis public trust bukan sekadar soal korupsi atau ijazah palsu. Ini adalah refleksi dari sistem yang telah kehilangan kompas moralnya.
Arendt menyebutnya: the banality of evil. Ketika pejabat publik lebih sibuk membangun dinasti daripada membangun bangsa, ketika jabatan menjadi warisan keluarga dan bukan hasil kompetensi, maka publik tak punya alasan lagi untuk percaya.
Kita hidup dalam zaman di mana satire bercampur komedi menjadi kenyataan, dan kenyataan terlalu menyebalkan untuk jadi tuntunan. Antara lucu dan konyol mbulat logikanya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti berharap pada para pejabat yang hanya pandai berpose di depan kamera dan mulai membangun kembali kepercayaan dari bawah.
Karena jika krisis ini terus dibiarkan, maka yang tersisa hanyalah reruntuhan kepercayaan, di mana publik tak lagi peduli siapa yang memimpin, karena semua tampak sama: banal, sarkastik, dan ironis.
Dan “sesal mana yang mesti disesali?” Toh, banyak di antara mereka putus urat malu dan yang tinggal moralitas berkulit badak dan berlidah komodo. (*)
#coversongs: Genesis, Dancing with the Moonlit Knight (1973).