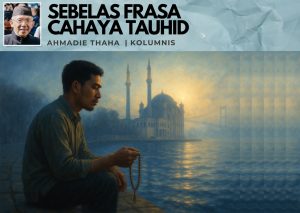Narudin Pituin
HATIPENA.COM – Kehadiran Sutardji Calzoum Bachri di atas panggung sastra Indonesia pada tahun 1970-an cukup heboh karena si penyair eksentrik ini ingin mengembalikan kata kepada mantra. Salah satu kredo andalannya ialah “kata-kata bukanlah alat untuk mengantar pengertian”. Apabila demikian halnya, hal itu secara tak langsung melanggar prinsip dikotomi struktural Ferdinand de Saussure (1988), yakni penanda (signifier) dan petanda (signified).
Jadi, kredo puisi Sutardji bertentangan dengan prinsip dasar Semiotika bahwa setiap kata membawa arti dan setiap gabungan kata membawa makna. Dalih Sutardji mengembalikan kata kepada mantra tak berlaku bagi puisi bagus yang mengutamakan kesempurnaan dimensi bahasa, sastra, dan filsafat—yang saya istilahkan dengan “trikotomi puisi yang bagus”.
Setiap tanda membawa penanda sekaligus petanda, mirip dengan selembar kertas yang terdiri dari halaman muka (penanda) dan halaman belakang (petanda). Kertas itu sendiri ialah tanda. Maka, jika Sutardji berkata bahwa kata-kata (penanda) bukan alat untuk mengantar pengertian (petanda), ucapan ini sudah tidak sahih sebagai kredo-nya karena bersifat kontradiktif (bertentangan) di dalam dirinya sendiri atau diistilahkan dengan contradictio in terminis.
Dengan demikian, kredo Sutardji itu pada dasarnya tidak meyakinkan sebab mantra itu sendiri sebenarnya “ingin bermakna”. Hal penting ini harus diperhatikan secara saksama dalam rangka pembicaraan tentang perkembangan puisi kontemporer Indonesia yang sering kali terlupakan hingga saat ini.
Kemudian, membaca puisi-puisi seorang kritikus sastra Indonesia senior, Maman S. Mahayana, yang menerbitkan buku kumpulan puisi perjalanannya, berjudul Jejak Seoul (2016), kumpulan puisi tahun 2009-2014, menarik. Menarik karena kita dapat melihat kemampuannya dalam menulis puisi (salah satu jenis karya sastra). Seorang teoretikus Barat berkata bahwa puisi ialah karya sastra tersulit karena sangat kompleks. Oleh karena itu, kita tentu dapat melihat kecerdasan seseorang lewat puisi-puisinya.
Demikian pula ketika kita membaca puisi-puisi Maman dalam buku puisinya ini: ungkapan yang terlalu langsung, tak disaring secara ketat, dan terlampau asyik dengan pengalamannya sendiri di Seoul. Jadi, buku puisi Maman ini hanya sejenis laporan perjalanan yang masih bersifat komunikatif, tidak puitis, serta cenderung boros kata-kata.
Saya selalu berharap Maman menerbitkan buku puisi kedua yang lebih menunjukkan kemahirannya dalam menulis karya sastra (dalam hal ini minimal buku puisi bagus). Bukankah seorang kritikus sastra harus memiliki identifikasi diri dengan bukti karya sastra bagusnya sebelum mengkritik karya sastra orang. Kata wartawan senior, Yurnaldi, apabila kritikus tak berkarya sastra bagus, maka runtuhlah kekritikusannya.
2019—2025
-0-
Biodata Singkat
Narudin Pituin ialah sastrawan, penerjemah, dan kritikus sastra. Karya sastra, terjemahan, esai dan kritik sastranya dimuat di Kompas, Tempo, Media Indonesia, Majalah Sastra Horison, Majalah Basis, Pikiran Rakyat, dan banyak lagi di dalam dan luar negeri.
Buku puisinya berjudul Di Atas Tirai-tirai Berlompatan (2017) menjadi pemenang Anugerah Puisi CSH 2018 dan dua buku puisi terjemahan bahasa Inggrisnya mendapat penghargaan tingkat internasional.
Buku-buku terbarunya berjudul Sintesemiotik: Teori dan Praktik (2023), Sastra Indonesia dalam Sastra Dunia: Kumpulan Esai dan Kritik Sastra (2023), Sang Nabi Al-Muqaffi (novel, 2022), dan Kuntilanak Monru (kumpulan cerpen, 2024).
Alamat FB/IG/TikTok/Youtube: Narudin Pituin. Nomor kontak WA: 0821-271-207-29.