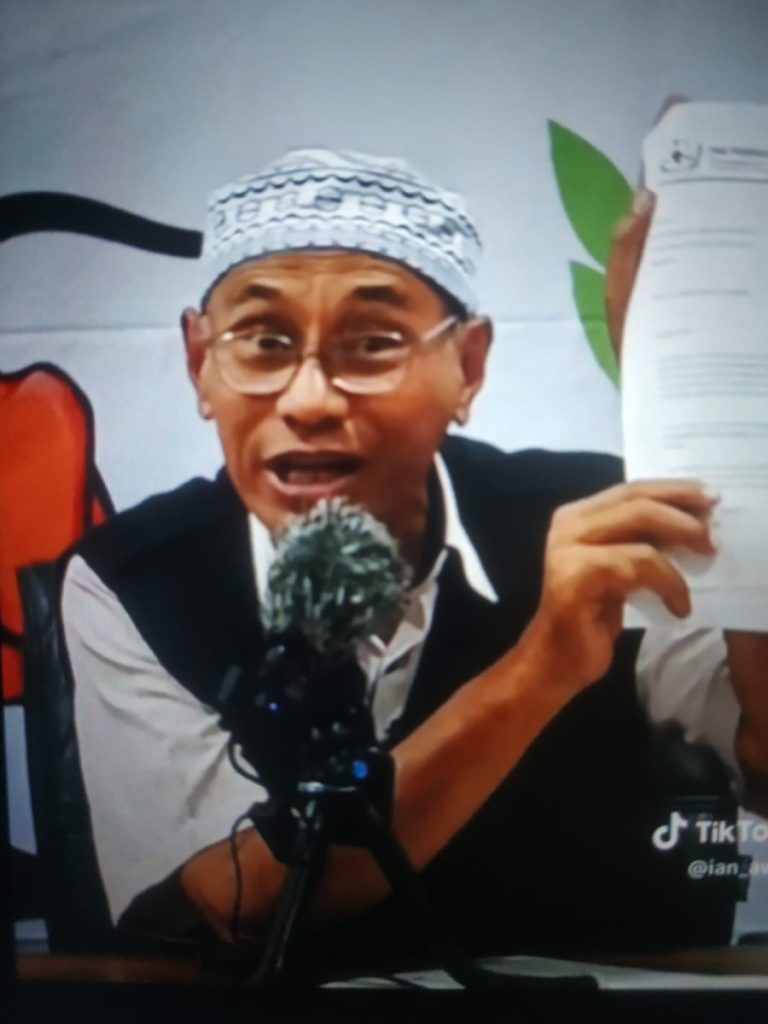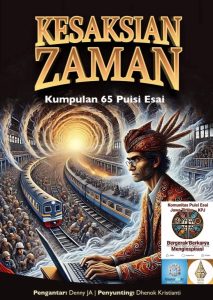Catatan Satire; Rizal Pandiya
Sekretaris Satupena Lampung
HATIPENA.COM – Di tengah musim halal bihalal dan ketupat dengan opor ayam yang sudah beku di dalam freezer, sekelompok warga negara yang terguncang keimanannya pada dunia fotokopian, tengah bersiap melakukan ritual paling sakral dalam demokrasi kita pada 15 April 2025.
Ini persoalan serius. Saking seriusnya, polemik ijazah Joko Widodo, kini muncul ritual baru yang bisa disebut sebagai ziarah ijazah. Tujuannya kampus UGM. Penggagasnya bukan sembarang orang. Namanya Simon Hasiholan Sianipar—bukan fans band metal, tapi idenya cukup hardcore dalam menuntut transparansi. Simon ini bukan kaleng-kaleng. Dia ahli forensik digital, alumni UGM dan mencari ilmu koding sampai ke Jepang. Kelihatannya, dia sudah kenyang baca metadata file PDF, bukan sekadar status WhatsApp.
Kegelisahan Simon bukanlah kegelisahan pribadi. Ia adalah gema dari keresahan kolektif bangsa—kebatinan rakyat yang capek ditipu Jokowi dengan senyuman dan pencitraan dengan bansos dan lempar-lempar T-Shirt dari dalam mobil dinasnya.
Bagaimana mungkin seorang presiden bisa mengelabui begitu banyak tahapan pemilu, dari Pilwalkot Solo dua periode, Pilgub DKI Jakarta, sampai Pilpres dua kali, tanpa ada satu pun panitia yang sadar ijazahnya bisa jadi cuma hasil crop-an Photoshop?
Dan yang lebih menyayat, sebagai alumni UGM, Simon pasti merasa kampusnya jadi korban scandal by association. Nama besar almamaternya kini ikut tercoreng gara-gara sosok yang dia anggap niretika dan nirmoral. Maka, niat ziarah itu bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi juga bentuk eksorsisme akademik—mengecek apakah ijazah itu asli atau palsu.
Kita tahu, Universitas Gadjah Mada (UGM), kampus terkemuka yang katanya melahirkan banyak pemimpin bangsa—dan mungkin juga melahirkan mitos-mitos akademik, salah satunya bernama Joko Mulyono alias Joko Widodo.
“Ini bukan main-main. Ini pencarian kebenaran. Kami ingin melihat ijazah aslinya, bukan hasil laminating fotokopi di belakang kampus,” ujar salah satu tokoh gerakan, sembari membawa pembesar layar dan senter seperti tim CSI.
Rektor UGM, seorang ibu dengan jabatan resmi tapi dengan kemampuan melihat ijazah yang masih setara warga biasa, sebelumnya sempat menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli adanya. Tapi, belakangan terungkap bahwa yang dilihat sang rektor bukan ijazah asli, melainkan fotokopian yang viral itu juga.
Sebagai pembanding, ijazah versi fotokopi tersebut kini juga beredar di handphone anak-anak yang hobi bolos sekolah karena keranjingan game online.
Masalahnya, jurusan “Teknologi Kayu” yang tertera di ijazah… masih jadi misteri di UGM. Kayu-kayu di fakultas kehutanan pun mengeluh, merasa difitnah. “Kami tidak pernah merasa ditempuh oleh seorang Joko Widodo,” ujar pohon jati yang jadi maskot lulusan 1985.
Lebih mencurigakan lagi, saat halal bihalal alumni Fakultas Kehutanan lulusan ‘85 berlangsung meriah, hanya dua yang tidak hadir, yaitu yang sudah wafat dan yang bernama Joko Widodo. Lucunya, tidak seorang pun yang merasa kehilangan teman. Padahal kalau benar dia satu angkatan, minimal masuk grup WA alumni dan disuruh jualan kaos reuni dong.
Dan misteri baru kembali muncul. Saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo, gelar akademiknya adalah Drs.—gelar umum lulusan fakultas sosial atau pendidikan. Namun kini, gelarnya menjadi Ir., seorang insinyur perkayuan dari jurusan yang tidak jelas keberadaannya.
Kucing aja bingung. Mau disebut insinyur, tapi waktu jadi pejabat awal nggak pernah pakai gelar itu. Tiba-tiba saat jadi presiden, berubah jadi insinyur. Gelar itu bukan kayak akun media sosial, yang bisa diganti sewaktu-waktu sesuai suasana hati.
Tapi yang paling menggelitik adalah soal foto di ijazah itu sendiri. Biasanya, dalam aturan resmi kampus dan negara, foto untuk ijazah harus bersih dan rapi: tidak memakai topi, tidak memakai atribut partai, apalagi kaca mata.
Tapi aneh bin ajaib, di ijazah milik mantan presiden yang paling banyak disorot itu – ia malah pakai kaca mata. Memang jabatan bapaknya apa, sampai mendapatkan privilege memakai kaca mata untuk ijazah?
Lalu, sejak kapan Joko Widodo pakai kacamata? Selama menjabat dua periode, tampil di ratusan pidato, rilis video dari Istana, sampai foto keluarga… nihil, bro. Matanya sehat wal’afiat, menatap masa depan anaknya untuk jadi Wapres tanpa lensa bantuan.
Ini jadi misteri besar. Apakah dia sempat jadi brand ambassador optik lokal tapi tidak terekspos media? Atau jangan-jangan… foto itu hasil pinjam muka dari alumni lain? Yang difotokopi cuma mukanya, lupa diganti nama.
Rakyat yang kepo, mulai memperhatikan bentuk hidung dalam foto ijazah tersebut. Kok… lebih mancung? Kok… agak tirus? Kok… kayak bukan dia?
Seorang pakar estetika digital menyimpulkan bahwa foto tersebut bisa saja melalui proses penghalusan visual atau bahkan penukaran wajah. “Biasanya terjadi jika seseorang lupa bawa pas foto, lalu pinjam pas foto temennya yang kebetulan mirip-mirip,” ujar dia sambil tertawa getir.
Dan di tengah kegaduhan ini, sorotan kini tertuju pada sosok penting di kampus kerakyatan, yaitu Prof. dr. Ova Emilia, Rektor UGM.
Sebagai pemegang kunci gerbang akademik, banyak pihak mendesaknya untuk mengambil langkah berani, yaitu mengundang Pak Joko Widodo langsung ke kampus, sekalian reuni, temu alumni, dan kalau perlu buka lemari arsip bersama-sama dengan Simon Hasiholan Cs, di depan publik.
“Ya kalau memang ijazahnya asli, kenapa harus main kucing-kucingan terus?” kata seorang warga yang rela akan cuti kerja untuk ikut rombongan safari pencarian bukti.
Dibanding jadi buronan dari alumni sendiri, Jokowi seharusnya bisa hadir, duduk manis berdampingan dengan para pencari kebenaran, disuguhi teh panas, dan menjawab pertanyaan sambil menunjukkan ijazah—bukan hasil scan, bukan hasil fotokopi, tapi yang berbau map-folder dan bertekstur kertas tebal.
Biar semuanya terang. Biar nggak ada lagi yang merasa negara ini dijalankan oleh seseorang yang ijazahnya seperti Pokemon langka—banyak yang percaya, tapi tak pernah ada yang benar-benar melihat langsung.
Tentu, acara itu bisa jadi sejarah baru dalam dunia pendidikan, “UGM Transparency Day 2025”. Acara bisa saja digelar di Balairung, dibuka dengan pembacaan puisi oleh alumni, dilanjutkan sesi live verifikasi ijazah, dan ditutup dengan tanya jawab ala town hall—syaratnya, tidak boleh bawa batu, hanya boleh bawa argumen.
Masyarakat pun menanti, apakah Prof. Ova akan memilih jalur konstitusional, atau tetap bertahan dalam posisi “percaya tanpa perlu melihat”, seperti kisah-kisah spiritual pada umumnya. (*)