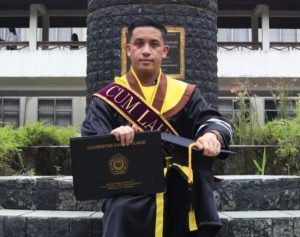Oleh ReO Fiksiwan
“Kamp adalah ruang yang dibuka ketika keadaan darurat mulai menjadi aturan.” — Giorgio Agamben (83), Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998).
HATIPENA.COM – Dalam panorama politik kontemporer Indonesia yang makin menyerupai panggung „standup comedy“ absurd, buku terbaru Dr. dr. Taufiq Pasiak MKes., MPdi., SH hadir seperti palu Thor yang menghantam kesadaran kolektif kita.
Dilaunching pekan silam (18/8/25) dalam perayaan syukuran Komisaris Independen BSG, Ir. Djafar Alkatiri, MM., MPdi, dan dihadiri Dirut BSG, Revino Pepah SE.MM, buku ini bukan sekadar refleksi spiritual-neurosains, melainkan semacam eksorsisme intelektual terhadap praktik politik yang telah lama kehilangan ruhnya.
Politik Ruci —yang dalam bahasa Manado berarti menipu, triki, manipulatif, flas (dusta) —dikontraskan secara tajam dengan praktik cuci otak yang dilakukan oleh para politisi terhadap publik, media, bahkan terhadap diri mereka sendiri.
David Runciman (58), political scientist asal Inggris, pernah menulis bahwa demokrasi modern adalah sistem yang memungkinkan kebohongan menjadi alat kelangsungan hidup politik: political hypocrisy.
Dalam konteks Indonesia, kebohongan itu bukan lagi sekadar alat, melainkan telah menjadi identitas dan rutinitas.
Para politisi tampil dengan “muka ruci“, berbicara tentang moral, agama, dan keadilan, namun di balik layar mereka mengoperasikan mesin cuci otak yang bekerja 24 jam: menggiring opini, memanipulasi persepsi, dan menanamkan narasi palsu yang dikemas dalam jargon populis.
Mereka bukan lagi pemimpin, melainkan operator algoritma sosial yang mengerti bahwa kebenaran bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang bisa direproduksi berulang-ulang.
Giorgio Agamben, filsuf politik asal Italy, telah mengurai tentang “homo sacer“, kodrat manusia yang bisa dikorbankan tanpa konsekuensi hukum.
Sebaliknya, kodrat homo sacer itu berbalik 360% dalam kasus Noel, ijazah palsu, Tom Lembong dan Hasto.
Agamben menunjukkan bahwa dalam biopolitik modern, kekuasaan tidak lagi sekadar mengatur hukum, tetapi mengatur kehidupan itu sendiri—termasuk bagaimana manusia berpikir, merasa, dan memahami eksistensinya.
Di sinilah praktik “cuci otak” politik menemukan resonansinya: ketika negara atau penguasa menciptakan kondisi di mana kesadaran publik dibentuk oleh narasi kekuasaan, bukan oleh kebebasan berpikir.
Dalam politik Indonesia, rakyat telah lama menjadi homo sacer: dikorbankan dalam proyek-proyek kekuasaan, dijadikan objek eksperimen kebijakan, dan dirayu dengan janji-janji palsu yang tak pernah dimaksudkan untuk ditepati.
Para politisi, dengan senyum ruci dan retorika surgawi yang sangat paradoks, menjadikan rakyat sebagai ladang cuci otak massal.
Ibarat keharusan menelan pil murtibing dalam novel politik, The Captive Mind (Zniewolony umysł,1953) dari Czesław Miłosz.
Mereka tahu bahwa dalam masyarakat yang lelah dan bingung, yang dibutuhkan bukanlah kebenaran, melainkan kenyamanan.
Dan kenyamanan itu dijual dalam bentuk propaganda, subsidi sesaat, dan pencitraan spiritual yang dangkal.
John Eccles (1903-1997), dalam buku neurosainsnya, Das Gehirn und das Ich (1984) —peraih Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran tahun 1963, bersama Alan Hodgkin dan Andrew Huxley —menunjukkan bahwa kesadaran manusia bukan sekadar hasil dari aktivitas neuron, tetapi juga dari interaksi dengan realitas yang bermakna.
Namun dalam politik kita, makna telah digantikan oleh simulakra.
Kesadaran publik dibentuk bukan oleh fakta, tetapi oleh impresi.
Para politisi memahami bahwa otak manusia lebih mudah dipengaruhi oleh emosi daripada logika.
Maka mereka mengemas kebijakan dalam drama, bukan dalam data. Mereka mengatur narasi seperti sutradara sinetron, bukan seperti negarawan.
Buku Dr. Taufiq Pasiak, “Manipulasi Dan Cuci Otak Dalam Politik Indonesia: Perspektif Neurosains dan Psikologi Politik” (2025), adalah tamparan filosofis yang menyadarkan kita bahwa spiritualitas bukanlah kosmetik politik, melainkan fondasi etis yang harus menjiwai setiap tindakan kekuasaan.
Namun dalam praktiknya, spiritualitas telah direduksi menjadi alat cuci otak: digunakan untuk membungkus ambisi, menyamarkan korupsi, dan menenangkan nurani yang seharusnya memberontak.
Politik Ruci, political manipulation, yang sejatinya adalah politik tipu-tipu, kini menjadi politik pencucian: bukan mencuci kotoran, tetapi mencuci kesadaran agar tetap tunduk dan tidak bertanya.
Dalam dunia yang makin mirip laboratorium manipulasi, kita perlu bertanya: apakah kita masih memiliki daya kritis untuk membedakan antara ruci dan cuci?
Ataukah kita telah menjadi bagian dari eksperimen besar, di mana otak kita bukan lagi milik kita, melainkan milik mereka yang tahu cara mengendalikan impuls, memanipulasi citra, dan mengatur narasi?
Jika politik adalah seni kemungkinan, maka politik ruci adalah seni keberanian untuk mengatakan yang tak nyaman.
Dan jika cuci otak adalah seni penghapusan makna, maka tugas kita adalah menjadi pengganggu: mempertanyakan, mengganggu, dan menolak tunduk pada narasi yang terlalu rapi untuk menjadi nyata. (*)