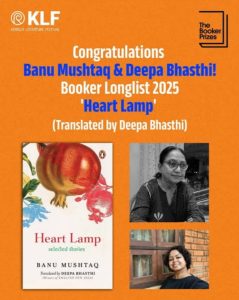Oleh: Rizal Tanjung
HATIPENA.COM – Puisi “Pipiet Senja” yang ditulis pada 21 Mei 2025 di RSUI, merupakan sebuah karya sastra yang meledak dengan semangat perlawanan, kepedihan, dan solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Melalui gaya bahasa yang ekspresif, repetitif, dan penuh kekuatan metaforis, puisi ini menjadi medium perlawanan non-fisik yang menggugah nurani kemanusiaan global. Puisi ini bukan sekadar untaian kata, tetapi teriakan kolektif atas tragedi yang terus berulang—sebuah nyala api solidaritas yang menyala dari balik luka.
Struktur dan Gaya Bahasa: Retorika Perlawanan
Puisi ini dibangun dengan pola repetisi dan teriakan retoris yang memperkuat intensitas emosionalnya. Kalimat “Berikan kami senjata, wahai dunia” diulang dalam beberapa bait, menjadi semacam mantra perlawanan dan harapan. Ini bukan permohonan biasa, tapi jeritan dari lorong luka kolektif—dari anak-anak Gaza, dari para ibu yang menjadi simbol kekuatan dan kehilangan sekaligus.
Gaya bahasa dalam puisi ini sangat langsung, tidak mengandalkan simbolisme rumit, tapi justru menyentuh dengan kejujuran puitis yang telanjang. Pemilihan kata seperti “Menyembur peluru,” “melempar duka,” “tiada puas bantai bayi-bayi kami” adalah bentuk konkretisasi penderitaan yang disampaikan tanpa filter, menjadikannya seperti peluru yang juga menghantam nurani pembaca.
Birruh Biddam: Lirik Perlawanan dan Iman
Frasa “Birruh biddam, ya Aqsa / ya Gaza / ya Palestina”—yang berarti “Dengan darah, dengan nyawa, wahai Aqsa/Gaza/Palestina”—berulang dalam puisi ini sebagai semacam zikir perjuangan. Frasa ini berasal dari teriakan massa dalam aksi solidaritas Palestina di berbagai belahan dunia, dan diadopsi dalam puisi sebagai pengikat spiritual dan emosional antara puisi dan realitas politik.
Repetisi ini menjadikan puisi seperti nyanyian protes dan doa dalam satu tarikan napas. Ia menegaskan bahwa perjuangan Palestina bukan hanya fisik, tetapi spiritual. Bahwa tanah itu bukan sekadar wilayah, tapi warisan para Nabi—“Palestina, tanah air warisan para Nabi”.
Figur Perempuan dan Anak: Simbol Luka dan Daya Hidup
Dalam puisinya, Pipiet Senja menghadirkan tokoh ibu dan anak secara kuat:
“Agar tangan-tangan mungil di Gaza menyandang sangkur…”
“Agar ibu-ibu perkasa melempar duka…”
Anak-anak dan ibu bukan hanya korban, tetapi juga pengusung semangat perlawanan. Mereka bukan lagi figur pasif, tetapi hadir sebagai subjek perjuangan yang penuh daya. Ini menciptakan gambaran bahwa revolusi tidak hanya milik prajurit bersenjata, tetapi juga mereka yang paling terdampak oleh kekejaman.
Puncak dan Ledakan Emosi: Bait Penghabisan
Menuju akhir puisi, kemarahan memuncak, dan sekaligus transenden:
“Wajah-wajah bengis temperasan dari kerak neraka: Laknatatullah!”
Seruan laknat adalah ledakan emosional yang tak bisa dibendung. Namun, sekaligus, puisi ini ditutup dengan pernyataan penuh keyakinan:
“Kami melawan dan menang
Allahu Akbar!”
Keyakinan ini bukan klaim retoris belaka, tetapi cermin dari harapan yang disandarkan pada iman—bahwa meski tertindas, Palestina tak pernah tunduk. Ada Allah yang menjaga bumi para Nabi.
Pipiet Senja: Dari RSUI untuk Dunia
Fakta bahwa puisi ini ditulis di RSUI (kemungkinan saat penyair sedang dirawat atau mengunjungi pasien) menambah lapisan makna eksistensial. Di tengah ruang yang biasa menjadi tempat pengobatan fisik, penyair menulis puisi sebagai pengobatan luka batin dunia. RSUI bukan lagi hanya ruang medis, tapi altar sunyi tempat doa dan amarah dituangkan dalam bait.
Puisi Sebagai Perlawanan Moral
“Pipiet Senja” bukan hanya karya sastra, tapi manifestasi kepedulian moral yang dijalin dengan kekuatan kata. Ia menggambarkan bagaimana bahasa bisa menjadi senjata paling tajam untuk membela kebenaran, bagaimana puisi bisa menjadi tempat berpijak bagi yang tak bersenjata.
Di tengah dunia yang sering diam, puisi ini hadir sebagai saksi dan sakralitas perjuangan. Ia menolak lupa. Ia menolak tunduk. Ia berteriak: “Lihatlah, wahai dunia yang masih senyap!” (*)
Sumatera Barat ,2025
Catatan: Pipiet Senja, dalam tradisi penyair pejuang, menempatkan dirinya dalam barisan mereka yang menggunakan pena sebagai peluru, dan puisi sebagai medan juang.