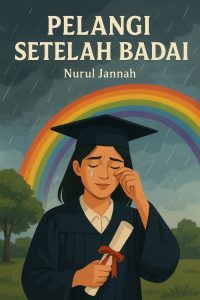Oleh ReO Fiksiwan
“Artinya kita memiliki aturan dan nilai yang sama, namun tetap saja berbeda. Islam tidak memiliki gagasan ini. Dan Islam juga tidak memiliki tradisi toleransi.” — Bassam Tibi(81).
HATIPENA.COM – Sebagai seorang ilmuwan politik dan penulis terkenal kelahiran Suriah, Bassam Tibi alumnus dua PhD di dunia universitas Jerman dalam ilmu politik, pantas dirujuk untuk menelanjangi krisis dan kritik kebudayaan Islam dewasa ini.
Selain dikenal karena kritiknya yang tajam terhadap kebudayaan dan politik di dunia Arab dan Islam, Tibi terus menggaungkan filsafat politik Islam kontemporer di dan dari dunia Barat (Jerman dan Amerika).
Mengawali karir akademiknya sejak muda — setelah bermigrasi ke Jerman — dalam “The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific-Technological Age”(1988), kritik Tibi mengarah pada kebudayaan Islam tradisional dan menyerukan perlunya reformasi dan modernisasi.
Menurut Tibi, kebudayaan Islam tradisional telah mengalami krisis yang mendalam karena ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
Lanjut ia katakan, kebudayaan Islam telah terjebak dalam dogma dan ritualisme, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern.
Tibi juga mengkritik peran ulama dan institusi keagamaan yang dianggapnya telah mempertahankan kebudayaan tradisional dan menghambat perubahan.
Dalam “Islam between Culture and Politics” (2001), Tibi terus mengembangkan kritik kebudayaannya terhadap kebudayaan Islam yang dianggap literal-skriptural dan terperosok pada kejayaan masa lalu, salafisme (lihat Salafismus in Deutschland,2014).
Pendapatnya, Islam telah menjadi politis dan digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan dengan itu memperluas pengaruhnya.
Karena itu, Tibi menganjurkan perlunya pemisahan antara agama dan negara, serta urgensi penerapan demokratisasi dan liberalisasi di negara-negara Islam.
Demikian pula kritiknya tentang konsep Islamisme sebagai kebudayaan politik yang dianggap berupaya hendak mengembalikan kejayaan kebudayaan Islam tradisional (lihat Islam dan Islamisme, 2016).
Tibi berpandangan, upaya ini tidak hanya tidak realistis, tetapi juga dapat membahayakan kemajuan dan modernisasi di negara-negara Islam.
Untuk menengahi pemaksaan kejayaan Islam historis itu, jauh sebelumnya, 1990, Tibi — alumni dua PhD dari Universitas Goethe
Frankfurt dan Universitas Hamburg ini — telah menggagaskan dalam “Islam And The Cultural Accommodation Of Social Change.”
Dalam konteks Indonesia, kritik Tibi terhadap kebudayaan Islam tradisional sangat relevan dalam memahami dinamika sosial dan politik di negara ini. Terutama, krisis pergolakan politik Islam paskah reformasi. Remah-remah krisisnya pun masih terasa sejak 2014 hingga kini.
Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam telah jadi sansak dan kurasan dari kurap kebudayaan politik elit medioker.
Oleh karena itu, memahami kritik kebudayaan Tibi dapat membantu bagaimana memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam merangkul “syariah” modernisasi dan globalisasi era digital.
Akhirnya, sebagai seorang ilmuwan politik yang kritis terhadap kebudayaan Islam tradisional di Eropa (Jerman), Tibi, profesor emiritus Universitas Göttingen (1973-2009) yang masyhur dan cendekiaan Islam kontemporer yang malang melintang di dunia akademi Barat (Amerika), pantas didengar suara keras kritiknya.
Untuk itu, ia selalu menyerukan perlunya reformasi dan modernisasi di negara-negara Islam, serta pemisahan antara agama dan negara.
Kritiknya pun sangat relevan dalam memahami dinamika sosial dan politik di negara-negara Islam, terutama Indonesia yang hingga kini terus memojokkan kondisi politik dan kebudayaan Islam.
Betapapun umat Islam Indonesia mayoritas yang terbelah oleh antropologi politik Geertzian (The Religion of Java,1960), kritik kebudayaan Tibi justru harus jadi gagasan penting dan urgen bagi rancang bangun kebudayaan Islam mutakhir. (*)