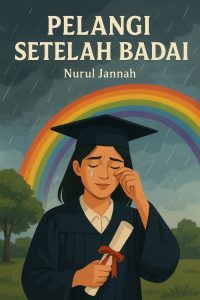Oleh: Junaidi Ismail
Koordinator Poros Wartawan Lampung
HATIPENA.COM – “Wartawan dari dulu hingga kini adalah buruh kerah putih berjeans biru. Makanya sebutannya kuli tinta.”
Kalimat ini disampaikan oleh salah satu wartawan senior Lampung, Herman Batin Mangku (HBM), dalam sebuah grup WhatsApp organisasi wartawan. Sebuah komentar singkat, namun mengandung makna mendalam, sekaligus menggugah kesadaran saya sebagai sesama pewarta.
Komentar ini muncul sebagai respons atas tulisan saya yang berjudul “Peran Pers dan Media dalam Membela Pekerja”. Sebuah tulisan reflektif tentang bagaimana media massa dan insan pers seharusnya memainkan peran lebih signifikan dalam memperjuangkan hak-hak kaum pekerja. Namun dlam perjalanannya, saya juga dihadapkan pada kenyataan bahwa wartawan bukan hanya pembela pekerja, mereka adalah bagian dari pekerja itu sendiri.
Saya sangat setuju dengan HBM. Dan dari sanalah, tulisan ini lahir sebagai refleksi, sekaligus ajakan, bahwa sudah saatnya wartawan tidak hanya menjadi pena bagi orang lain, tapi juga menjadi suara bgi dirinya sendiri.
Jika ada profesi yang menulis tentang semua hal, dari istana hingga kampung, dari tragedi hingga kemenangan, maka itulah wartawan. Tapi sering kali, dalam narasi-narasi besar itu, wartawan melupakan satu hal: menulis tentang dirinya sendiri.
Wartawan adalah pekerja. Mereka bukan pemilik media. Mereka bukan pemilik saham. Mereka bukan bos iklan. Mereka adalah para peliput yang bekerja dari pagi hingga larut malam, berpacu dengan tenggat waktu, bersaing dengan algoritma, kadang berhadapan dengan intimidasi, bahkan ancaman keselamatan. Semua itu dilakukan demi menyampaikan fakta dan kebenaran kepada publik.
Tapi, siapa yang peduli pada wartawan?
Sebutan “buruh kerah putih berjeans biru” begitu pas menggambarkan kondisi wartawan hari ini. Mereka mengenakan kemeja untuk tampil rapi di hadapan narasumber, namun tetap memakai jeans lusuh saat mengejar berita di pasar atau pinggiran kota. Di satu sisi, mereka dianggap profesional—kerah putih. Di sisi lain, mereka tetap harus siap bekerja di medan apapun—berjeans biru.
Mereka bukan pegawai kantoran yang bisa pulang jam lima. Mereka juga bukan artis media sosial yang hidup dari endorsement. Mereka adalah pekerja, dengan gaji kadang tak layak, dengan jam kerja tanpa batas, dengan tekanan kerja yng luar biasa.
Dan sebutan kuli tinta—dulu mungkin terdengar kasar—sekarang justru menjadi simbol perjuangan. Simbol dari profesi yang bekerja dengan semangat, tetapi sering dilupakan dalam sistem.
Mari kita tengok ke dalam. Berapa banyak media di Indonesia yang memberikan kontrak kerja jelas kepada wartawannya? Berapa yang membayar sesuai UMR? Berapa yang menyediakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan? Dan lebih penting lagi, berapa yang mau mendampingi wartawannya saat terkena masalah hukum karena berita yang ia tulis?
Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan betapa rapuhnya struktur ketenagakerjaan dalam industri media. Bahkan dalam media besar sekalipun, banyak wartawan honorer, kontributor lepas, hingga wartawan magang yang tidak memiliki kepastian kerja.
Jika para pekerja media tidak diperhatikan, bagaimana media bisa memperjuangkan nasib pekerja lain?
Kita sering menulis tentang buruh pabrik yang dipaksa lembur. Tapi lupa, bahwa kita sendiri kadang menulis berita itu di tengah malam, saat anak-anak kita sudah tidur, dan kita belum makan malam.
Kita sering mengangkat suara buruh yang dibayar di bawah UMR. Tapi lupa bahwa sebagian wartawan juga menerima honor ratusan ribu per bulan—kadang bahkan dalam bentuk pulsa atau transport, bukan gaji tetap.
Kita sering menyoroti perusahaan nakal yang tak memberikan hak pekerja. Tapi apakah media tempat kita bekerja benar-benar bersih dari praktik yang sama?
Ironi ini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi untuk membuka mata bahwa perjuangan buruh juga harus dimulai dari dalam profesi kita sendiri.
Sebagai Koordinator Poros Wartawan Lampung, saya percaya bahwa organisasi wartawan harus hadir sebagai rumah perjuangan, bukan sekadar simbol status. Organisasi wartawan harus menjadi tempat berlindung saat ada anggotanya dikriminalisasi. Menjadi tempat belajar saat ada anggotanya kesulitan mengembangkan kapasitas. Menjadi tempat advokasi saat ada anggotanya mengalami ketidakadilan di tempat kerja.
Kita harus keluar dari budaya diam. Wartawan harus berani bicara tentang kesejahteraan profesinya sendiri, tanpa takut dicap “tidak profesional” atau “tidak tahu diri”. Sebab tidak ada martabat dalam diam saat ketidakadilan terjadi.
Tanggal 1 Mei kemarin adalah Hari Buruh Internasional. Tapi, mengapa wartawan tidak pernah benar-benar merayakannya? Mengapa kita hanya meliput buruh yang demo, tanpa ikut merefleksikan diri bahwa kita pun bagian dari mereka?
Hari Buruh seharusnya menjadi momen bagi wartawan untuk bersolidaritas, bukan hanya sebagai peliput, tapi sebagai bagian dari dunia kerja yang harus diperjuangkan haknya.
Mungkin sudah waktunya para wartawan juga membawa poster: “Kami bukan alat kekuasaan. Kami adalah pekerja informasi yang butuh perlindungan dan kesejahteraan.”
Impian sederhana saya adalah agar anak-anak wartawan bisa sekolah dengan layak, agar wartawan bisa membeli rumah tanpa harus jadi “agen iklan”, agar wartawan bisa pensiun tanpa khawatir besok makan apa.
Untuk itu, perlu langkah bersama:
Mendorong kontrak kerja dan upah layak bagi semua wartawan.
Memperkuat organisasi profesi agar bisa menjadi pelindung sejati, bukan sekadar stempel legalitas.
Menumbuhkan solidaritas sesama wartawan, dari media besar hingga media kecil, dari pusat hingga daerah.
Meningkatkan literasi keuangan dan hukum bagi wartawan, agar mereka tidak mudah dimanfaatkan.
Kita bukan hanya penulis sejarah. Kta juga bagian dari sejarah. Kita bukan hanya saksi perjuangan. Kita juga bagian dari perjuangan.
Menjadi wartawan adalah kehormatan. Tapi kehormatan itu tidak boleh dibayar dengan kemiskinan, kelelahan, dan ketidakpastian. Kita punya hak untuk hidup layak. Kita punya hak untuk bekerja dengan martabat.
Sebagaimana kita membela kaum buruh, maka kita juga harus berani membela diiri kita sendiri.
Mari kita terus menulis. Bukan hanya untuk mereka. Tapi juga untuk kita. (*)
Tabik Pun…