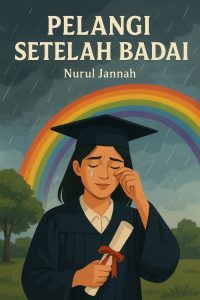Cerpen Sadri Ondang Jaya
LANGIT sore membentang kelabu. Angin berbisik lirih, menyelinap di antara pepohonan, membawa serta debu yang menari tanpa arah.
Aku duduk di teras rumah, menyesap teh yang telah lama mendingin. Lembar-lembar laporan proyek berserakan di atas meja, tetapi pikiranku melayang jauh, tersesat dalam lorong kenangan yang ingin kuhindari.
Sejak siang, dadaku sesak. Sebuah kabar mengetuk kesadaranku, seolah tangan tak kasatmata mengguncang hati. Nama yang telah kukubur bertahun-tahun tiba-tiba menyeruak. Rahmat. Ya, itulah namanya.
Awalnya hanya desas-desus. Seorang remaja empat belas tahun mengguncang kota kecil ini. Suaranya saat mengumandangkan azan mampu menggetarkan hati. Lantunan Al-Qur’annya menembus relung jiwa yang paling dalam.
Aku tak pernah menyangka, bocah yang namanya kini menggema itu adalah Rahmat. Anak dari keluarga yang tanahnya pernah kucaplok sepuluh tahun lalu.
Hatiku bergetar. Aku pikir dosa itu telah mati bersama waktu. Tapi ternyata, dosa tak pernah mati.
Dulu, aku pria muda yang haus keberhasilan. Bekerja di perusahaan properti milik seorang taipan besar, aku melangkah cepat, menyelesaikan proyek demi proyek tanpa peduli siapa yang tertinggal di belakang.
Kala itu, kami sedang membangun kompleks perumahan elite di pinggiran kota. Semua tanah telah kami beli dari warga, kecuali satu bidang kecil yang terletak tepat di tengah. Sebidang tanah itu milik seorang lelaki tua bernama Malik, istrinya bernama Sabariah, dan anak semata wayang mereka, Rahmat.
“Ini tanah leluhur saya,” kata Pak Malik suatu hari. Matanya tajam, suaranya serak tapi tegas. “Saya tidak menjual warisan ayah dan kakek saya hanya untuk dijadikan rumah mewah yang tak akan kami tinggali. Lagi pula, kalau kami jual, kami akan tinggal di mana?”
Aku tertawa kecil kala itu. Bagiku, dia hanyalah pria tua keras kepala yang tak paham bagaimana dunia bekerja. Dalam pikiranku, tanah bukan warisan, hanya angka di atas kertas. Hanya transaksi.
Negosiasi gagal. Maka, aku memilih jalan lain.
Malam itu, hujan turun deras. Dari balik kaca mobil, aku menyaksikan beberapa pria bertubuh kekar, suruhanku, menyelinap ke rumah Pak Malik. Bayangan mereka menari di balik tirai jendela, diiringi suara bentakan, jeritan, dan benda yang jatuh berdebam.
Aku menutup mata. Mencoba menutup telinga.
Keesokan harinya, tanah itu telah menjadi milik perusahaan. Pak Malik dan keluarganya lenyap tanpa jejak. Aku tidak pernah bertanya ke mana mereka pergi. Kata berita, orang tua itu dibawa ke rumah sakit. Entahlah! Aku tidak ingin tahu.
Tapi, ke mana pun aku pergi, bayangan mereka terus mengikutiku. Aku selalu dihantui kesalahan. Dosa yang tak termaafkan.
Sepuluh tahun berlalu.
Aku pikir semua telah berlalu. Sampai hari ini, ketika nama Rahmat kembali menggema di kota.
Ia bukan lagi bocah kecil yang dulu tak berdaya menyaksikan orang tuanya dihantam di hadapannya. Ia telah tumbuh menjadi remaja yang suaranya membangunkan jiwa-jiwa yang terlelap.
Aku menemuinya di masjid. Saat tiba, ia duduk di sudut ruangan, membaca Al-Qur’an. Suaranya pelan, lembut, tetapi setiap getarannya menekan dadaku, menggetarkan sukmaku.
Aku melangkah mendekat.
“Assalamu’alaikum.”
Ia mengangkat wajah. Tersenyum. Senyuman yang menelanjangiku.
“Wa’alaikumussalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?”
Aku tercekat. Ingin mengaku. Ingin mengatakan bahwa akulah yang telah menghancurkan keluarganya, merampas tanahnya, membuatnya yatim. Namun, lidahku kelu, seolah ada beban ribuan ton menahannya.
“Saya ingin mengenal Anda lebih jauh,” ucapku akhirnya.
Rahmat menutup mushafnya. Matanya jernih.
“Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, Pak,” katanya lembut. “Saya hanya seorang anak yatim. Kedua orang tua saya, Malik dan Sabariah, meninggal sepuluh tahun lalu… dipukul oleh cukong tanah. Sekarang, saya hanya berusaha menjadi manusia yang baik.”
Oh, Tuhan…
Aku menelan ludah. Dadaku sesak.
“Tahu kah Anda siapa cukong tanah itu?” tanyaku nyaris berbisik. “Anda tidak ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah menzalimi keluarga Anda?”
Rahmat tersenyum kecil. Menggeleng.
“Dendam tidak akan menghidupkan ayah bundaku kembali,” katanya. “Biarlah Allah Swt membalas semua kezaliman cukong tanah itu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya percaya, setiap perbuatan akan menemukan balasannya sendiri.”
Aku terdiam lama.
Waktu salat tiba. Kami berpisah. Aku berwudhu, Rahmat memasuki mimbar, mengumandangkan azan.
Saat azan berkumandang, suaranya membelah udara, menggema di seluruh penjuru masjid, menyelinap ke dalam rongga jiwaku yang kosong.
Setiap kalimatnya adalah belati yang mengoyak hati.
“Allahu Akbar… Allahu Akbar…”
Aku mendengarnya tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh kesadaranku.
Dan untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, aku menangis.
Terbayang wajah Pak Malik. Sorot matanya yang tajam. Suara Sabariah yang merintih, memohon. Tangis Rahmat yang masih kecil.
Aku tersungkur dalam sujud yang paling sunyi dalam hidupku.
Hatiku berbisik, “Kalau kamu menzalimi seseorang, lalu orang itu diam, waspadalah. Itu tanda hidupmu akan hancur. Karena kamu akan berhadapan dengan Allah Swt.”
Teringat sebuah hadis Rasulullah saw:
“Barang siapa yang menzalimi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), niscaya Allah akan membebaninya dengan tujuh lapis bumi hingga hari kiamat. Lalu Allah mengalungkannya di lehernya pada hari kiamat sampai semua manusia diadili.”
Ya Allah…
Aku menggigil. Betapa zalimnya aku. Aku merampas tanah yang bukan hakku, menyakiti pemiliknya, membuat seorang anak kecil menjadi yatim.
Semua demi ambisi.
Semua demi keserakahan.
Dan kini, hanya menyisakan kehampaan.
“Apakah Engkau menerima tobatku, ya Allah?” bisikku lirih.
Angin kembali berdesir. Langit yang kelabu kini mulai merona jingga.
Aku menatap masjid. Lalu menatap Rahmat.
Aku harus menebus dosaku. Tapi bagaimana?
Dan dalam isak panjang, aku sadar.
Dosa tanah ini akan tetap melekat di bumi dan langit, kecuali aku menebusnya.
Bagaimana aku menebusnya?
Aku belum tahu.
Tapi aku harus mencobanya.[*]
*) Guru dan pemerhati dinamika sosial budaya berdomisili di Aceh.