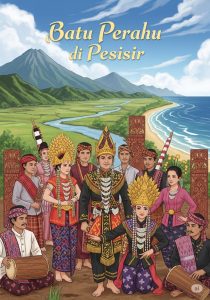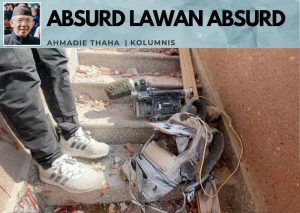Oleh: A.Yudi & M.Taufik
Alumnus IPA 1 SMAN Bangil 1986
HATIPENA.COM – Hujan turun perlahan di luar jendela, seperti perasaan yang tak pernah sempat diucapkan. Di sebuah kedai kecil yang hangat, empat sahabat duduk melingkar dengan secangkir teh dan sepiring roti. Mereka adalah Ana, Anis, Chichiek, dan Ening—sahabat sejak duduk di bangku IPA 1 SMAN Bangil 1984.
Sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali mereka saling menyapa di ruang kelas yang kini tinggal kenangan. Namun sore itu, di tengah hujan dan kenangan, mereka berkumpul kembali, bukan untuk merayakan, tapi untuk saling menguatkan.
Ana menatap cangkirnya dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar oleh kata yang tertahan. “Aku kira dia mencintaiku,” ucapnya pelan. “Tapi ternyata… yang menyakitkan bukan karena dia tidak mencintaiku. Tapi karena harapanku sendiri yang terlalu tinggi.”
Anis menatapnya penuh empati. Ia tahu, luka seperti itu tidak mudah sembuh. Chichiek menyahut, “Bukan cinta yang menyakitkan, Ana. Tapi harapan yang berlebihan.” Suaranya lembut namun tegas, seolah ia pun pernah belajar dari luka yang sama.
Ening yang duduk di samping Ana, meraih tangannya dan berkata, “Cinta bukan untuk digantungkan, tapi untuk dimaknai.”
Di atas meja, sebuah topeng kecil tersenyum. Topeng itu milik kedai yang mereka datangi—tapi seolah mewakili perasaan mereka. Topeng itu simbol dari semua pura-pura bahagia, dari senyum yang disembunyikan luka, dari hati yang berpura-pura kuat.
Dalam psikologi, Albert Ellis menjelaskan bahwa yang membuat seseorang terluka bukan realita itu sendiri, tapi harapan yang tidak realistis atau yang ia sebut irrational beliefs. Ketika kita berharap seseorang mencintai kita seperti dalam skenario hati kita, dan ternyata tak sesuai, maka luka itu muncul bukan dari cinta, tapi dari skenario yang kita ciptakan sendiri.
Anis menimpali, “Kata Carl Rogers, cinta itu tumbuh ketika kita menerima seseorang—dan diri kita—tanpa syarat. Tapi kalau kita mencintai dengan pamrih, kita rentan kecewa.”
Chichiek mengangguk pelan. “Makanya dalam pendidikan sekarang pun, anak-anak perlu diajarkan emotional resilience. Dr. Michele Borba, pakar pendidikan karakter, bilang kalau generasi muda harus belajar bangkit dari harapan yang patah—bukan justru tumbang.”
Ening, yang selama ini menjadi penyeimbang di antara mereka, membaca ulang catatan kecil dari Qur’an yang selalu ia bawa. Ia membisikkan sabda Rasulullah SAW:
“Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya saja, siapa tahu ia akan menjadi orang yang kamu benci suatu hari nanti.”
(HR. Tirmidzi)
Ana tersenyum samar. “Berarti selama ini aku hanya sedang belajar ya…”
“Bukan salah, bukan gagal,” jawab Chichiek. “Kita cuma sedang berproses.”
Empat cangkir teh, empat hati yang pernah patah, dan satu persahabatan yang tak lekang waktu. Malam itu, bukan malam air mata, tapi malam pembebasan. Bahwa cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihargai. Bahwa harapan harus dibingkai dengan kesadaran. Dan bahwa, yang paling romantis bukanlah “aku mencintaimu,” tapi “aku ikhlas melepasmu tanpa kehilangan diriku sendiri.”
Dari SMAN Bangil tahun 1986 hingga kini, mereka tetap sahabat. Dan dari ruang IPA 1 hingga ruang hati yang penuh luka dan harapan, mereka tetap saling menguatkan. (*)
#menukiscerpenpramuka&persahabatan Cerpen ke-17