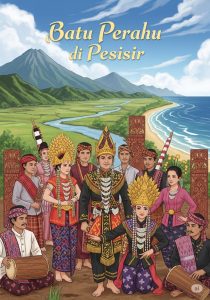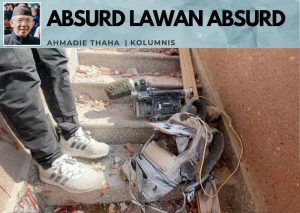Pipiet Senja
HATIPENA.COM – Anno, 1981
Sudut kamar yang sangat nyaman, kota hijau, Cimahi.
Saat ini aku telah menyadari betul bagaimana kondisi tubuhku, penyakit abadi kelainan darah bawaan, maka aku pun memutuskan untuk bertahan.
Ya, mencoba untuk bertahan, sebuah istilah yang terlontar begitu saja, ketika aku diwawancarai oleh seorang reporter majalah Kartini yang sengaja datang ke rumah orang tuaku di Cimahi pada tahun1980.
“Mencoba Untuk Bertahan… Wah, Teteh, boleh juga tuh jadi judul cerpen,” komentar adikku En yang paling dekat dan sering curhatan.
Bukan cerpen melainkan sebuah novelet (60 halaman) bertema pernikahan, Mencoba Untuk Bertahan, akhirnya kupakai sebagai judul yang telah melampaui proses kreativitas panjang. Buku itu berupa novelet mungil, diterbitkan oleh Aries Lima sekitar tiga tahun kemudian.
Nah, kembali kepada keputusan untuk mencoba bertahan. Begitu aku mendapatkan honor tertinggi yang pernah kuperoleh yakni satu juta dari buku memoar perdanaku; Sepotong Hati di Sudut Kamar, maka aku pun membangun pavilyun di depan rumah orang tuaku.
Pembangunan pavilyun itu ternyata melebihi budget, melampaui dana yang kumiliki. Kutahu kemudian diam-diam ayahku menambahinya dengan cara membelikan berbagai bahan material melalui para tukang.
“Baik, di sinilah aku bertahan, mengisi dan menikmati hari-hariku, seberapapun yang diberikan Tuhan kepadaku,” gumamku ketika pavilyun itu selesai, dan aku bisa menempati sebuah kamar berukuran empat kali empat.
Inilah kamar milikku sendiri dan ditempati sendirian pula.
Sebelumnya aku menempati sebuah kamar sempit, berukuran dua kali tiga, dan sering kali ada seorang adikku ikut pula tidur bersamaku. Bagiku ini sebuah kado terindah yang pernah kumiliki, berkat ikhtiar, hasil dari mata pencaharianku sendiri.
Ada lemari buku sebagai penyekat antara kamarku dengan ruang tamu. Di rak buku itu pula aku menderetkan koleksi bukuku dan memajang karya-karyaku sejak tahun 1975. Belum banyak ternyata, demikian bila setiap malam iseng kucermati dokumentasiku yang berderet di depan mata.
Baru dua buku; Biru Yang Biru dan Sepotong Hati di Sudut Kamar.
Namun, sesungguhnya cerpenku sudah ratusan, demikian pula novelet dan cerita bersambung yang telah dimuat di berbagai media Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya bahkan beberapa koran terbitan Malaysia.
Setahun sebelumnya aktivitasku telah bertambah, yakni belajar teater pada para seniorku di Bandung. Tak lama kemudian aku memutuskan untuk kembali ke sudut kamarku, melahirkan karya, seorang diri!
Demikian yang kulakukan memasuki proses pendewasaan diriku.
Menulis, menulis dan menulis… Transfusi, transfusi dan transfusi. Sampai suatu saat aku pun merasai suatu kehampaan yang tak teperi. Perasaan itu awalnya tidak kuindahkan sama sekali, tapi ternyata terasa mencengkeram jiwaku.
Awalnya aku bertemu dengan En yang telah melahirkan seorang anak laki-laki.
“Enak, ya En… menjadi seorang ibu?” tanyaku sambil menatapnya dengan iri. Sementara dia sibuk memberi susu botol kepada bayi yang baru dilahirkannya.
“Ya, inilah kebahagiaan yang takkan mampu kulukiskan,” sahutnya dengan wajah berseri-seri, sepasang matanya yang agak menyipit berbinar-binar indah. “Puncak kebahagiaan seorang wanita,” lanjut adikku yang telah melangkahiku, menikah dengan seorang pria berasal dari Manado.
Seorang bayi montok yang lucu tampaknya menggemaskan sekali. Pipi-pipinya yang gembil, membuat sepasang matanya menyipit. En memberinya nama; Peter Arief Rorimpandey. Agaknya mata sipit itu berasal dari dia, mengingatkanku kepada nenekku dari pihak ibu kami yang konon ada darah ningrat kasepuhan Cirebon dan Sumedang.
Sementara aku mendapat warisan berupa kulit kuning langsat, tapi lebih sering tampak memutih pucat akibat kekurangan darah. Ada juga adikku Ry, adikku ketiga yang juga terkena gen Thallasemia, sepasang matanya menyipit dengan kulit pucat.
Ya, aku bisa merasai pancaran kebahagiaan dari keseluruhan dirinya, sosok mungil yang pada masa remaja sering bermasalah dengan dietnya yang ekstrim itu.
Belakangan baru kutahu ada istilah kedokteran yang populer disebut anorexia dan bulimia. Kami mana tahu hal itu, bahkan ayah kami pun terkecoh, dan selalu menyebut kondisi adikku sebagai penderita maag.
“Bagaimana perasaan suamimu?” selidikku, itulah untuk pertama kalinya ingin kukorek tentang keadaan rumah tangganya.
Di mataku sosoknya kini telah menjadi Cinderella. Kutahu, sebagai istri muda dia telah banyak mengalami masalah, cemooh dari masyarakat, terutama dari pihak istri tua yang senantiasa mengirimkan orang-orang untuk menerornya. Sehingga hari-harinya tak pernah dibiarkan tenang begitu saja.
“Papi,” ujarnya terdengar mengambang. “Tentu saja dia bahagia, oh, siapa sih yang gak senang punya anak? Setelah lima belas tahun nikah dengan istrinya… Mereka tak dikaruniai anak juga?”
“Apa sekarang kamu sudah bahagia, meskipun menjadi seorang istri muda?” tanyaku ingin tahu.
“Siapa sih yang mau menjadi istri muda?” suaranya yang mendadak meninggi, seolah-olah masih terngiang di kupingku. “Tapi beginilah kenyataannya, mau apalagi, memang mungkin Tuhan maunya aku seperti ini…”
Kutinggalkan adikku dalam suasana kebahagiaan yang menyelimuti kehidupannya kini. Meskipun aku merasa sangsi akan kebahagiaannya. Entahlah, seakan-akan kebahagiaan itu hanyalah semu, dan suatu saat malah akan mencerabutnya dari puncak sana hingga terpelanting.
Bagiku, apapun alasannya, keputusan adikku untuk menjadi seorang istri muda itu adalah keliru. Ya, aku tak bisa menerima hal itu, seandainya aku berada di posisi yang sama. Tidak, aku tak pernah membayangkan seandainya diriku menjadi tukang rebut suami orang!
Apapun itu, kesepian mulai menghantui hari-hariku selanjutnya. Kesepian yang menghampakan seluruh jiwa dan ragaku, membuncah luas di sekujur diriku.
Duhai, kesepian yang sangat melukai!
Buat apa aku hidup? Buat apa aku bertahan? Bila takkan pernah kurasai menjadi seorang wanita sejati, seorang wanita dengan kebahagiaan puncak melahirkan anak?!
Inilah masalah kejiwaan yang mencengkeram diriku di usia ke-23.
Suatu jenjang usia yang sudah patut disebut jomblo, menjadi cemoohan masyarakat sekitarku kala itu. Maka, kegundahan itu tak pelak lagi mencuat juga dalam buah penaku.
Banyak cerpen yang terlahir dari suara kepedihan, kesepian yang mencengkeram jiwaku, kemudian menghiasi media-media Bandung dan Jakarta.
“Perbanyaklah sholat lail, Neng,” kata Ustazah Eha, guru mengaji yang didatangkan ayahku untuk mengajari anak-anak perempuannya memperdalam keislaman.
“Ya, saya sudah melakukannya, Ceuceu,” sahutku menunduk pedih, kitabullah di hadapan kami tampak sudah tua dan kusam. Saking seringnya bergulir di antara tujuh bersaudara, tambah seorang sepupu, kecuali adikku En yang jarang memperdalam keislamannya.
“Jangan lupa shaum Senin-Kemis juga shaumnya Nabi Daud,” nasihat ibu lima anak yang selalu mendengar curah hatiku itu.
Dengan kepatuhan seorang murid aku pun mengikuti nasihat-nasihatnya. Ya, kusadari bahwa aku telah menjadi orang yang tak bersyukur. Seolah-oleh tak puas jua, sudah diberi kesempatan hidup, malah menuntut yang lain-lainnya?
Aaaarrrggh, tapi bukankah ini manusiawi sekali?
Kebimbangan pun terus merunut jejak langkah yang coba kupatri. Aku masih mencoba bertahan, bertahan dan bertahan. Hingga dalam kelabilan jiwa itu, saat diriku nyaris menyerah pada titik nadir kepasrahan; Tuhan pun memberiku warna lain dalam lakon hidupku selanjutnya.
Aku takkan bisa melupakannya saat detik-detik Sang Pengasih mengirimkan jodohnya untukku.
Selamat tinggal masa-masa jomblo.
Selamat datang dunia pernikahan. (*)