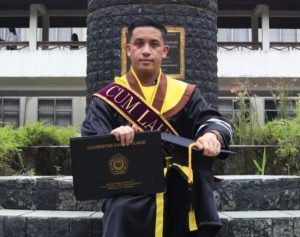Cerpen Sadri Ondang Jaya
(Sebuah Kisah Konflik Buaya dan Manusia di Aceh Singkil)
HATIPENA.COM – Senja merayap perlahan di cakrawala, meleburkan cahayanya ke permukaan Sungai Singkil. Airnya berkilauan seperti serpihan emas yang dihanyutkan waktu.
Di kejauhan, desir angin menggoyang rimbun nipah, enceng gondok dan bakung, membawa serta aroma lumpur, lumut basah, dan rahasia yang tertanam di dasarnya.
Di tubir Sungai Singkil yang hening, Kak Acu melangkah dan berenang pelan. Ember kecil bergoyang di tangannya, penuh dengan lokan yang ia gali dari lumpur.
Jemari kasarnya menyibak akar-akar berlumur lumpur, menelisik setiap sudut gelap di bawah air. Sekali-kali, ia menyelam. Memungut hewan kerang-kerangan itu.
Namun, sore itu, Sungai Singkil menyimpan sesuatu yang tak biasa.
Tiba-tiba, air beriak liar. Pusaran muncul dari dasar sungai, menciptakan getaran halus yang merambat ke daratan. Sekelebat bayangan hitam melesat di bawah permukaan, begitu cepat, begitu sunyi, seperti kilat yang tak bersuara. Buaya.
Byur! Byur…!
Sebuah kekuatan dahsyat menghantam Kak Acu. Rahang yang dingin dan kuat mencengkeram kakinya, menariknya ke dalam kegelapan. Dunia berputar. Air menyelubungi tubuh, mencekik napasnya.
Nelayan yang mencari lokan telah puluhan tahun itu, berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam riak dan gemuruh air.
Embernya berisi lokan terlempar, lokan-lokan yang telah ia kumpulkan berhamburan ke sungai, seolah menertawakan perjuangannya.
Tangan Kak Acu menggapai, mencakar lumpur, mencari pegangan. Namun, makhluk itu terlalu kuat. Gigi-gigi tajam menggali lebih dalam ke kulitnya, mengoyak dagingnya.
Dalam remang senja, ia hanya bisa melihat sepasang mata kuning yang menatapnya dari permukaan air. Dingin, kosong, tanpa iba.
Dengan tiba-tiba, di kejauhan, raungan mesin robin memecah keheningan. Bang Dulah, seorang nelayan tua, melihat kegaduhan itu. Dengan panik, ia melajukan perahunya ke arah Kak Acu.
“Hei, buaya hamba Allah! Lepaskan dia! Ia hanya mencari nafkah,” teriaknya, sembari memukul air dengan pengayuh kayu.
Buaya itu ragu sejenak. Rahangnya sedikit mengendur.
Dengan sisa tenaga, Kak Acu meronta. Ia menendang, menarik tubuhnya dengan berenang sekuat tenaga ke gundukan tanah pinggir sungai.
Rasa sakit menyambar seluruh sarafnya, tetapi ia tak peduli. Hidupnya dipertaruhkan di antara rahang dan lumpur gundukan.
Akhirnya, makhluk predator itu melepaskan cengkraman giginya.
Kak Acu terhempas ke gundukan sungai, dadanya naik turun, napasnya memburu. Luka di kakinya menganga, darahnya merembes, menciptakan jejak merah di air dan di atas tanah basah.
Bang Dulah melompat dari perahu dan menarik tubuh Kak Acu lebih jauh ke daratan. “Allahu Akbar! Kau masih selamat, Kak Acu!” serunya, suaranya gemetar antara lega dan ketakutan.
Sungai Singkil kembali sunyi. Hanya desir angin dan riak kecil yang tersisa.
Sejak hari itu, nama Kak Acu menjadi bisikan di seantero desa. Ia adalah orang yang selamat, tidak seperti Udo, pemuda yang tubuhnya ditemukan tercabik mengapung dan beberapa bagian hilang, beberapa bulan lalu.
Atau Uwo, yang hilang di Sungai Singkil dan tak pernah ditemukan lagi. Diduga ia diterkam buaya dan dibawa entah kemana.
Di warung kopi, di pasar, di jalanan desa, di balai-balai dan tempat-tempat umum, kisah tentang buaya pemangsa kembali menghantui.
Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan hitam itu mengendap di bawah tambatan perahu warga.
Ada yang kehilangan bebek yang dimangsa hewan ampibi itu. Ada yang mendengar suara gemuruh dari dalam air pada malam-malam tertentu.
Sungai Singkil yang dulu memberi kehidupan, kini menjadi gerbang maut yang mengintai dalam diam.
Di rumahnya, Kak Acu hanya bisa terbaring. Kakinya terbalut kain kasa, matanya menatap kosong ke langit-langit, pikirannya berkelana.
“Jika sungai tak lagi ramah, ke mana lagi kami harus mencari nafkah hidup?”gumam Kak Acu.
Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Lampu redup menciptakan bayangan orang-orang bergoyang di di sudut ruangan di dinding kayu.
“Adanya konflik buaya dengan manusia ini, kita tidak bisa diam saja,” ujar Keuchik, suaranya berat. “Buaya itu sudah kelewatan. Tapi kita juga tahu, kita tak bisa membunuhnya sembarangan.”
“Jadi kita biarkan saja?” sergah seorang pemuda. “Harus ada tindakan! Berapa lagi nyawa yang harus melayang?”
Bang Dulah menghela napas. “Dulu, orang-orang tua bilang, sungai ini ada penunggunya. Mungkin ini cara alam menegur kita.”
Seorang lelaki tua yang duduk di sudut, Wak Imran, seorang mantan pawang buaya mendeham pelan. “Buaya itu tak akan pergi sendiri. Kita harus mencari cara yang lebih bijak. Kita bisa bekerja sama dengan pihak konservasi, atau memindahkannya ke tempat yang lebih aman atau…”
Pak Keuchik mengangguk. “Kita buat laporan resmi. Jika pemerintah tak peduli, kita cari jalan sendiri. Wak Imran dengan kepiawaian bisa mengatasi. Yang penting, jangan ada lagi korban.”
Mereka tahu, ini bukan sekadar masalah manusia dan buaya. Ini juga masalah pengabaian, ketidakpedulian, kehadiran negara dalam melindungi warganya dan pertarungan takdir.
Masyarakat di tepian Sungai Singkil, Kuala Baru, dan Gosong Telaga, lokasi yang kerap terjadi konflik manusia vs buaya, kini memegang harapan.
Berharap ada solusi.
Berharap tak ada lagi tubuh yang terapung di antara batang nipah.
Berharap, suatu hari nanti, sungai yang mereka cintai akan kembali menjadi sahabat, tempat warga mencari penghidupan dan kearifan.
Bukan bayangan yang mengintai dari kedalaman. Dan bukan lagi sungai yang menggenggam takdir dengan rahang yang tak mengenal ampun.[*]
Gosong Telaga, 2 Februari 2025