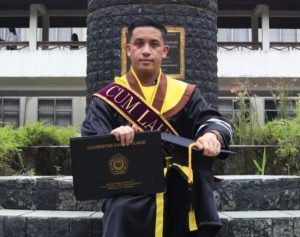Catatan Henri Nurcahyo
HATIPENA.COM – Meski sekilas tampak sederhana, dua karya Arahmaiani dalam ARTSUBS #2, “Kasih” dan Song of the Rainbow, menyimpan sejarah panjang dan berliku.
“Kasih” hadir sebagai soft sculpture yang ditempel di dinding, berupa kaligrafi Arab Pegon berwarna-warni yang timbul dari bahan lembut, sementara Song of the Rainbow adalah karya dua dimensi. Keduanya menegaskan pesan tentang toleransi dalam keberagaman: bahwa Islam sejatinya adalah kasih, kelembutan, dan sikap anti-kekerasan.
Bersama Handiwirman Saputra, Arahmaiani—perempuan kelahiran Bandung, 21 Mei 1961—berbagi kisah proses kreatifnya di selasar Balai Budaya, Sabtu siang (23/8), dipandu moderator Asmujo. Menurut Asmujo, sejak mahasiswa Yani—begitu ia akrab disapa—sudah dikenal “nakal”: pernah dikejar tentara Orde Baru, dipaksa mengundurkan diri dari ITB, hingga lari ke Australia. Bahkan, ia sempat dianggap “darahnya halal” karena karyanya dituding melecehkan agama.
Pertanyaannya, kalau karya “Kasih” itu substansinya adalah menyampaikan tentang kelembutan, mengapa tidak sekalian diberikan akses bagi pengunjung pameran agar memegangnya? Memang di dinding tidak terdapat larangan “dilarang menyentuh karya” sebagaimana karya-karya pada umumnya. Tapi mereka pasti tak akan berani menyentuhnya. Tanpa interaksi langsung antara pengunjung dengan karya, maka pesan itu kurang maksimal tersampaikan.
Menjawab pertanyaan ini, salah satu perupa kontemporer terkemuka di Indonesia ini, mengatakan: “Semula saya malah menginginkan karya itu jangan dipajang di dinding. Tapi diletakkan saja di lantai sehingga orang bebas memegang dan bahkan selonjoran di atasnya. Tapi kan ada pertimbangan, nanti jadi kotor, rusak, dan sebagainya.”
Dalam karya Song of the Rainbow, Arahmaiani menampilkan potongan huruf Arab Pegon: Syin berwarna kuning, ‘Ain merah, Lam biru tua, dan Alif hijau, semuanya diletakkan di atas latar biru muda. Setiap huruf membawa simbolnya sendiri—Syin sebagai cahaya pengetahuan, ‘Ain sebagai sumber kehidupan, Lam sebagai penegasan tauhid, dan Alif sebagai lambang keesaan—sementara warna-warna yang dipilih menguatkan makna tersebut. Latar biru muda berfungsi sebagai ruang universal, langit yang menaungi perbedaan huruf dan warna itu agar hadir dalam satu harmoni.
Dalam konteks Arab Pegon, huruf-huruf yang dipilih Arahmaiani—Syin (sy), ‘Ain (a), Lam (l), dan Alif (a)—jika dirangkai membentuk bunyi “syala”, yang dalam lidah Jawa–Sunda dekat dengan kata “nyala”. Kata ini berkaitan dengan cahaya, api, dan penerangan, sehingga selaras dengan konsep pelangi dan pesan harmoni yang ia usung dalam Song of the Rainbow. Dengan cara itu, Arahmaiani bukan hanya menghadirkan huruf sebagai bentuk visual, tetapi juga menghidupkan makna tersembunyi yang berakar pada bahasa dan budaya lokal.
Menariknya, kedua karya Arahmaiani ini dipajang bersebelahan di dinding yang menyiku, sementara sisi dinding lainnya sengaja dibiarkan kosong. Yani memang tidak menjelaskan hal ini dalam acara Wicara Seniman tersebut. Tetapi hal ini bisa dimaknai, bahwa kekosongan itu bukan tanpa arti. Kekosongan itu tak ubahnya sebagai ruang jeda, ruang napas, sekaligus bingkai tak kasatmata yang justru menegaskan kehadiran karya. Dalam tradisi Timur, termasuk Islam dan Buddhisme yang kerap dirujuk Arahmaiani, “kosong” bukanlah hampa, melainkan potensi—tempat di mana makna lahir dan tumbuh. Dengan demikian, dinding kosong itu dapat dibaca sebagai ruang kesunyian yang memperkuat pesan kelembutan, toleransi, dan kasih yang diusung karya-karyanya.
Darahnya Halal
Mengudar masa lalunya, sebagai mahasiswa seni rupa, Yani pernah kecewa dengan pendidikan seni di Indonesia yang menurutnya jauh dari realitas sehari-hari. Ia memilih berkarya di jalanan, bereksperimen secara intuitif dengan performance art. Pada 17 Agustus 1983, ia ditangkap dan diinterogasi oleh aparat setelah membuat karya dengan kapur di jalanan yang mempertanyakan makna kemerdekaan. Waktu itu, dia bersama dua kawan menggambar berbagai peralatan militer, tank, dan senjata, dengan kapur sebagai bentuk protes atas pemerintahan otoriter Soeharto. Setelah ditahan selama sebulan Arahmaiani baru dilepas setelah menandatangani surat tidak sehat secara mental. Konsekuensinya: dikeluarkan dari ITB.
Dalam kebingungan masa muda, ia hijrah ke Sydney bersama teman-temannya. Di sana, Yani bekerja di pasar komunitas hippies yang peduli isu penjajahan sekaligus menemukan akses pada manuskrip-manuskrip Nusantara yang tak pernah ia temukan di perpustakaan kampus. Pengalaman itu membuka matanya, hingga 2,5 tahun kemudian ia memutuskan: “Aku harus pulang.”
Sejak 1994, ia menekuni tradisi Arab Pegon—jejak budaya Islam Nusantara yang sarat toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia mendatangi situs-situs purbakala, berkemah di candi-candi, menyerap aura sejarah. Dari sana lahirlah karya monumental Lingga–Yoni, simbol keseimbangan kosmis yang mengingatkan agar manusia tidak terjebak pada oposisi biner: benar-salah, baik-buruk, hidup-mati.
Dalam lukisannya ini dia membalik posisi lingga dan yoni: yang perempuan (yoni) justru ditempatkan di atas, sementara lingga (laki-laki) berada di bawah. Dengan cara itu, ia hendak menggugat budaya patriarki sekaligus mempertanyakan klaim dominasi maskulinitas.
Tapi kelompok Islam fundamentalis, lukisan Lingga-Yoni membuat mereka marah. Mereka menuduh Yani menistakan agama karena menggabungkan huruf Arab dengan simbol kelamin. Padahal teks yang ia tampilkan berbunyi: “alam adalah kitab”—sebuah ajakan untuk menyadari kesatuan manusia dengan alam.
Tuduhan serupa muncul pada karya instalasi berupa etalase berisi patung Buddha, simbol Hindu, Al-Qur’an, Coca-Cola, dan kondom produksi perusahaan anak Soeharto. Pertanyaannya sederhana: mengapa kitab suci diletakkan di dekat kondom? Bagi Arahmaiani, itu adalah kritik atas ekonomi global yang masih menyisakan bentuk-bentuk penjajahan.
Keributan itu bergulir. Untunglah ia mendapat pembelaan dari tokoh-tokoh seperti Cak Nun, Romo Muji Sutrisno, WS Rendra, hingga Syuba Asa. Meski demikian, ancaman pembunuhan tetap menghantui, membuatnya kembali melarikan diri ke Australia, di mana ia sekaligus mengajar.
Sejak itu, perempuan yang menolak disebut feminis ini semakin mendalami tradisi budaya Islam Nusantara. Baginya, Arab Pegon tanpa harakat adalah medium kreatif yang mempertemukan Islam dengan budaya lokal melalui akulturasi. Dari situlah ia menemukan bahwa leluhur Nusantara memiliki kebijaksanaan: tidak merasa paling benar, tidak mudah menghakimi yang berbeda, dan selalu mengutamakan keseimbangan.
Selain dekat dengan para kiai NU, Yani juga memiliki jejaring dengan kalangan Muhammadiyah. Hubungan lintas ormas Islam ini memperlihatkan bagaimana ia berupaya merangkul keberagaman, melampaui sekat-sekat ideologis, dan tetap konsisten mengusung nilai toleransi.
Bahkan nama “Arahmaiani” itu sendiri mewakili bentuk sinkretisme atau percampuran dua budaya di keluarganya. Ayahnya seorang ulama dan ibu seorang Muslim yang berasal dari latar belakang agama Hindu-Buddha. “Arahma” berasal dari bahasa arab yang berarti “cinta” dan “iani/yani” berasal dari bahasa Hindi yang berarti “manusia”.
Beberapa bulan lalu, Arahmaiani bahkan diundang oleh Muhammadiyah untuk berbicara tentang warisan tradisi budaya leluhur, baik dari masa Islam maupun sebelumnya, serta kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Untuk yang terakhir, ia merasa beruntung pernah belajar langsung di vihara Tibet dan mempraktikkannya di sana. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa ajaran di vihara tersebut sesungguhnya berakar dari tradisi dan budaya masa Borobudur—sebuah warisan yang masih lestari hingga kini, terutama di kalangan sekte Topi Kuning yang dipimpin langsung oleh Dalai Lama.
Hal ini seolah menjadi muara atas pengalamannya yang sejak kecil hidup di dekat alam terbuka dan kerap melakukan kegiatan di sana.
“Karena itu pesan saya, jangan lupakan kearifan budaya tradisi, terutama yang terkait dengan lingkungan hidup dan kebersamaan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan komunal. Komunitas itu penting. Bukan individualistis, yang ujung-ujungnya jadi egois. Kita harus saling mengingatkan supaya jangan keblabasan,” tutur penerima Anugerah Budaya Kota Bandung Tahun 2021 ini.
Kabar terbaru, Arahmaiani akan menjadi pembicara dalam sebuah konferensi internasional di Doha, Qatar, pada November mendatang. Undangan itu datang dari kalangan terpelajar Timur Tengah yang tertarik mempelajari budaya Islam Nusantara. Ironisnya, mereka sendiri mengakui bahwa budaya Abrahamik di Arab cenderung sempit: Hindu, Buddha, bahkan tradisi animisme sudah lama terhapus dari ingatan.
“Saya bilang ke mereka, tolong dipastikan tidak ada orang-orang dari garis keras yang akan mengancam keselamatan saya,” tegas salah satu pelopor dalam perkembangan performance art di Indonesia dan Asia Tenggara ini. (*)