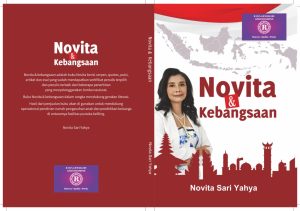Oleh Sadri Ondang Jaya
(Guru dan Budayawan Aceh)
PAGI itu mendung menggantung di langit, seakan enggan membuka tirainya. Angin berembus lembut, membawa hawa sejuk yang menyelinap hingga ke ruang guru. Sebelum bel tanda masuk berbunyi, aku duduk bersama empat guru, berbincang tentang berbagai hal, terutama tentang rendahnya etos kerja guru belakangan ini.
“Ah, saya juga bingung, Pak,” keluh Pak Rahmat, Wakil Kepala Sekolah bidang akademik yang sudah dua dekade mengajar. “Banyak guru sekarang lebih suka buru-buru pulang daripada berlama-lama di sekolah. Dulu, suasana sekolah terasa lebih hidup. Sekarang tidak lagi, bagai kuburan.”
Bu Siti, guru Bahasa Indonesia, menimpali, “Jangan salah, Pak. Saya pun kadang merasa begitu. Saya mulai bertanya-tanya, apakah kita ini benar-benar pendidik atau sekadar pegawai kantoran?”
Pak Rahmat mengangguk pelan. “Padahal, kita sudah menerima tunjangan profesi. Tapi masih banyak yang datang terlambat, pulang cepat, dan mengabaikan tanggung jawabnya. Jujur saja, sebagai Wakil Kepala Sekolah, saya merasa tidak dihargai di sekolah ini.”
Di sudut meja, Pak Mis, guru muda yang baru setahun mengajar, terdiam. Dulu, semangatnya mengajar begitu membara. Pernah ia berkata kepadaku, “Mengajar adalah panggilan hidup saya.” Namun kini, semangat itu tampak meredup.
“Saya ingin jadi guru yang baik, Bu Siti, Pak Sadri, dan Pak Rahmat. Tapi bagaimana bisa, kalau suasana sekolah seperti ini? Banyak guru sering absen, tak masuk kelas, atau sekadar menggugurkan kewajiban. Bagaimana saya bisa mengajar dengan hati dan dedikasi yang tinggi jika lingkungan sekitar justru melemahkan niat dan tekad saya?” ujar Pak Mis dengan nada putus asa.
Aku, Pak Rahmat, dan Bu Siti saling pandang. Kami tahu, di hati kecilnya, Pak Mis masih punya bara semangat.
“Memang tidak mudah, Pak Mis,” kata Pak Rahmat, serius. “Tapi kita harus ingat, profesi ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah amanah. Kita bertanggung jawab atas masa depan anak-anak bangsa. Tanggung jawab ini, akan kita pertanggungjawaban pada Allah.”
Pak Mis terdiam, merenungkan kata-kata itu.
“Menjadi guru,” lanjut Pak Rahmat, “bukan hanya berdiri di depan kelas dan mengajar, cas cis cus. Kita adalah teladan. Kita harus memotivasi, menginspirasi, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan.”
Namun, kenyataan yang ada jauh dari ideal. Banyak guru sekadar masuk kelas, memberi tugas, lalu pergi. Tak peduli apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Mereka tidak lagi memperbarui metode mengajar, enggan belajar hal-hal baru.
Parahnya, mereka yang diberi tugas tambahan, seperti kepala laboratorium atau wakil kepala sekolah, justru makin menjauh dari tanggung jawabnya. Entah karena jenuh, karena kepemimpinan kepala sekolah yang kurang transparan dalam mengelola dana BOS, atau karena mereka merasa tak dihargai.
Pak Mis menghela napas panjang. Dalam hati ia bergumam, “Jika mereka yang menerima tunjangan saja malas, kenapa saya harus bersusah payah?”
Aku bisa membaca kekecewaan itu dari sorot mata Pak Mis. Dan aku pun bertanya dalam hati, “Bagaimana bisa seorang guru, yang seharusnya menjadi teladan, justru kehilangan rasa tanggung jawab?”
Bel tanda masuk berbunyi, menandai dimulainya jam pelajaran. Diskusi kami terhenti tanpa kesimpulan. Kami bangkit, melangkah menuju kelas masing-masing, membawa segumpal tanya dalam benak.
Rapat Awal Semester
Ketika isu etos kerja guru di sekolah kami ini diangkat dalam rapat awal semester, Pak Dharma, kepala sekolah kami, tampak sendu.
“Bapak-Ibu sekalian,” suaranya tegas, “ada yang tidak beres di sekolah kita belakangan ini! Bagaimana kita bisa berharap sekolah berkembang dan peserta didik bermutu, kalau semangat kerja kita semakin memudar?”
Ia menatap kami satu per satu, seakan ingin menegaskan bahwa ini bukan sekadar keluhan biasa.
“Saya paham, mengajar itu berat. Tapi menjadi guru bukan hanya soal hadir dan mengajar. Jadi guru tanggung jawab moral. Jika kita sendiri tak bisa berkomitmen, bagaimana kita bisa menuntut murid-murid kita untuk disiplin?”
Kata-kata itu membuatku teringat kembali pada niat awal menjadi guru, untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Mendidik anak-anak bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.
Kemudian, suara Pak Dharma merendah, namun tetap penuh berwibawa. “Saya ingin jujur kepada kalian semua. Dana BOS kita mengalami banyak pemotongan. Saya pun bingung mempertanggungjawabkannya.
Sekolah ini sudah terseret dalam pusaran politik luar. Bahkan, beberapa guru di sini merasa menjadi ‘raja’ hanya karena jagoannya menang dalam Pilkada. Mereka lupa, tugas utama mereka adalah mendidik, bukan berpolitik!”
Ruangan mendadak sunyi. “Jika kita terus membiarkan, sekolah ini akan hancur. Peserta didik yang bermutu, jauh panggang dari api. Pendidikan akan makin terpuruk. Dan yang paling dirugikan adalah murid-murid kita!” lanjut Pak Dharma, suaranya penuh emosi yang tertahan.
Aku tersentak. Aku tahu, Pak Dharma menghadapi tekanan besar. Bahkan, tersiar kabar bahwa ia berniat mengundurkan diri karena dalam Pilkada, ia kelompok yang kalah. Ia tak ingin terjebak dalam pusaran politik yang kotor.
Namun, di akhir rapat, ia berdiri tegak dan berkata dengan penuh tekad, “Saya tidak akan tinggal diam. Saya ingin mengubah keadaan ini!”
Lalu, Pak Dharma mengangkat dagunya. “Saya punya prinsip keguruan. Jika kita bisa menjalankannya, sekolah ini akan berubah dan maju.”
Ia lalu menyebutkan satu per satu: Mengajar adalah rahmat, lakukan dengan ikhlas, mengajar adalah amanah; lakukan dengan tanggung jawab, mengajar adalah panggilan; lakukan dengan integritas dan mengajar adalah aktualisasi; lakukan dengan semangat.
Kemudian ulas Pak Dharma lagi, mengajar adalah ibadah; lakukan dengan cinta, mengajar adalah seni; lakukan dengan kreativitas, mengajar adalah kehormatan; lakukan dengan keunggulan. Terakhir, mengajar adalah pelayanan; lakukan dengan kerendahan hati.
Apa yang disampaikan kepala sekolah kami, bagaikan setrum yang menginspirasi pikiranku, mungkin juga guru-guru lain.
Ruangan tetap sunyi. Tapi ada sesuatu yang terasa berubah. Entah apa, tapi seperti ada cahaya kecil yang menyala.
Bersinar Kembali
Bulan-bulan berlalu. Perlahan, sekolah kami mulai berbenah dan berbeda. Pak Mis kembali menemukan semangatnya. Bu Siti sering mengajak kami berdiskusi tentang metode mengajar baru. Pak Rahmat mulai tersenyum lebih sering. Guru lain mulai betah berlama-lama di sekolah.
Kami belum sempurna. Masih ada yang datang terlambat. Masih ada yang mengeluh. Tapi ada satu hal yang pasti, kami tak lagi berjalan tanpa arah.
Dan di setiap ruang kelas, aku melihatnya. Cahaya kecil yang dulu redup, kini mulai menyala kembali.[*]