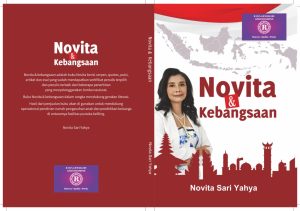Elza Peldi Taher
HATIPENA.COM – Bangun tidur di Minggu pagi, suasana di sekitar rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Deru kendaraan sepi. Burung-burung berkicau riang, seperti mengajak manusia berdialog, mengingatkan bahwa dunia tetap berdenyut meski ritme kesibukan melambat. Minggu memang berbeda. Banyak orang bangun lebih siang dari hari kerja. Pertanyaannya, apakah Hari Minggu hanya sekadar hari libur, atau sebuah ruang untuk kontemplasi?
Hari Minggu membuka kesempatan untuk melambat. Tak ada jam masuk kantor yang menuntut ketepatan, tak ada bel sekolah yang mendesak. Minggu adalah hari ketika orang bisa menjadi dirinya sendiri, sejenak melepaskan seragam peran sosial.
Dalam banyak tradisi agama, ada penekanan bahwa manusia perlu punya satu hari untuk beristirahat. Dalam tradisi Yahudi dikenal “Sabbath”, dalam tradisi Kristen dikenal “Sunday Service”, dalam Islam dikenal “hari Jumat” sebagai waktu berkumpul. Intinya sama: manusia membutuhkan hari untuk jeda. Jeda itu bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa.
Filsuf Denmark Søren Kierkegaard pernah berkata: “Kesunyian adalah bahasa keabadian.” Barangkali, Minggu adalah kesempatan langka bagi manusia modern untuk kembali berbicara dengan keabadian—menyapa ruang batin yang sering kita abaikan di tengah hiruk-pikuk dunia.
Bagi saya pribadi, Minggu adalah hari untuk kembali mencintai rumah. Membaca buku, membersihkan ruang-ruang yang terabaikan sepanjang pekan, atau menata ulang rak buku yang berserakan. Ada pula ritual renang, olahraga yang bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi juga memberi kesegaran batin. Satu jam berenang tanpa henti, menempuh jarak satu kilometer, di sebuah kolam renang di Limo atau Depok, menjadi cara merayakan Minggu. Di luar itu, Minggu juga sering menjadi momen untuk bertemu anak-anak. Obrolan yang di hari biasa tercecer oleh kesibukan, kembali bisa dijalin dengan tenang.
Minggu di kota dan Minggu di desa tentu menghadirkan wajah yang berbeda. Di desa, Minggu lebih sederhana. Orang-orang ke sawah lebih siang, atau sekadar duduk di warung kopi, bercakap soal hasil panen. Anak-anak berlari di lapangan, main bola tanpa alas kaki. Tidak ada belanja massal, tidak ada kerumunan mall. Ada ruang yang lebih lapang bagi waktu, ada kesunyian yang masih terjaga. Di kota, Minggu bagi sebagian besar orang adalah hari paling riuh. Jalan menuju mall penuh, restoran padat, tempat wisata dijejali. Ruang publik dipenuhi keluarga dengan kantong belanjaan dan selfie-stick, seakan kebahagiaan diukur dari seberapa banyak konsumsi. Minggu telah bergeser menjadi “pasar malam di siang hari.”
Friedrich Nietzsche, dengan sinisnya, pernah mengingatkan: “Manusia modern sibuk mencari hiburan agar tidak berjumpa dengan dirinya sendiri.” Kutipan ini terasa relevan: konsumsi massal di hari Minggu kerap bukan soal kebutuhan, melainkan upaya melarikan diri dari keheningan yang justru menakutkan.
Data juga mendukung hal ini. Survei BPS tentang pengeluaran rumah tangga (2023) mencatat bahwa akhir pekan, khususnya Hari Minggu, adalah puncak aktivitas belanja keluarga, terutama untuk makan di luar rumah, rekreasi, dan hiburan. Laporan Nielsen bahkan menemukan bahwa lebih dari 60% transaksi ritel modern di kota besar terjadi pada Sabtu-Minggu, dengan Minggu menjadi puncaknya.
Fenomena ini bukan hanya khas Indonesia. Di Amerika Serikat, riset National Retail Federation (2022) menunjukkan bahwa sekitar 40% pembelanja memilih Minggu sebagai hari utama untuk belanja keluarga, terutama untuk kebutuhan rumah tangga mingguan, pakaian, dan hiburan. Sebaliknya, di beberapa negara Eropa—seperti Jerman, Austria, dan Swiss—undang-undang Ladenschlussgesetz (aturan jam tutup toko) membuat toko tutup pada Hari Minggu. Alhasil, Minggu di sana lebih identik dengan sunyi: orang beribadah, berkunjung ke keluarga, atau berjalan santai di taman tanpa hiruk-pikuk belanja.
Kontras ini menarik. Indonesia dan Amerika memaknai Minggu sebagai “hari konsumsi”, sementara banyak negara Eropa justru mempertahankan Minggu sebagai “hari hening”. Maka pertanyaan yang muncul: kita ingin menempatkan Minggu di jalur yang mana? Menjadi hari belanja tanpa jeda, atau hari istirahat yang memberi ruang bagi jiwa?
Minggu dan Kenangan
Kenangan saya tentang Minggu jauh dari hiruk-pikuk mall. Waktu kecil di kampung, Muara Labuh, Solok Selatan, Minggu saya habiskan untuk mencari rumput makanan sapi. Kadang, bersama teman-teman, kami pergi ke pinggir kali yang sunyi, mandi berjam-jam di air jernih sambil mendengar kicau burung. Dari tepian kali itu, saya menatap bukit-bukit hijau dan puncak Gunung Kerinci yang gagah. Itulah kebahagiaan sederhana yang tak pernah saya lupakan.
Mandi di kali, tertawa bersama kawan, lalu pulang dengan tubuh lelah tapi hati penuh riang—itulah Minggu yang melekat dalam ingatan saya. Sederhana, tapi memberi rasa damai yang sekarang terasa mahal.
Refleksi Penutup
Hari Minggu adalah hadiah kecil yang datang setiap pekan. Ia bukan sekadar hari tanpa kantor, tanpa sekolah, tanpa rapat. Lebih dari itu, Minggu adalah ruang yang dititipkan waktu kepada kita untuk berhenti, menoleh ke belakang, menata ulang diri, dan memandang jauh ke depan.
Kita bisa memilih menghabiskannya dengan hiruk-pikuk konsumsi, atau kita bisa memanfaatkannya untuk menyegarkan jiwa: membaca buku, bercakap dengan keluarga, menulis catatan sederhana, atau sekadar duduk diam mendengar suara burung di pagi hari.
Barangkali, dalam keheningan Minggu itu kita diingatkan bahwa hidup bukan hanya soal berlari, tetapi juga tentang menemukan makna ketika kita berhenti.
Seperti diingatkan Marcus Aurelius dalam Meditations: “Manusia mencari ketenangan di desa, di pantai, atau di pegunungan. Tetapi engkau dapat menemukan ketenangan kapan saja engkau mau — di dalam dirimu sendiri.”
Maka, mari kita rawat Hari Minggu bukan semata sebagai hari libur, tetapi sebagai hari jeda, hari untuk beristirahat, menata batin, dan merenungi apa arti hidup yang sedang kita jalani. (*)
Pondok Cabe Udik Minggu 24 Agustus 2025