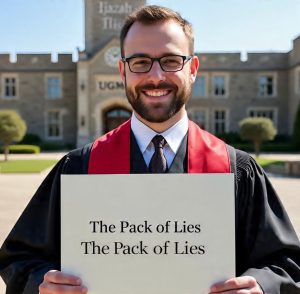Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
HATIPENA.COM – Joko Widodo alias Jokowi mantan presiden saya, ente, dan kita semua sedang sakit. Bukan sakit biasa. Tak boleh terkena sinar matahari langsung. Mari kita ungkap penyakit yang menyerang Pakdhe sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Di negeri tropis yang hidupnya bergantung pada cahaya, kabar datang dari istana, Joko Widodo kini tak boleh lagi terkena sinar matahari langsung. Bukan karena konspirasi, bukan pula karena siang hari kini berbahaya secara politis, tapi karena kulitnya sendiri menolak terang. Sejak kunjungannya ke Vatikan pada April 2025, mantan presiden dua periode itu mengalami iritasi kulit yang disebut “alergi biasa” oleh ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Tapi, di republik yang gemar membaca tanda-tanda, kata biasa sering kali menjadi sinonim dari sesuatu yang tidak ingin dijelaskan.
Absennya Jokowi di perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, 6 Oktober lalu, menjadi bahan bisik-bisik di seluruh negeri. Di tengah parade militer dan pidato Prabowo yang gagah di bawah terik matahari, ketidakhadiran Jokowi justru menjadi sorotan utama. “Beliau masih pemulihan, dianjurkan tidak terkena panas,” kata Syarif. Secara medis terdengar logis. Tapi dalam politik, kalimat itu bergaung seperti metafora, tubuh seorang pemimpin yang pernah berdiri di tengah sorotan kini memilih teduh.
Foto-foto yang beredar menunjukkan wajah Jokowi lebih pucat, lehernya kemerahan, dan ekspresi yang seperti menolak kamera. Iriana pun dikabarkan mengalami gejala serupa. Publik langsung berubah menjadi dokter dadakan, ada yang bilang autoimun, ada yang menyebut vitiligo, bahkan ada yang menuduh sindrom langka. Istana menepis semuanya dengan dua kata sakti, “Alergi biasa.” Tapi semakin dibantah, semakin banyak yang menebak. Begitulah hukum komunikasi di negeri yang alergi terhadap kejelasan.
Secara ilmiah, alergi bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa karena iklim, stres, paparan zat asing, atau obat. Namun lima bulan berlalu, matahari tetap menjadi hal yang harus dihindari. Tubuh Jokowi, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar persoalan medis. Ia adalah simbol dari tubuh republik itu sendiri, lelah, sensitif, dan mungkin terlalu lama berdiri di bawah sorotan panas politik tanpa tabir surya kejujuran.
Namun, kelelahan bukan dosa. Dua periode memimpin bangsa bukan perkara ringan. Ia membawa negara ini melewati pandemi, konflik, dan tekanan ekonomi yang membuat siapa pun bisa kehilangan warna kulit. Bahwa hari ini ia harus beristirahat di bawah atap, itu bukan aib, itu tanda bahwa bahkan seorang pemimpin pun tetap manusia. Tubuhnya, seperti juga tubuh republik, berhak untuk sembuh.
Filsuf Maurice Merleau-Ponty pernah bilang, tubuh adalah cara kita mengalami dunia. Maka ketika tubuh Jokowi menolak terang, barangkali ia sedang mengajarkan kita sesuatu, bahwa tak semua cahaya itu menyehatkan. Ada sinar yang membakar, ada sorot yang menyilaukan. Mungkin, setelah sepuluh tahun di bawah panas kekuasaan, tubuh itu hanya ingin teduh, bukan sembunyi.
Kini Jokowi sesekali masih muncul, bertopi, berjaket, tersenyum sopan. “Saya baik-baik saja,” katanya. Kalimat yang sederhana tapi nyaris tragis. Karena dalam politik, baik-baik saja sering kali berarti sedang tidak baik. Tapi biarlah, ia sudah menanggung cukup banyak sinar, cukup banyak panas. Jika kini ia ingin sedikit teduh, biarkan matahari yang memahami.
Matahari tetap terbit untuk semua, juga untuk mereka yang memilih berteduh. Mungkin, dalam absurditas yang lembut ini, republik sedang belajar sesuatu, terang tak selalu berarti terbuka, dan teduh tak selalu berarti lari. Kadang, keduanya hanyalah cara berbeda untuk tetap bertahan hidup, di negeri yang sinarnya kian menyilaukan. (*)
#camanewak
Sumber foto: detik.com