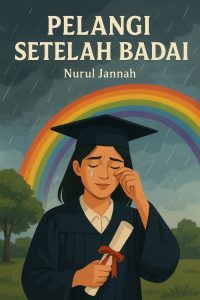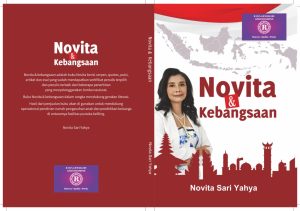Oleh: Anies Septivirawan
HATIPENA.COM – Membaca dan menulis adalah dua kata kerja, namun berbeda makna. Dan kesamaannya adalah sama memiliki awalan “me”.
Membaca dan menulis adalah kegiatan yang berbeda. Meskipun berbeda, namun dua kata kerja ini bagaikan dua sisi mata uang logam yang memiliki kebermanfaatan di tengah berlangsungnya kehidupan manusia dalam berperadaban.
Dan, dua kata kerja ini pula, bak sepasang kekasih, sepasang suami istri yang melengkapi kehidupan alam semesta raya hingga semesta atau jagad kecil di dalam diri manusia.
Sebuah kekuatan besar bernama tuhan telah berpuluh abad yang lalu memerintahkan makhluk berakal bernama manusia agar mau membaca ayat -ayat tidak tertulis berupa peristiwa – peristiwa besar di jagat raya, dan agar mau membaca ayat -ayat tertulis yang tertuang di atas lembar – lembar semua kitab suci agama.
Dengan membaca aksara di semesta raya, kita mengerti, kita berasal dari mana dan akan kemana. Begitu pula membaca dan merangkai huruf demi huruf yang menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf di atas kertas dan buku. Dengan membaca, kita menjadi tahu dan pintar. Maka dari itu, aku lebih senang dan suka membaca.
Kesukaanku terhadap kegiatan membaca, adalah bermula ketika duduk di bangku sekolah dasar kelas dua di kota Jember.
Ingatanku masih tajam dan jernih ketika sepulang dari sekolah, aku selalu disuguhi menu bacaan majalah anak – anak. Bacaan majalah anak – anak pada saat itu yang sering kubaca adalah majalah Bobo dan Ananda.
Kala itu, bapakku yang bekerja sebagai staf rendah di sebuah BUMN di kecamatan Tanggul, Jember, rela merogoh kocek recehnya untuk berlangganan majalah Bobo dan Ananda untukku dan kakakku.
Namun hanya aku yang gemar “melahap” menu-menu sajian bacaan kedua majalah anak -anak itu. Sedangkan kakakku hanya gemar bermain layang-layang dan memancing.
Kegemaran atau kesukaan membacaku sejak kecil berlangsung hingga pada usia remaja ketika aku duduk di bangku SMP. Setelah kurasakan kenikmatan membaca sampai pada titik jenuh, aku mulai sering dilanda kegelisahan. Dan kegelisahan di dadaku mulai mendorongku agar segera bergerak untuk menulis apa saja.
Aku pun mulai menulis seluruh aktivitasku mulai dari pagi hingga aku tidur pada malam hari. Aktivitas itu kutulis di atas kertas buku diary. Meskipun kegiatan menulis di buku diary itu kebanyakan dilakukan oleh anak – anak perempuan atau cewek, aku tidak pernah malu dan minder membawa buku diary kemana – mana.
Selain seluruh aktivitas keseharian, aku juga sering menulis puisi dan sejumlah cerita pendek di dalam buku diary kesayanganku saat itu, aku masih kelas dua SMP di sebuah SMP Negeri favorit di Situbondo pada tahun 1982.
Seiring berjalannya roda waktu yang telah membawaku pada usia remaja hingga lulus sekolah menengah atas, aku mulai gemar coba – coba mengirim karya puisiku ke sejumlah media massa. Meskipun ada banyak media massa yang menolak naskahku, tapi ada juga segelintir media massa berupa koran harian yang rela menerima naskah puisi cintaku di rubrik budaya kala itu.
Ketika memiliki rasa haru dan bahagia ketika puisiku dimuat oleh salah satu koran tidak terkenal di Jakarta, pikiran, jiwa dan hatiku mulai mengambil keputusan agar aku harus selalu menulis. Menulis apa saja tentang kebaikan.
Karena dengan menempuh jalan menulis, bagiku, ion-ion negatif bernama kegelisahan akan musnah lalu terlempar ke luar badan/tubuhku. Badanku sehat. Dan tidak hanya badanku, jiwaku juga waras alias sehat.
Dan aku jadi teringat secuil syair lagu kebangsaan negara kita, “Indonesia Raya” , ciptaan Wage Rudolf Supratman: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya….untuk Indonesia Raya… Indonesia Raya… merdeka…. merdeka….
Kubaca syair lagu kebangsaaku itu sangat teliti dan berhati-hati agar tidak terbalik: “Bangunlah jiwanya… bangunllah badannya …” .
Kalau kita membaca dan menyanyikan secara terbalik menjadi “bangunlah badannya… bangunlah jiwanya…, keadaannya akan menjadi negeriku pada saat ini. Semoga kita tidak membaca dan memaknainya secara terbalik, agar negeriku selalu baik – baik. Salam akal sehat. (*)
Malang, Paruh Mei 2025