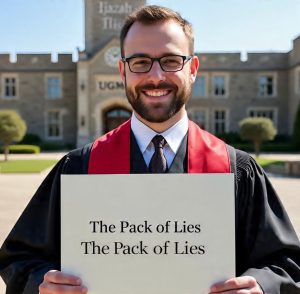Oleh ReO Fiksiwan
“Dan aku pun menjadi manusia bebas, karena aku bisa berpikir dan menulis.” — Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), Bumi Manusia (1988).
HATIPENA.COM – Dalam pertumbuhan karya-karya sastra kontemporer yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan jejaring digital, munculnya sastra hibrida menjadi penanda penting pergeseran estetika dan ideologis dalam praktik penulisan dan pembacaan.
Sastra hibrida tidak hanya merujuk pada pencampuran bentuk—antara prosa dan puisi, antara narasi dan esai—tetapi juga pada pencampuran suara, identitas, dan posisi epistemologis yang saling bersilang.
Dalam konteks ini, pendekatan poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak (83), profesor di Columbia University dan aktif secara intelektual dalam bidang teori poskolonial, feminisme, dan kritik sastra, memberikan lensa tajam untuk membaca ulang karya-karya sastra yang menantang struktur representasi dominan.
Dalam era yang disebut sebagai cyberliterary — di mana teks tidak lagi terikat pada medium cetak, melainkan beredar dalam jaringan digital yang cair dan interaktif — membaca sastra apapun harus memperkaya perspektif pemaknaan interteks-interkultur yang luas.
Spivak, dalam esainya yang monumental Can the Subaltern Speak? (1988;1999) mengajukan pertanyaan mendasar tentang kemungkinan suara dari mereka yang terpinggirkan dalam struktur wacana global.
Ia menunjukkan bahwa bahkan dalam upaya representasi yang paling simpatik sekalipun, suara subaltern sering kali tereduksi atau bahkan terhapus oleh mekanisme epistemik Barat.
Dalam konteks sastra hibrida, pertanyaan Spivak menjadi relevan ketika kita membaca karya seperti Beloved (1987) karya Toni Morrison (1931-2019) dan Impian Labirin (LKiS, 1999) karya Jorge Luis Borges (1899-1986).
Kedua teks ini, meski berasal dari latar budaya dan sejarah yang berbeda, sama-sama mengusung strategi naratif yang membongkar struktur representasi tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna.
Beloved adalah sebuah narasi yang menggabungkan sejarah perbudakan dengan elemen magis dan psikologis, menciptakan ruang naratif di mana trauma kolektif dan ingatan personal saling berkelindan.
Morrison tidak hanya menulis tentang subaltern—ia menulis dari dalam luka subaltern itu sendiri, menghadirkan suara yang selama ini dibungkam oleh sejarah resmi.
Dalam perspektif Spivak, Beloved adalah upaya artikulasi yang kompleks, di mana subaltern tidak sekadar “berbicara” tetapi juga mengganggu tatanan wacana yang mengatur siapa yang boleh berbicara dan bagaimana.
Beloved mengisahkan protagonis, Sethe, seorang mantan budak yang dihantui oleh roh anaknya yang telah meninggal.
Kisah Sethe menggambarkan trauma perbudakan, ingatan, dan identitas dengan gaya naratif yang hibrid dan penuh kekuatan emosional.
Morrison menggunakan bentuk hibrida untuk menolak linearitas sejarah dan membuka kemungkinan bagi pembacaan yang lebih etis terhadap pengalaman yang terpinggirkan.
Sementara itu, Impian Labirin dari Borges, adalah eksplorasi metafiksi yang mengaburkan batas antara realitas dan ilusi, antara penulis dan pembaca, antara pusat dan pinggiran.
Borges menciptakan dunia teks yang berlapis-lapis, di mana makna tidak pernah final dan identitas tidak pernah tunggal.
Dalam perspektif Spivak, Impian Labirin dapat dibaca sebagai kritik terhadap logika representasi Barat yang mengandaikan transparansi dan stabilitas makna.
Borges, dengan gaya naratifnya yang hibrid dan penuh paradoks, mengganggu asumsi-asumsi epistemologis yang menjadi fondasi kolonialisme intelektual.
Membaca gaya Borges melalui Spivak mengaburkan batas antara realitas dan fiksi, antara pusat dan pinggiran, antara pengetahuan dan ilusi—sebagai bentuk gangguan terhadap struktur epistemologis Barat yang mapan.
Dalam Impian Labirin, yang merupakan kumpulan cerita dan esai terjemahan, Borges menulis: “Saya membayangkan bahwa surga adalah semacam perpustakaan.”
Ia tidak menulis tentang subaltern secara eksplisit, tetapi struktur teksnya sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi naratif yang homogen.
Mengacu pada era cyberliterary, di mana teks beredar dalam bentuk digital dan interaktif, pendekatan Spivak terhadap etika representasi menjadi semakin penting.
Teknologi tidak serta-merta membebaskan suara subaltern; ia bisa menjadi alat baru bagi penghapusan dan komodifikasi.
Sastra hibrida, dalam bentuknya yang cair dan eksperimental, menawarkan kemungkinan untuk menantang logika ini.
Ia membuka ruang bagi suara-suara yang tidak terdefinisi, yang tidak sesuai dengan kategori-kategori dominan, dan yang menuntut pembacaan yang lebih reflektif dan etis.
Melalui karya-karya Beloved dan Impian Labirin, juga Pramoedya, misal, kita melihat bagaimana sastra hibrida dapat menjadi medan artikulasi yang kompleks, di mana pertanyaan Spivak tentang siapa yang berbicara dan bagaimana suara itu didengar menjadi sangat relevan.
Dalam membaca dan menulis di era cyberliterary, kita diajak untuk tidak hanya mengapresiasi bentuk, tetapi juga untuk mempertanyakan struktur representasi yang membentuk makna.
Membaca sastra hibrida, dalam perspektif Spivak, bukan sekadar eksperimen estetika, tetapi juga tindakan etis dan politis yang menantang batas-batas wacana dan membuka kemungkinan bagi suara yang selama ini dibungkam. (*)
#coverlagu: Lagu “Derai-Derai Cemara (1949) Musikalisasi Puisi Chairil Anwar” oleh Banda Neira dirilis pada 29 Januari 2016 sebagai bagian dari album mereka yang berjudul „Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti.“
Lagu ini merupakan interpretasi musikal dari puisi terakhir Chairil Anwar sebelum wafat pada tahun 1949.
Banda Neira, duo musik, Ananda Badudu dan Rara Sekar, mengubah puisi DDC Chairil Anwar menjadi lagu dengan aransemen yang melibatkan dawai dan piano hingga menciptakan suasana melankolis yang selaras dengan isi puisi.