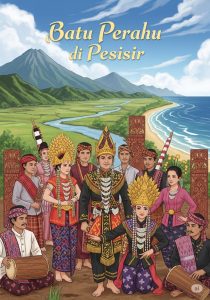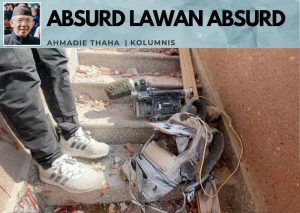Ilhamdi Sulaiman
HATIPENA.COM – Di kampungku, orang sepertiku dijuluki “orang kalah.” Julukan itu menempel serupa lumut di punggung batu sungai, diam-diam licin, susah disikat. Begitulah mereka menamai siapa saja yang pulang ke tanah asal pada usia senja setelah merantau. Dalam adat kami, lelaki sejati diukur dari seberapa jauh debu rantau melekat pada tapaknya dan seberapa asing tanah yang akan menelan jasadnya kelak: pulang hanya untuk dikafani.
Mereka membungkus perintah itu dengan petatah-petitih halus, harum sekaligus menusuk:
“Ka rantau madang di hulu, babuah babungo balun.
Marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun.”
Nasihat itu dulu hanya gema di telingaku; kini kudengar ia sebagai komando tabuh genderang: pergilah, taklukkan dunia, jangan sekadar hidup,jadilah cerita.
Aku pulang bukan karena tersungkur. Masa baktiku sebagai aparatur negara telah purna; lencana kusimpan, bukan kubuang. Istriku masih setia menopang musim. Kami ingin menanam sisa usia pada ladang kelahiran, tempat dahulu kami memancang pohon kenangan bersama orang-orang yang kini tinggal nama tersusun di pandam kuburan adat.
Ada banyak alasan kami kembali, tapi barangkali angin kampunglah yang paling lihai memanggil.
Di kota, udara seperti kaca retak,tajam, memantulkan kelelahan. Di sini, napas terasa seperti meneguk embun dari gelas,waktu melambat sebagaimana layang-layang yang sengaja diulur talinya.
Pagi-pagi kami duduk di beranda, menyeruput kopi Hitam pahit,sementara kabut turun mengelus pundak bukit hingga warnanya berubah hijau basah.
Anak sulungku kini bekerja di Departemen Keuangan, adiknya mekanik mesin mobil Eropa di Jakarta, dan anak perempuan mengembara bersama suaminya yang tentara di rimba Papua. Mereka tak lagi memerlukan kami kecuali untuk alasan rindu.Tiap bulan mereka mengirim uang untuk ibunya, bukan karena kami lapar, melainkan karena kasih sayang dan bakti mereka pada orang tuanya.
Orang kampung tahu itu. Mereka menyaksikan anak-anakku pulang Lebaran dengan mobil dan setelan serapi daun sirih. Mereka tahu aku tak pernah meminta sebutir beras pun. Namun, sebutan “orang kalah” tetap melekat seperti cap merah di surat dinas rahasia.
Suatu malam sehabis Isya, aku singgah ke kedai kopi
di simpang masjid ruang mungil yang berbau kayu terbakar dan biji kopi terpanggang. Di sanalah lidah kampung menari. Kumandang cerita, gosip, dan peluru sindiran melesat bebas. Aku duduk di bangku kayu tua, memesan kopi hitam tanpa gulapahitnya kugunakan untuk menyilet sunyi.
Dari sudut ruangan, obrolan mengalir seperti arus sungai di musim hujan, deras, tak peduli siapa saja bisa hanyut.
Manap, lelaki separuh baya yang pernah merantau ke Pekanbaru namun kini lebih sering bercengkerama dengan asap rokok ketimbang keringat kerja, melempar batu ke permukaan air.
“Sekarang banyak orang pulang kampung karena tak tahan sengsara di kota,” ujarnya, suaranya serak seperti gesekan besi karatan. “Gagal jadi orang besar, baliklah ke kampung, cari tenang di atas reruntuhan impian.”
Aku tahu sindiran itu ditujukan padaku. Sunyi mendadak menggantung di langit-langit kedai, jaring laba-laba waktu. Aku mengangkat cangkir perlahan, menatap pusaran kopi yang mulai mendingin.Lalu ku cicipi sedikit gelapnya, dan kulepas cangkir kembali ke piring.
“Jika keberhasilan hanya diukur dari alamat KTP dan seberapa sering nama kita disebut di rapat kota,” kataku serendah desir kapas, “maka benar, aku kalah. Tetapi bila berhasil artinya punya keluarga utuh, tidur nyenyak tanpa hutang, dan dada lapang menampung angin pagi, barangkali akulah yang menang.”
Manap tertawa, tapi tawanya rapuh, semacam paku karatan yang dipaksa berdering. Obrolan bubar, tersisa dengung lampu petromax. Di luar, malam menyerap setiap kata yang tak sanggup diucap.
“Kita terlalu rajin menilai kebun orang dari balik pagar bambu,” tambahku, sebelum bangkit. “Padahal kita tak tahu biji apa yang disemai di tanahnya. Mungkin mawar, mungkin ilalang.”
Aku berjalan ke pemilik warung, meletakkan selembar uang, lalu berbisik, “Untuk semua gelas yang belum terbayar malam ini.” Setelah itu kutinggalkan sisa kopi yang tak lagi hangat Untuk aku seruput.
Beberapa pagi setelahnya, istriku pulang dari warung dengan mata serupa hujan terkurung awan.
“Ada apa?” tanyaku, melihat tangannya gemetar menggenggam kantong bawang dan cabe.
Ia diam lama.Hening yang terasa seperti jarak antara petir dan gemuruh.
“Waktu kutanya harga kunyit, seorang ibu nyeletuk, ‘Kalau sudah pulang kampung, semua jadi murah ya? Termasuk harga diri.’”
“Padahal kita nggak pernah minta apa-apa. Bahkan harga kunyit pun kita bayar tunai,” katanya lirih, sambil memutar-mutar sendok di gelas tehnya yang sudah dingin.
Aku menggenggam tangannya.
“Biarkan saja. Mereka bicara dari mulut, kita hidup dari kenyataan. Mereka mungkin merasa menang, tapi mereka belum tentu bahagia.”
Ia mengangguk pelan. Tapi aku tahu, luka dari sindiran perempuan bisa bertahan lebih lama dari luka apa pun.
Sejak malam di kedai kopi, dan pagi itu di warung bumbu, aku dan istriku tahu,pulang kampung bukan cuma soal rumah dan udara segar. Tapi juga kesiapan hati untuk menghadapi orang-orang yang tak pernah benar-benar mengerti kenapa kami memilih pulang.
Dan kami tetap di sini. Menanam serai, menyeduh kopi, dan menua dengan tenang di tanah yang pernah mengusir kami diam-diam.
Kadang aku tersenyum sendiri.
Jika pulang dengan tenang dianggap kalah, maka biarlah aku jadi pecundang yang bahagia.
Karena di mataku, kalah bukan soal pandangan orang tapi ketika kita kehilangan diri sendiri demi tepuk tangan dan pujian. (*)
5 April 2025