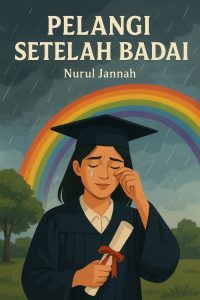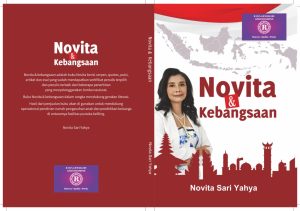Oleh: Nia Samsihono
HATIPENA.COM – Adri Darmadji Woko, penyair yang malang melintang di dunia puisi, pernah menyebut bahwa penyair radikal adalah mereka yang jatuh bangun karena puisi. Ini bukan sekadar metafora romantik, melainkan sebuah penegasan tentang kedalaman relasi eksistensial antara penyair dan puisinya. Seorang penyair radikal hidup dalam denyut puisinya, mempertaruhkan hidup, keyakinan, bahkan reputasi demi satu baris kata yang jujur dan membebaskan. Namun, apakah itu satu-satunya cara memahami keradikalan seorang penyair?
Apa Itu radikal? Secara etimologis, radikal berasal dari kata Latin radix yang berarti “akar”. Jadi, sikap radikal bukan semata soal ekstremisme atau kekerasan seperti dalam persepsi populer, melainkan keberanian untuk menyentuh persoalan sampai ke akar-akarnya. Seorang pemikir radikal adalah orang yang tidak puas dengan permukaan. Ia menggali sebab-musabab, mencabut ilusi, dan berani mengguncang kenyamanan demi kebenaran yang lebih dalam.
Siapa penuair Itu? Penyair adalah pencari makna yang menggunakan bahasa sebagai alat pembongkar. Ia tidak hanya menulis untuk indah-indahan, tapi untuk mengatakan yang tak terkatakan, menyuarakan yang dibungkam, dan melihat dengan mata batin yang jeli. Dalam puisi, penyair mengolah kenyataan menjadi permenungan, luka menjadi lentera, dan protes menjadi nyanyian abadi.
Penyair radikal, maka siapa?Dengan demikian, penyair radikal adalah mereka yang bersetia pada akar realitas dan keberanian menafsir ulang dunia lewat puisi.
Bukan sekadar mereka yang “jatuh bangun karena puisi” secara fisik atau sosial (meski itu pun penting), tetapi mereka yang mempertaruhkan jiwanya demi menemukan kebenaran yang otentik melalui puisi.
Mereka tak ragu mematahkan bentuk lama jika bentuk itu tak lagi menampung derita zaman. Mereka tak segan menjadi asing dari arus utama, bahkan dicemooh, karena puisinya dianggap terlalu menggugah atau terlalu “membuka luka”. Contohnya, Wiji Thukul. Puisinya bukan hanya karya sastra, tapi juga alat perlawanan.
Ia hidup dalam dan karena puisi. Tapi juga, ia “jatuh” karena puisi—hingga hilang dan menjadi ikon perlawanan. Atau Chairil Anwar, yang dalam puisinya membawa semangat eksistensial, individualisme, dan keberanian menggugat Tuhan, zaman, dan hidup itu sendiri. Chairil adalah radikal dalam bahasa, tema, dan sikap.
Radikal bukan berarti beringas.
Perlu digarisbawahi, penyair radikal bukan berarti beringas atau sok keras kepala. Mereka bisa sangat lembut, sangat sunyi, namun tetap mengguncang kesadaran pembaca.
Radikalisme puisi bisa hadir dalam bisikan, dalam tanya yang tak dijawab, atau dalam kesenyapan yang mengiris. Penyair seperti Sapardi Djoko Damono mungkin tampak tidak radikal karena puisinya lembut dan lirih. Tapi sesungguhnya ia radikal dalam cara melihat cinta, waktu, dan kefanaan sebagai medan filsafat yang dalam—ia mengajak kita menyentuh akar-akar keberadaan manusia.
Mungkinkah penyair radikal itu hidup dalam dan karena puisi? Adri Darmadji Woko memberi kita pintu untuk merenungkan keradikalan penyair. Bahwa seorang penyair bisa saja kehilangan banyak hal karena puisinya—kenyamanan, jabatan, bahkan keselamatan. Namun lebih dari itu, penyair radikal adalah mereka yang hidup karena puisi, dan tak sanggup hidup tanpanya. Mereka bukan hanya menulis puisi. Mereka adalah puisinya.
Kenalkah penyair seperti itu? Atau mungkin kamu sendiri sedang jadi salah satunya? (*)
Jakarta, 7 Juli 2025