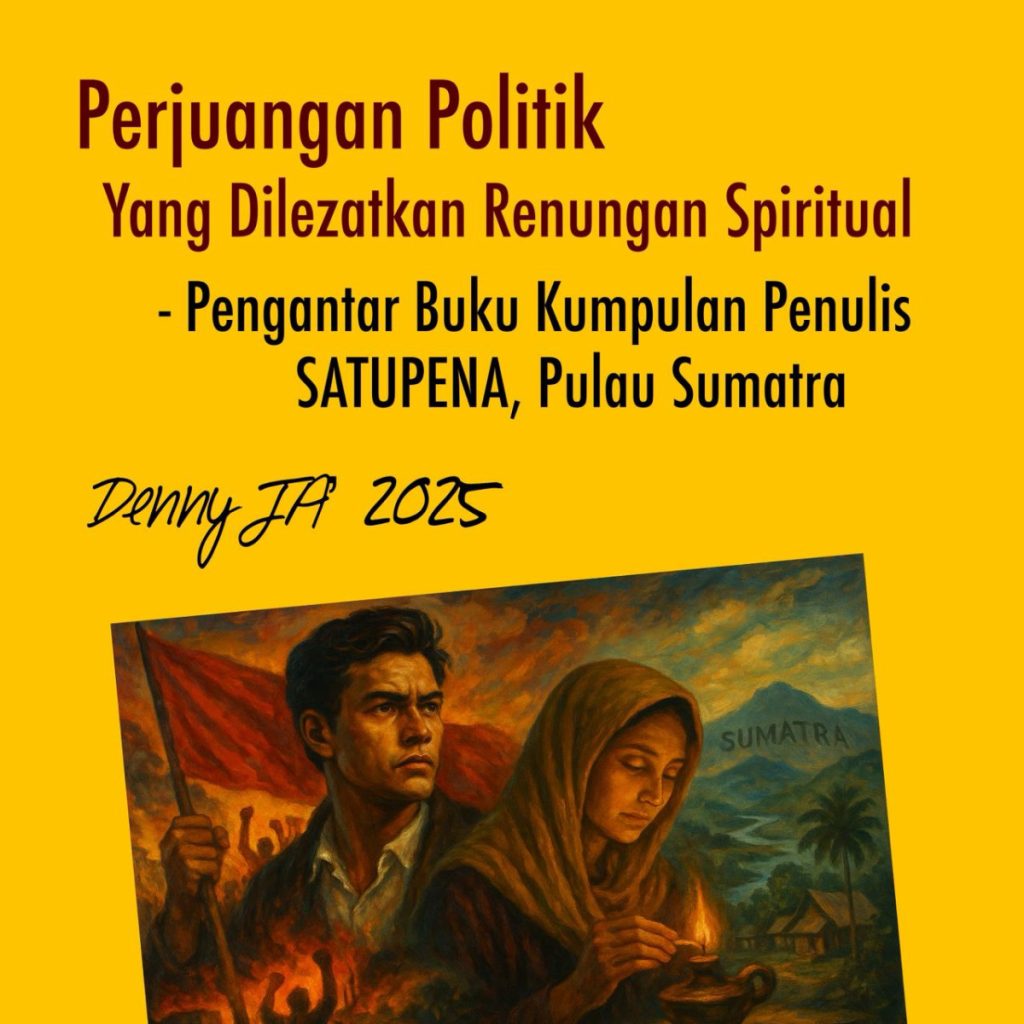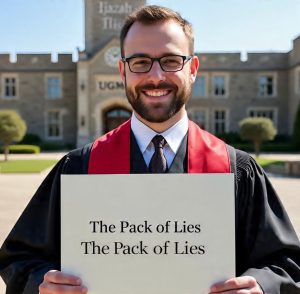- Pengantar Buku SATUPENA Pulau Sumatra, “Persilangan Sumatra” (2025)
Oleh Denny JA
“Setiap malam ia menyalakan lampu kecil di rumahnya—
bukan untuk menerangi,
tetapi untuk mengingat.”
HATIPENA.COM – Lampu kecil itu bukan sekadar cahaya fisik; ia adalah metafora tentang keteguhan perempuan Aceh yang menolak padam meski diterpa gelap sejarah.
Ia menyalakan bukan untuk mencari jalan, melainkan untuk menjaga makna keberadaan—bahwa mencintai dan mengingat adalah bentuk tertinggi dari perlawanan terhadap lupa.
-000-
Puisi ini berakar dari kisah nyata yang panjang: perang dan kekerasan yang membekas di Aceh selama lebih dari tiga dekade.
Sejak awal tahun 1976, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia menelan ribuan nyawa.
Desa-desa dibakar, perempuan kehilangan suami, anak-anak menjadi yatim dalam sekejap.
Namun di tengah situasi itulah lahir kekuatan baru yang sunyi—perempuan-perempuan Aceh yang menjadi penjaga kehidupan.
Mereka menghidupi anak-anak, menenun kain, menanam padi, mengubur orang yang mereka cintai tanpa air mata, lalu berdoa.
Bait itu adalah inti dari seluruh napas puisi “Menafsir Ulang Duka di Tanah Rencong” karya Delia R. — sebuah puisi yang bergetar antara kehilangan dan iman.
Delia menangkap satu fragmen kecil dari kisah besar itu: seorang istri yang setiap malam menyalakan lampu, seolah berkata,
“Aku masih di sini. Cinta ini belum mati, dan negeri ini masih bisa sembuh.”
Puisi ini bukan tentang perang, tapi tentang apa yang tersisa setelah perang usai: kemanusiaan.
Ini cuplikan dari satu dari 22 tulisan di dalam buku antologi Persilangan Sumatera, karya para penulis SATUPENA Pulau Sumatra, yang datang dari aneka provinsi: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung .
-000-
Dalam sejarah sastra dunia, gema emosional puisi Delia menemukan saudara sejiwa pada karya Anna Akhmatova, penyair besar Rusia, dalam puisinya “Requiem” (1935–1940).
Akhmatova menulis dari tengah rezim Stalin yang menahan dan mengeksekusi jutaan warganya, termasuk putranya sendiri di Leningrad.
Ia menulis bukan dari podium, tetapi dari antrean panjang di depan penjara, di mana ibu-ibu berdiri tanpa suara.
Dalam satu baris yang terkenal ia menulis:
“Aku ingin memanggil kalian semua dengan nama,
tetapi daftar itu telah diambil malaikat.”
Seperti Delia, Akhmatova tidak menulis dengan kemarahan, melainkan dengan rasa duka yang suci.
Keduanya sama-sama perempuan yang berbicara dari posisi tak berdaya secara sosial, namun kuat secara spiritual.
Delia menyalakan lampu kecil di rumah Aceh; Akhmatova menyalakan lilin di jantung Rusia—
dua perempuan yang memelihara terang agar dunia tidak sepenuhnya jatuh ke dalam gelap.
-000-
Puisi “Menafsir Ulang Duka di Tanah Rencong” mengajarkan kita bahwa perdamaian tidak lahir dari meja perundingan, melainkan dari hati yang bersedia memaafkan tanpa melupakan.
Dalam sejarah bangsa mana pun, selalu ada perempuan yang berdiri di antara reruntuhan, bukan untuk meratap, tetapi untuk menjaga cahaya agar tidak padam.
Delia R. menulis dari tempat itu—dari titik paling sunyi yang justru menjadi sumber kekuatan manusia.
Dan karena itulah, puisi ini tak hanya berbicara tentang Aceh, tetapi tentang seluruh dunia yang pernah kehilangan, namun masih punya alasan untuk menyalakan lampu.
-000-
Setiap zaman punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka dan mengabadikan cahaya.
Di Sumatra—pulau dengan sejarah gemetar dan memori yang panjang—orang-orang menulis bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk bertahan.
Buku ini lahir dari kebutuhan yang lebih dalam daripada sekadar dokumentasi sastra.
Ia adalah cara generasi hari ini menafsirkan ulang arti menjadi manusia Indonesia setelah semua yang dilalui—perang, kemiskinan, kehilangan, dan keajaiban kecil yang masih bertahan di antara reruntuhan harapan.
Buku ini ditulis oleh para penulis SATUPENA Pulau Sumatra, dari berbagai provinsi.
Nama-nama mereka mungkin tak semua dikenal luas di kancah nasional, namun tiap kata yang mereka tulis adalah serpihan kejujuran.
Mereka datang dari berbagai latar—guru, wartawan, sastrawan, penyair, dosen, ibu rumah tangga—tetapi dipertemukan oleh satu kesadaran yang sama:
Bahwa menulis adalah cara terbaik untuk menyelamatkan kemanusiaan dari keheningan.
-000-
Dalam pengantarnya, Anwar Putra Bayu—Koordinator Satupena Sumatra—menyebut buku ini sebagai hasil kerja kolektif lintas provinsi yang lahir dari semangat
“Melihat Indonesia dari Kota dan Desa Kami.”
Ia menulis bahwa antologi ini bukan sekadar dokumentasi karya, melainkan ruang dialog antara kota dan desa, antara penulis muda dan penulis mapan, antara yang klasik dan yang baru.
“Persilangan Sumatra,” tulis Anwar, “adalah pertemuan dari berbagai asal, generasi, dan kebudayaan yang membentuk identitas bersama.”
Baginya, antologi ini bukti bahwa semangat menulis di Sumatra belum padam—ia terus tumbuh sebagai pelita dari pinggiran, menerangi Indonesia dari batas yang sunyi .
-000-
Isi buku ini beragam seperti laut yang mengelilingi pulau ini:
- Esai reflektif, yang berbicara dengan tenang namun menghunjam seperti doa di tengah malam.
- Puisi dan puisi-esai, yang memadukan jantung puisi dan nalar esai, menjadikan fakta sosial terasa seperti mimpi yang suci.
- Cerpen, kisah pendek dengan napas panjang, yang membawa kita menelusuri hati manusia dengan kesepian dan keberanian yang tak biasa.
Kumpulan ini bukan sekadar antologi sastra—melainkan peta emosi masyarakat Sumatra kontemporer, dari pantai Sabang yang sunyi hingga kota Palembang yang bising oleh arus modernitas.
Jika dibaca perlahan, buku ini membangun pohon tema yang akarnya tumbuh dari tanah kehidupan nyata.
Ada tiga cabang besar yang menaungi keseluruhan karya:
1. Luka dan IngatanTentang perang, kehilangan, dan perempuan yang menanggung sunyi sejarah.
Di sini, bahasa menjadi kuburan dan nyanyian sekaligus.
2. Kehidupan Urban dan Keterasingan ModernTentang kota yang tumbuh tanpa jiwa, anak muda yang berlari tapi tak tahu arah, pekerja yang kehilangan makna di balik beton dan lampu.
3. Alam dan Kesadaran SpiritualTentang sungai yang menghitam, laut yang menua, gunung yang menyimpan rahasia,
dan manusia yang mulai sadar bahwa kerakusan adalah dosa paling sunyi di dunia.
-000-
Tiga Hal yang Membuat Buku Ini Penting
- Ia Menyambung Tradisi yang Terputus
Buku ini menjadi jembatan antara sastra Sumatra masa lalu—yang besar dengan nama-nama seperti Hamka, Chairil, dan Idrus—dengan generasi kini yang menulis dari pinggiran.
Ia membuktikan bahwa Sumatra bukan sekadar bab sejarah sastra, tetapi nadi yang masih berdenyut.
- Ia Merekam Kebenaran yang Tak Dicatat Negara
Karya-karya di sini adalah arsip emosi bangsa, bukan laporan resmi.
Mereka menulis dengan darah sehari-hari, bukan tinta birokrasi.
Karena itu, buku ini penting: ia menjaga ingatan agar tidak dibunuh oleh keheningan.
- Ia Menjadi Cermin Kesadaran Kolektif Baru
Generasi penulis hari ini tidak lagi menulis untuk melawan negara, tetapi untuk menyembuhkan manusia.
Sumatra dalam buku ini bukan sekadar ruang geografis, tetapi metafora dari jiwa bangsa yang sedang belajar memaafkan diri sendiri.
-000-
Beberapa tulisan yang dramatis.
- “Menafsir Ulang Duka di Tanah Rencong” – Delia R. (Aceh)
Delia menulis seperti seseorang yang berdoa di atas luka.
Ia menceritakan perempuan Aceh yang kehilangan suami di masa perang, namun tetap menyalakan lampu kecil di rumahnya setiap malam sebagai tanda cinta yang tak padam.
Tulisan ini penting karena mengingatkan bahwa perdamaian bukan keputusan politik, melainkan kerja spiritual.
- “Luka di Ujung Lampu Merah Palembang” – Isbedy Stiawan ZS (Lampung)
Potret getir kehidupan urban di bawah lampu merah: anak jalanan, sopir ojek, dan ibu kota yang kehilangan nurani.
Tulisan ini mengguncang karena mengubah realitas sosial menjadi puisi kemanusiaan.
- “Menunggu Cahaya di Hulu Siak” – Husnu Abadi (Riau)
Refleksi ekologis dan spiritual tentang sungai yang kehilangan kesucian.
Tulisan ini menyadarkan bahwa perjuangan lingkungan adalah doa panjang untuk bumi.
-000-
Buku ini penting bukan hanya karena isinya, tetapi karena jiwanya.
Ia tidak berpretensi muluk-muluk untuk “mengubah dunia,”
tetapi pelan-pelan, seperti hujan di pagi hari, ia menyembuhkan cara kita memandang kehidupan.
Dalam setiap halaman, kita belajar bahwa:
- Menjadi manusia berarti berani ingat, bukan melupakan.
- Menjadi penulis berarti menjaga agar bahasa tidak mati di tengah kebisingan dunia.
- Menjadi bagian dari bangsa berarti terus memeluk luka yang sama, sambil tetap menyalakan lilin di tengah gelap.
Sumatra—dalam imajinasi buku ini—bukan sekadar tanah, tetapi jiwa yang hidup.
Ia bergetar di setiap kata, bernapas di setiap kisah, dan menangis dalam setiap jeda sunyi.
Para penulisnya bukan ingin dikenal, tetapi ingin dikenang:
bahwa mereka pernah menulis dengan jujur di masa ketika kejujuran dianggap naif.
Buku ini adalah bukti bahwa kata masih bisa melawan kabut,
dan bahwa di balik semua luka yang kita tanggung sebagai bangsa,
masih ada yang percaya:
selama ada yang menulis dengan hati,
Indonesia tak akan pernah kehilangan arah. (*)
Jakarta, 9 Oktober 2025
Referensi
1. Anwar Putra Bayu. Kata Pengantar Satupena Sumatera. Dalam Persilangan Sumatera. Satupena Indonesia, 2025 .
2. Anna Akhmatova. Requiem (1935–1940). Terbit pascaperang, diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Stanley Kunitz, 1963 – puisi klasik dunia tentang duka, kehilangan, dan daya spiritual perempuan di tengah represi.
-000/
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World