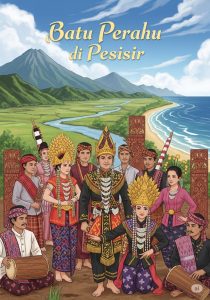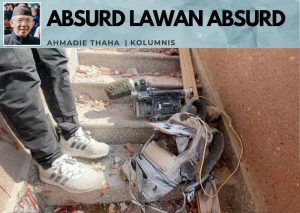Oleh: Ririe Aiko
HATIPENA.COM – Eza, 28 tahun, lulusan universitas negeri ternama, penuh prestasi dan berlembar-lembar sertifikat dari TK hingga kuliah—kini harus menelan kenyataan pahit: ia masih menganggur.
Bukan karena malas. Justru sebaliknya, Eza lebih rajin dari sebagian orang yang sudah punya pekerjaan. Ia bangun pagi, rapi berpakaian, menata berkas lamaran seperti hendak berangkat kerja. Tapi bukan ke kantor tujuannya—melainkan ke tempat fotokopi, atau sekadar duduk di warung kopi, menanti kabar lowongan dari grup pencari kerja.
Lima tahun berlalu sejak ia lulus. Ratusan lamaran telah dikirim, puluhan wawancara dijalani. Ia hafal bentuk-bentuk penolakan, yang intinya sama: “Maaf, bukan kamu yang kami cari.” Bahkan, mungkin map coklat yang ia beli lebih sering jadi bungkus gorengan ketimbang sampai ke tangan HRD.
Padahal, IPK-nya cumlaude. Di SMA, ia langganan olimpiade, membawa pulang medali demi medali. Namanya sempat dibanggakan sekolah, dipajang di media sosial oleh para guru. Tapi kini, semua penghargaan itu tersimpan rapi dalam laci—berdebu, nyaris dilupakan.
Dompetnya pun lebih sering berisi catatan utang daripada uang. Semua demi ongkos cetak, fotokopi, dan transport mencari kerja. Kadang ia bertanya dalam hati: Apakah semua perjuangan itu sia-sia?
Lebih menyakitkan lagi, Eza mencari kerja di tengah gelombang PHK massal. Ribuan kehilangan pekerjaan—sementara ia bahkan belum pernah diberi kesempatan untuk memulai.
Ia mulai bertanya-tanya:
Apakah negeri ini tak lagi butuh orang berpotensi?
Apakah nilai tinggi dan piagam penghargaan kini cuma formalitas?
Atau, jangan-jangan negeri ini hanya ramah bagi yang punya koneksi, bukan kompetensi?
Kisah Eza memang fiktif. Tapi getirnya nyata. Ia satu dari sekian banyak “Eza-Eza” lain—terjebak dalam siklus lamaran, wawancara, lalu ditolak.
Sementara itu, negeri ini terus bicara soal bonus demografi, generasi emas, dan kebanggaan atas prestasi anak bangsa. Tapi lupa, bahwa banyak anak-anak berprestasi kini duduk termenung di kamar—bukan karena menyerah, tapi karena tak pernah diberi ruang untuk membangun masa depan. Kesempatan tertutup oleh kualifikasi yang kadang tak masuk akal.
Selamat datang di negeri para pengangguran
—tempat di mana sertifikat hanya hiasan, ijazah jadi pelengkap, dan masa depan? Entah di mana. (*)