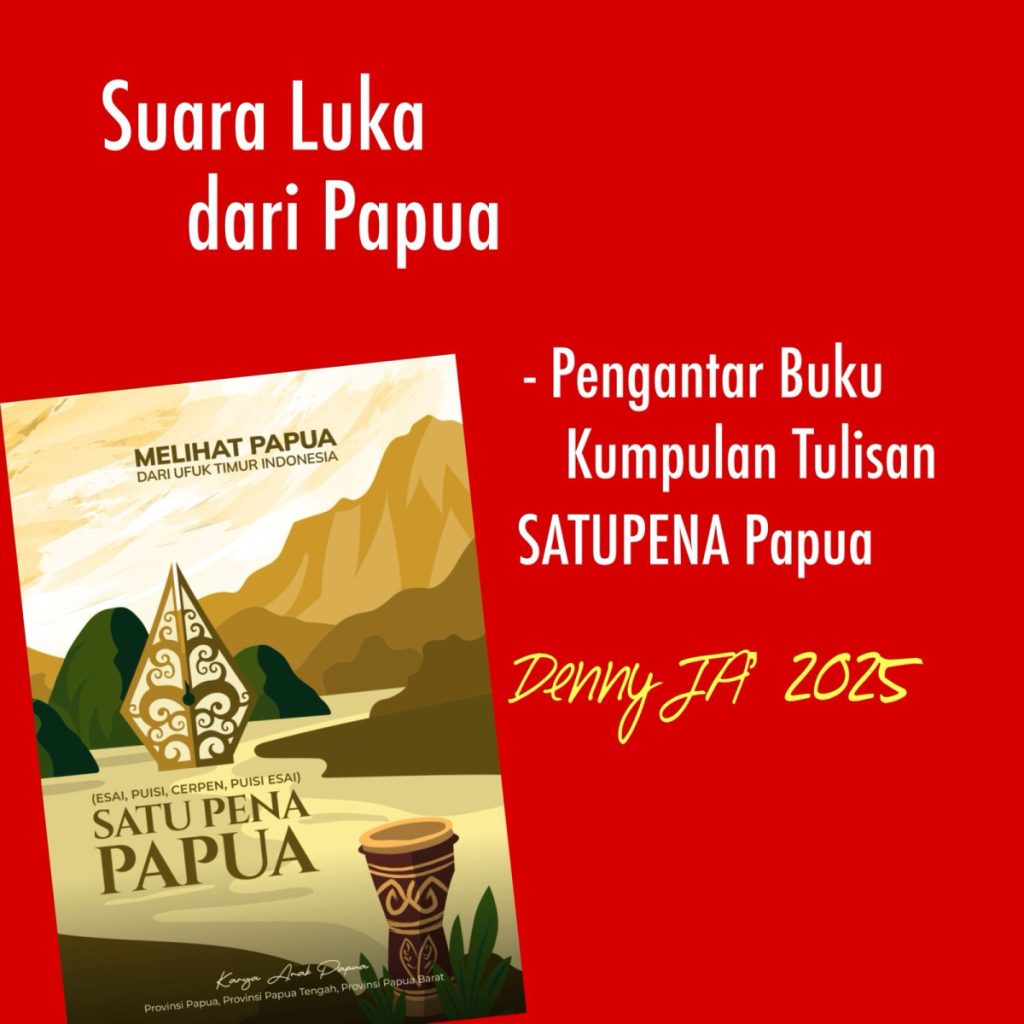- Pengantar Buku Karya Perkumpulan Penulis SATUPENA Papua: Melihat Papua dari Ufuk Timur Indonesia
Oleh Denny JA
“Tambang, katanya emas bagi negeri,
tapi bagi anak pulau,
ia hanyalah perampas masa depan,
mencuri warisan yang tak ternilai.”
HATIPENA.COM – Empat baris puisi Acil Daat Tambang di Raja Ampat ini bagai palu nasib yang menghantam hati nurani kita.
Ia lahir bukan dari imajinasi kosong, melainkan dari pengalaman yang berdenyut di tubuh masyarakat Papua.
Ini surga yang seharusnya diwariskan pada generasi, justru dikoyak oleh mesin-mesin tambang.
Di tanah karang biru Raja Ampat, laut mestinya menjadi kitab kebahagiaan: ikan yang menari, burung cenderawasih yang berkabar, ombak yang bersenandung damai.
Namun, suara itu pecah oleh deru mesin yang menggali rahim bumi. Apa yang semula “surga kecil jatuh ke bumi” perlahan menjelma menjadi neraka ekologis—air jernih yang keruh, karang yang patah, tanah yang berdarah.
Acil Daat, dengan lirih, menyingkap luka yang tak tertutup kata-kata pembangunan.
Inilah puisi yang lebih dari sekadar karya sastra: ia adalah testimoni, saksi sejarah, dan jeritan hati kolektif.
-000-
Membaca puisi itu, saya teringat banyak buku yang mencoba menjelaskan hal ihwal luka Papua.
Puisi itu hanyalah serpihan dari mozaik luka Papua yang lebih luas. Sejak lama para peneliti, aktivis, dan sastrawan menuliskan paradoks besar: tanah Papua kaya raya, tetapi rakyatnya miskin dan menderita.
Aneka buku itu menguraikan dengan terang empat luka mendasar Papua:
1. Marginalisasi dan diskriminasiOrang asli Papua dipandang berbeda, kerap diremehkan, bahkan dilukai dengan stigma yang menyayat martabat.
Migrasi besar-besaran sejak Orde Baru menimbulkan rasa terpinggirkan: di kota, orang Papua justru menjadi minoritas di tanahnya sendiri.
2. Kegagalan pembangunanTriliunan rupiah dana otonomi khusus mengalir, namun sekolah tetap reyot, rumah sakit tetap jauh, dan anak-anak tetap kekurangan gizi.
Indeks Pembangunan Manusia Papua paling rendah di Indonesia. Pembangunan fisik memang tampak, tetapi pembangunan manusia gagal.
3. Kekerasan politikDemonstrasi sering dijawab dengan peluru. Ingatan tentang operasi militer, penangkapan, penyiksaan, dan orang hilang menorehkan trauma yang diwariskan lintas generasi.
4. Sejarah politik yang belum selesaiPepera 1969 bagi Jakarta sah, tetapi bagi banyak orang Papua adalah luka. Rasa dipaksa masuk ke Indonesia menciptakan bara api yang tak padam.
Empat luka ini saling terkait. Buku Papua Road Map karya LIPI misalnya, juga memperingatkan tentang kutukan sumber daya.
Kekayaan alam Papua tidak hanya gagal membawa kemakmuran, tetapi justru memperparah ketidakadilan.
Freeport menghasilkan emas dan tembaga yang menyumbang besar pada APBN, namun kampung-kampung Papua tetap gelap tanpa listrik.
Gas dijual ke luar negeri, tapi banyak mama-mama Papua tetap memasak dengan kayu bakar.
Apa yang bagi negara disebut “kemajuan” justru dihayati rakyat Papua sebagai perampasan: tanah adat yang digusur, hutan sagu yang ditebang, laut yang rusak oleh tumpahan tambang.
Ketika identitas dan sumber hidup dicabut, pembangunan berubah menjadi bentuk kolonialisme baru—dengan wajah modern, tetapi luka yang sama dalamnya.
Karena itu, jalan keluar tak bisa hanya proyek infrastruktur atau transfer dana. Rekonsiliasi adalah kata kunci.
• Rekonsiliasi dengan sejarah: mengakui bahwa masa lalu menyimpan luka.
• Rekonsiliasi dengan masyarakat: mendengar, bukan sekadar memerintah.
• Rekonsiliasi dengan alam: membangun yang berkelanjutan, bukan merusak.Damai di Papua hanya lahir bila martabat dipulihkan. Tanpa pengakuan atas identitas dan hak orang Papua, pembangunan hanya menjadi hiasan yang rapuh.
-000-
Buku Melihat Papua dari Ufuk Timur Indonesia, antologi karya 20 penulis dari Satupena Papua, hadir untuk mengisi ruang batin yang tak tersentuh data statistik.
Victor Manengkey, koordinator Satupena Papua sekaligus editor buku ini, membuka pengantarnya dengan bahasa penuh kontemplasi: Papua adalah “surga kecil yang jatuh ke bumi.”
Setiap puisi di dalam buku ini menjadi denyut nadi yang mencatat luka sekaligus harapan.
Victor menegaskan, anak-anak Papua menulis bukan sekadar rangkaian kata. Mereka menulis dari hutan yang ditebang, dari laut yang keruh.
Juga menulis dari air mata mama-mama yang berdagang di pasar, dari tarian Yospan yang menyimpan identitas, hingga dari tifa yang berdentum sebagai penanda eksistensi.
Selain puisi Tambang di Raja Ampat karya Acil Daat, antologi ini memuat karya-karya lain yang menyingkap wajah Papua.
Ada Daniel Eluay yang menulis tentang Gunung Cyclops, ada Aleks Giyai dengan Monolog Bumi Terjarah, ada Weynand Christovanly yang menulis Papua-ni, sebuah pengakuan cinta sekaligus luka terhadap tanah leluhur.
Tema-tema yang muncul bukan sekadar keindahan alam, tetapi juga kritik sosial, doa-doa sederhana anak kampung, dan renungan tentang masa depan yang terus dicari.
Puisi-puisi itu berjumlah sekitar 120 judul: sebuah orkestra suara yang menolak bungkam.
-000-
Membaca puisi-puisi ini, berpadu dengan analisis riset, kita sampai pada kesadaran pahit: Papua adalah cermin bangsa Indonesia itu sendiri.
Apa arti kemerdekaan bila sebagian anak bangsa masih merasa dijajah di rumahnya sendiri? Apa arti pembangunan bila jalan raya mulus menuju tambang, tetapi anak-anak Papua tetap berjalan kaki ke sekolah tanpa buku?
Apa arti persatuan bila stigma dan diskriminasi terus diwariskan dari mulut ke mulut?
Papua adalah luka yang belum dijahit. Tetapi sekaligus, Papua adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar rumah bagi semua, bukan hanya bagi mayoritas.
Kesempatan untuk menyalakan rekonsiliasi, bukan dengan proyek mercusuar, melainkan dengan keberanian mengakui luka, mendengar jeritan, dan memberi ruang setara bagi identitas Papua.
Antologi Melihat Papua dari Ufuk Timur Indonesia menjadi obor kecil yang dinyalakan oleh para penulis Papua.
Obor itu mungkin tak mengubah kebijakan tambang, tak menghentikan kekerasan, tak menutup luka sejarah. Tapi obor itu menyalakan kesadaran kita: bahwa ada suara dari timur yang tak boleh padam.
Suara itu adalah suara anak pulau yang berbisik: “emas bagi negeri, tapi merampas masa depan.”
Suara itu adalah suara mama-mama Papua di pasar, suara tifa yang berdentum di malam pesta adat, suara burung cenderawasih yang tetap bernyanyi meski hutan kian gundul.
Apabila bangsa ini ingin benar-benar berdiri tegak di atas pilar keadilan, ia harus berani menoleh ke timur, mendengar suara luka dari Papua, dan menjadikannya suara kita bersama.
Karena sesungguhnya, di ufuk timur itu bukan hanya Papua yang sedang menanti. Di sana, yang menanti adalah kemanusiaan kita sendiri.***
Singapura, 2 Oktober 2025
Referensi
1. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future of Papua – Tim Peneliti LIPI (2009).
2. Tanah Papua yang Luka: Sejarah, Kekerasan, dan Jalan Damai – Adriana Elisabeth (2011).-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World