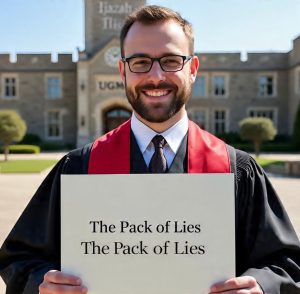Oleh ReO Fiksiwan
“Pada awalnya adalah hubungan… Ketika seseorang berhubungan dengan dunia sebagai Engkau, ia berdiri dalam hubungan dengan Tuhan.” — Martin Buber (1887-1965), Ich und Du (1923).
HATIPENA.COM – Teologi Yahudi, yang selama ribuan tahun berakar pada pengalaman diaspora, penderitaan, dan harapan mesianik, mengalami transformasi radikal ketika bertemu dengan gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19.
Dalam perjumpaan ini, spiritualitas yang sebelumnya bersifat eskatologis dan transenden mulai dikonversi menjadi proyek politik dan teritorial.
Roger Garaudy (1913-2012) dalam The Case of Israel: A Study of Political Zionism (1985;1988) menyebut bahwa Zionisme bukan kelanjutan dari tradisi Yahudi, melainkan sebuah mutasi ideologis yang memanfaatkan simbol-simbol agama untuk membenarkan kolonisasi dan eksklusi.
Zionisme, dalam bentuknya yang paling agresif, menjadikan tanah sebagai dogma dan kekuasaan sebagai liturgi baru, menggeser makna eksil sebagai ruang kontemplatif menjadi trauma yang harus dibalas dengan dominasi.
Dalam The Hidden History of Zionism (1988), Livia Rokach (1935-1984), seorang jurnalis dan aktivis asal Israel yang dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan militer dan ekspansionis Israel, mengungkap dokumen dan pernyataan dari tokoh-tokoh Zionis awal, termasuk Moshe Sharett, untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap warga Palestina bukanlah reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi sistematis.
Dengan kata lain, ia mengungkap bagaimana proyek negara Israel dibangun di atas narasi penderitaan yang dikapitalisasi untuk legitimasi politik.
Teologi Yahudi yang semula menekankan keadilan, belas kasih, dan pengharapan kini dibingkai ulang sebagai pembenaran atas tindakan militer dan ekspansi wilayah.
Dalam konteks ini, malaikat tidak lagi menjadi utusan damai, tetapi metafora bagi drone dan rudal yang dikirim atas nama keamanan.
Ketika Israel berperang sejenak dengan Iran dan terus melanjutkan konflik dengan Palestina, kita menyaksikan bagaimana teologi yang seharusnya menjadi sumber etika berubah menjadi instrumen geopolitik.
Proposal perdamaian dari Presiden Amerika, Donald Trump (79), yang dikenal sebagai “Deal of the Century,” justru memperkuat logika eksklusi dan peneguhan status quo, bukan rekonsiliasi yang berakar pada nilai-nilai profetik Yahudi.
Max I. Dimont (1912-1992) dalam Yahudi, Tuhan, dan Sejarah (2018) dan The Indestructible Jews (2010) menulis bahwa kekuatan Yahudi terletak pada kemampuan mereka bertahan dalam sejarah yang penuh luka.
Namun, daya tahan itu kini dikaburkan oleh proyek Zionisme yang menjadikan penderitaan sebagai alat politik, bukan sebagai sumber empati universal.
Dimont menekankan bahwa Yahudi bertahan bukan karena senjata, tetapi karena ide—ide tentang keadilan, pengampunan, dan dialog.
Ketika Israel mengabaikan nilai-nilai ini demi supremasi teritorial, maka yang terjadi bukan penggenapan nubuat, melainkan pengkhianatan terhadap akar spiritual mereka sendiri.
Simon Schama (80), profesor sejarah dan sejarah seni di Columbia University, dalam The Story of the Jews: Finding the World (2013) dan Simon Sebag Montefiore (60), sejarawan, novelis, dan jurnalis, dalam Jerusalem: The Biography (2012) menunjukkan bahwa sejarah Yahudi adalah sejarah keterbukaan, perjumpaan, dan transformasi. Yerusalem, kota yang menjadi jantung spiritual tiga agama besar, kini menjadi simbol eksklusi dan kekerasan.
Teologi Yahudi yang semestinya mengajarkan bahwa tanah adalah titipan, bukan milik mutlak, telah digantikan oleh Zionisme yang memandang tanah sebagai hak eksklusif dan absolut.
Dalam tubuh negara Israel, teologi Yahudi telah mengalami sekularisasi yang ekstrem: Tuhan dipanggil hanya untuk membenarkan perang, bukan untuk membangun perdamaian.
Refleksi ini bukan penolakan terhadap hak hidup bangsa Yahudi, melainkan kritik terhadap distorsi spiritual yang terjadi ketika agama dijadikan alat politik.
Teologi Yahudi yang sejati tidak membenarkan penindasan, tidak merayakan eksklusi, dan tidak mengabaikan penderitaan orang lain.
Ketika Israel terus membangun tembok, memperluas pemukiman, dan menolak hak kembali rakyat Palestina, maka yang terjadi bukan penggenapan janji Tuhan, tetapi pengkhianatan terhadap pesan para nabi.
Teologi Yahudi di tubuh Zionisme Israel hari ini bukan lagi suara langit, melainkan gema dari ambisi duniawi yang kehilangan arah spiritualnya. (*)
#coversongs: Lagu „Osse Shalom“ dari The Jewish Starlight Orchestra dirilis pada 27 Mei 2014, dalam album Traditional Jewish Music and Songs(The Best of Yiddish Songs).
Osse Shalom(Oseh Shalom) adalah lagu tradisional Yahudi yang berasal dari bagian akhir doa Kaddish dan merupakan doa untuk perdamaian universal, baik di langit maupun di bumi.
Dalam tradisi Yahudi, frasa ini mencerminkan harapan bahwa Tuhan, yang menciptakan harmoni di alam semesta, juga akan menghadirkan kedamaian di antara umat manusia.
Lagu ini sering dinyanyikan dalam ibadah, peringatan, dan momen reflektif, sebagai simbol kerinduan akan rekonsiliasi dan ketenangan batin.