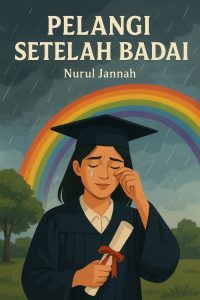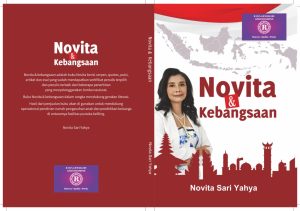LK Ara
HATIPENA.COM – Sore berwarna kopi di sudut kafe kecil, meja kayu, lampu kuning temaram, dan asap rokok yang perlahan melayang di udara. Di pojok, seorang lelaki duduk dengan kemeja putih kusut — Chairil Anwar. Aku duduk di depannya, membawa catatan kecil.
Aku:
“Selamat sore, Bang Chairil. Terima kasih sudah mampir ke sini… di sela-sela perjalanan panjangmu.”
Chairil Anwar:
(tersenyum tipis)
“Ah, aku memang tak pernah benar-benar pergi.”
Aku:
“Banyak orang mengenangmu setiap Hari Puisi, Bang. Rasanya, puisimu tetap hidup, meski kau sudah pergi jauh. Apa kau pernah membayangkan akan sebesar ini?”
Chairil Anwar:
(menghembuskan asap pelan)
“Aku menulis bukan untuk dikenang. Aku menulis untuk hidup. Untuk mengerang, untuk menjerit, untuk tertawa… Semua itu hidup dalam kata.”
Aku:
“Kalau melihat anak-anak muda zaman sekarang, yang menulis puisi di media sosial, dengan berbagai gaya, apa pendapatmu?”
Chairil Anwar:
(menyeringai)
“Bebas. Puisi itu harus bebas. Tak peduli di kertas buram atau layar ponsel. Yang penting, ada nyawa di dalamnya.”
Aku:
“Bang, dulu katanya kau menulis di tengah lapar, di tengah hidup yang keras. Apa itu membuat puisimu lebih dalam?”
Chairil Anwar:
(tertawa pendek)
“Lapar, cinta, marah, rindu — semua itu guru yang kejam tapi jujur. Kalau kau kenyang terus, kadang kata-kata jadi malas.”
Aku:
“Bang Chairil, kalau malam-malam kami kehabisan kata, kehabisan semangat, apa yang harus kami lakukan?”
Chairil Anwar:
(tersenyum simpul)
“Pergi keluar. Dengarkan angin. Dengarkan suara jalanan. Kadang kata-kata tersembunyi di antara langkah orang-orang yang pulang.”
Aku:
“Bang, menurutmu puisi itu lebih baik ditulis untuk diri sendiri atau untuk orang lain?”
Chairil Anwar:
“Untuk diri sendiri dulu. Kalau tulus, nanti orang lain ikut merasa. Puisi yang pura-pura hidup hanya akan jadi debu.”
Aku:
“Kalau suatu hari puisi tidak lagi dihargai, tidak dibaca, apakah kau akan tetap menulis?”
Chairil Anwar:
(mengepalkan tangan di atas meja)
“Puisi bukan soal dihargai atau tidak. Puisi itu kebutuhan, seperti bernafas. Aku akan tetap menulis, meski dunia diam membatu.”
Aku:
“Akhirnya, Bang… kalau ada satu baris yang bisa kau wariskan untuk kami semua, satu saja, apa itu?”
Chairil Anwar:
(menatap lekat-lekat)
“‘Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang…’ Tapi ingat, jalang bukan berarti liar tanpa arah. Jalang artinya merdeka memilih jalan sendiri.”
Akhir wawancara:
Di luar, hujan mulai turun perlahan. Chairil menghabiskan kopinya, lalu berdiri, melambaikan tangan sambil menghilang ke dalam gerimis.
Penutupan:
Aku duduk sejenak, merenungi kata-kata yang baru saja terucap. Suasana kafe yang semakin sepi, hujan yang semakin deras, dan suara Chairil yang seolah terus bergema dalam batin. Puisi memang tak pernah benar-benar mati. Mereka hidup di setiap kata yang berani kita tulis.