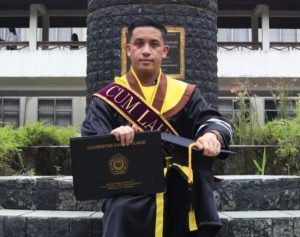Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
HATIPENA.COM – Saya belum pernah naik Whoosh. Belum sempat selfie di kursi empuknya, belum merasakan melesat 350 km/jam sambil menyeruput kopi, eh… yang menyeruak malah kabar, rugi besar.
Gimane ceritenye, Bang? Sepanjang 2024, proyek ini bikin KAI tekor Rp 2,69 triliun. Masuk semester I 2025, tambah lagi Rp 951,48 miliar. Total setahun lebih, tembus Rp 1,9 triliun. Proyeksi 2026? Jangan kaget, Rp 6 triliun. Kalau rugi punya sayap, pasti dia sudah terbang keliling dunia sambil tertawa keras.
Padahal investasinya bukan recehan, US$ 7,2 miliar alias Rp 116,5 triliun. Belum cukup? Ada bonus cost overrun US$ 1,2 miliar (Rp 19,4 triliun). Shinkansen di Jepang butuh waktu lama sampai balik modal. Whoosh di Indonesia? Baru setahun, sudah balik rugi.
Nah, di sinilah misteri besar negeri ini. Kenapa BUMN selalu identik dengan rugi? Padahal, banyak yang monopoli. PLN satu-satunya penjual listrik, tetap bisa tekor. Pertamina kuasai bensin dari Sabang sampai Merauke, tetap teriak rugi. Kini giliran KAI dengan Whoosh, melanjutkan tradisi, bikin kereta tercepat di Asia Tenggara, tapi defisit juga tercepat.
Apakah rugi itu nasib, atau strategi? Saya kok curiga, ini bagian dari “nyanyian rugi” setiap kali RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPR. Setiap direksi datang, syairnya sama, “Kami rugi, tolong tambah anggaran.” Dewan mendengar, mengangguk, lalu anggaran turun. Sungguh duet klasik, direksi mendendangkan kerugian, DPR memberi aplaus dengan stempel persetujuan.
Logikanya aneh. Kalau kita pedagang warung rugi, kita evaluasi resep, atau tutup toko. Tapi kalau BUMN rugi, yang muncul malah konferensi pers, janji manis, dan proposal penambahan modal. Kerugian bukan aib, justru jadi tiket masuk ruang anggaran.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin menyebut, proyek ini “bom waktu”. Tapi sebetulnya lebih cocok disebut gong waktu. Setiap tahun dipukul, bunyinya keras, duuum! Lalu pejabat bergantian bicara soal restrukturisasi. Danantara, holding BUMN baru, masuk sebagai pawang bom, padahal mungkin hanya ganti baterai jam weker.
Filosofinya begini, untung itu berlari kecil, pakai sendal jepit. Sementara rugi naik Whoosh, ngebut 350 km/jam. Itulah kenapa untung jarang sampai ke meja rapat, tapi rugi selalu hadir, pakai jas rapi, sambil membawa proyeksi miliaran hingga triliunan.
Masyarakat awam cuma bisa geleng-geleng. Kursi Whoosh kosong lebih banyak dari penumpang warung pecel lele, tapi di atas kertas, narasi tetap sama, “tenang, ini investasi masa depan.” Masa depan siapa? Masa depan generasi yang harus bayar cicilan?
Namun mari kita akui, Whoosh tetap epik. Inilah kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Sebuah monumen kecepatan, bukti kita bisa sejajar dengan Jepang dan Tiongkok. Bedanya, Shinkansen bikin untung, Whoosh bikin laporan rugi. Tapi di negeri kita, rugi justru jadi gaya hidup.
Kalau ada yang tanya, “Kenapa BUMN identik dengan rugi?” Jawabannya sederhana, karena rugi itu bukan masalah, melainkan metode komunikasi. Sebuah strategi. Satu-satunya bahasa yang efektif untuk membuka dompet negara.
Whoosh hanyalah bab terbaru dalam simfoni panjang bernama “Nyanyian Rugi” dan PLN pernah mendendangkannya, Pertamina rutin menyanyikannya, kini KAI melanjutkan dengan irama lebih cepat. Lalu, kita, rakyat, hanya jadi penonton konser.
Bedanya, tiket konser bisa ditolak. Tiket rugi BUMN? Mau tak mau, kita sudah beli lewat pajak.
Whoosh… rugi pun melesat cepat, sampai ke meja DPR.
Pesan moral dari kisah Whoosh ini sederhana tapi dalam, sebesar apa pun teknologi, secanggih apa pun proyek, kalau manajemen lebih sibuk membungkus kerugian sebagai “strategi” ketimbang mencari jalan keluar nyata, maka rakyat hanya akan jadi penonton setia konser rugi. Artinya, kemajuan sejati bukan sekadar seberapa cepat kereta melaju, tapi seberapa jujur dan bijak kita mengelola keuangan serta amanah publik. (*)
#camanewak