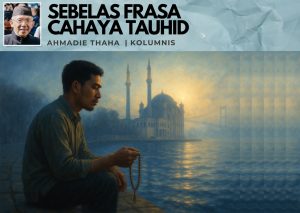Perjalanan Jiwa Orang-Orang yang Tak Terlihat
Antologi Puisi Sufi oleh Rizal Tanjung
Puisi I
Dunia yang Sibuk Menyamar
Tuhan berfirman di balik bayangan layar: “Wahai manusia yang mengecat wajahmu dengan cahaya semu, kenapa kau menari di atas panggung yang tak kau pilih?
Kau bukanlah piksel yang bersinar, tapi cahaya yang tak butuh layar.”
Dan manusia menjawab dalam kebisuan: “Aku hanya ingin diterima, walau harus menghilang.”
Lalu Tuhan berbisik, “Yang hilang tak pernah kutinggalkan. Kau sembunyi di balik topeng, tapi Aku tetap melihat wajahmu.”
Puisi II
Panggung dan Topeng
Di ruang kelas, engkau dilatih bukan untuk menemukan, tapi meniru. Bukan untuk menjadi hening, tapi menjadi hafalan.
Tuhan bertanya dalam detik sunyi: “Apakah kau masih mengingat wajahmu sendiri, kala dunia memberimu topeng bertingkat?”
“Lepaskanlah itu, wahai jiwa, dan datanglah padaku dalam tangis. Biar Aku peluk dirimu yang gagal, bukan dirimu yang sempurna.”
Puisi III
Sunyi yang Menyimpan Kejujuran
Dalam sepi, cermin kamar mandi berubah jadi kitab wahyu. Bukan ayat-ayat yang tertulis, tapi kerut dan kantung mata menjadi tafsir hidup.
Sunyi adalah bahasa yang Tuhan pakai tatkala dunia terlalu bising.
Ia bertanya: “Masihkah engkau mendengarku, saat semua notifikasi memanggil lebih keras dari Aku?”
Dan manusia menjawab dalam hati: “Ya Rabbi, kau lebih dekat dari sinar layar. Dekat seperti gelisah yang tak bisa dijelaskan.”
Puisi IV
Kesibukan yang Menyamar sebagai Kehidupan
Engkau menyusun agendamu seperti salat yang dipercepat: rapat, tugas, proyek, panggilan.
Tapi Tuhan bertanya: “Wahai yang sibuk karena takut sunyi, kapankah kau menyentuh dadamu dan berkata: ‘Aku di sini, bukan hanya hadir.’”
Waktu bukan sekadar jam. Ia adalah taman tempat ruhmu tumbuh— jika kau sempat menyiraminya dengan diam.
Puisi V
Nilai yang Tak Bisa Dibeli
Tuhan tidak menciptakan ‘likes’. Ia menciptakan bara kecil di dadamu yang tak bisa dijual.
“Wahai jiwa, aku beri engkau cahaya yang menyala dalam hina. Tetaplah hidup walau diludahi dunia.”
Karena harga bukan di mata manusia, tapi di pandangan langit yang membaca keberanianmu, untuk tetap jujur walau sendiri.
Puisi VI
Suara Kecil yang Sering Dibungkam
Suara itu berkata: “Pulanglah.”
Tapi manusia menjawab dengan pekerjaan. Ia tumpuk lembar demi lembar agar tak terdengar panggilan sunyi.
Tuhan hanya menunggu. Ia tak mengetuk keras, hanya menggetarkan sedikit: dada, leher, air mata.
“Bila kau ingin Aku bicara lebih jelas, matikan lah dunia.”
Puisi VII
Masa Kecil sebagai Petunjuk Asal
Anak itu masih di dalam dirimu: yang menggambar matahari biru, bukan karena salah, tapi karena jiwanya belum dijajah konsep.
Tuhan berbisik melalui anak itu: “Jadilah seperti dia: yang melihat dunia bukan untuk dikuasai, tapi untuk dipeluk.”
Puisi VIII
Krisis sebagai Pintu Masuk
Saat segalanya hancur, itu bukan kutukan. Itulah suara Tuhan yang tak tahan melihatmu dipenjara pencapaian palsu.
“Aku runtuhkan menaramu agar kau melihat langit. Aku pecahkan cermimu agar kau menemukan wajahku dalam debu.”
Puisi IX
Retakan yang Menyala
Retak bukan tanda rusak. Ia adalah lubang di mana cahaya bisa masuk.
Tuhan tak hadir dalam sempurna, Ia hadir dalam lubang kecil yang kau tutupi selama ini.
“Biarkan Aku masuk melalui retakmu, supaya kau tahu: kesucian bukanlah tanpa cela, tapi menerima cahaya lewat luka.”
Puisi X
Diam sebagai Doa
Doa bukanlah daftar keinginan. Ia adalah keheningan yang mendengar Tuhan bicara kembali.
“Duduklah,” kata-Nya, “Bersamaku. Biar waktu larut, biar dunia lalu, Aku ingin engkau diam bersamaku saja.”
Dan diam itu berubah menjadi tasbih.
Puisi XI
Menjadi yang Tak Ditunjuk
Di gua kecil peradaban, seseorang duduk tanpa nama, bukan karena kalah, tapi karena tak ingin dipuja.
Tuhan mendekat lewat debu: “Yang kusebut dalam kitab-Ku bukan yang dielu-elukan, tapi yang menyembah-Ku saat tak dilihat.”
Tak terlihat bukan berarti tak bermakna. Tuhan hadir dalam getar sunyi yang tak dimuat berita.
Puisi XII
Melamun sebagai Revolusi
Saat dunia berlari, ia duduk di taman jiwa, memandang langit.
Tuhan berbisik: “Berpikir adalah ibadah yang tak berbunyi. Dan diam yang merenung adalah perlawanan terhadap dunia yang terburu.”
Melamun bukan malas, tapi jalan pulang yang tertutup semak agenda.
Puisi XIII
Cermin Tanpa Nama
“Siapa aku?” Ia bertanya bukan pada manusia, tapi pada luka.
Dan Tuhan menjawab: “Kau adalah keberanian untuk melihat tanpa topeng. Kau adalah nama yang kutulis di balik dinding rahasia.”
Cermin tak beri nama, tapi memantulkan keberanian.
Puisi XIV
Menolak Menjadi Fotokopi
Tuhan tak menciptakan duplikat. Ia meniupkan roh berbeda pada tiap jiwa.
“Jangan kau salin hidup orang,” kata-Nya. “Karena Aku menciptakanmu sebagai satu syair utuh. Bukan catatan kaki dari buku orang lain.”
Puisi XV
Cahaya yang Tak Ingin Dilihat
Ada cahaya dalam dada. Bukan untuk ditampilkan, tapi untuk dinikmati bersama Tuhan.
“Buka baju gelarmu,” kata-Nya. “Datang padaku sebagai jiwa, bukan jabatan.”
Cahaya tak butuh sorot. Ia butuh ketulusan untuk tinggal.
Puisi XVI
Surat dari Diri yang Hilang
Dalam mimpi, ia membaca surat berdebu: “Kau terlalu sibuk menjadi siapa-siapa, padahal aku tetap duduk di sini.”
Tuhan mengirim pesan bukan lewat email, tapi lewat rasa bersalah, rindu, dan tangis yang tak dimengerti.
“Diri sejati tak pernah pergi,” kata-Nya. “Hanya menunggu disapa.”
Puisi XVII
Jatuh sebagai Berkah
“Engkau jatuh bukan karena Aku benci,” kata Tuhan. “Tapi karena engkau lupa darimana kau berasal.”
Bumi memeluk bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan: bahwa kemuliaan bukan di atas, tapi di pelukan tanah.
Puisi XVIII
Jalan Pulang Tak Ada di Peta
Peta hanya tahu tempat, tapi jiwa tahu arah.
Tuhan berkata: “Arah bukan ditunjuk, tapi dirasakan. Dan kadang, jalan pulang bukan ke depan— tapi ke dalam.”
Puisi XIX
Sunyi, Sebelum Segala Nama
Sebelum kau disebut siapa-siapa, kau adalah diam.
Tuhan menciptakan semesta dari sunyi, bukan dari sorak.
“Datanglah padaku seperti sebelum kau diberi nama: tanpa label, tanpa peran. Hanya sebagai ruh yang ingin pulang.”
Puisi XX
Hidup sebagai Doa Tanpa Suara
Engkau tak perlu berbicara agar Aku mengerti. Tak perlu menangis keras agar Aku tahu.
“Jika engkau hidup jujur pada getaran jiwamu, maka seluruh hidupmu adalah doa.”
Dan ketika tubuhmu kupanggil pulang, Aku hanya akan bertanya: “Apakah engkau setia pada cahaya yang kutanamkan di dadamu?”
Karena keaslian adalah satu-satunya bahasa yang dikenang langit. (*)
Sumatera Barat, 2025